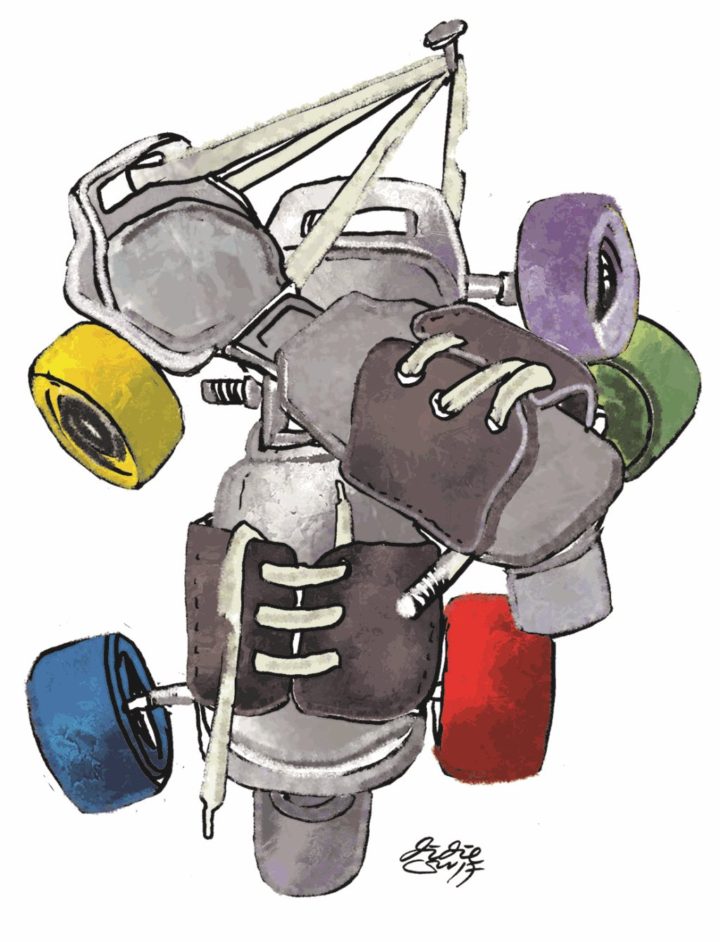
Membaca kembali uraian ilmuwan politik Indonesia generasi pertama Deliar Noer, sampailah kita pada kalimat, "Pemunculan pemimpin hanya mungkin dengan adanya kebebasan". Kalimat itu muncul dalam bukunya, Membincangkan Tokoh-tokoh Bangsa (2001). Apa yang disinyalir doktor ilmu politik lulusan Universitas Cornell ini tidaklah keliru dalam konteks demokrasi.
Kita dapat membacanya dalam pengertian bahwa tantangan pemunculan pemimpin di alam ketidakbebasan berbeda dengan dalam suasana demokrasi. Di era kebebasan seharusnya kita lebih mudah menghadirkan pemimpin. Namun, justru ketika kita masuk dan berada di era demokrasi, problem pengaderan tidak semulus bayangan semula. Tak mudah menghadirkan pemimpin bangsa.
Iklim kebebasan telah direspons oleh munculnya berbagai partai politik. Hal yang lazim ini mengingatkan masa awal kemerdekaan ketika partai-partai berkembang dalam corak ideologisnya. Pola pengaderannya pun bernuansa ideologis.
Deliar Noer mencatat mengemukanya pola kepemimpinan masa revolusi pasca-kemerdekaan, di mana calon-calon pemimpin harus melewati fase magang atau latihan. Dedikasi pada partai atau organisasi pun menguat. Para tokoh masa magang itu berbeda dengan para seniornya yang telah ditempa ujian politik sebelum kemerdekaan. Pola magang bertujuan menguji kesetiaan sekaligus peningkatan kapasitas politik. Partai-partai berlomba menghadirkan kader unggulan dalam kontestasi ataupun mengisi jabatan publik.
Namun, sejarah kepolitikan Indonesia yang begitu dinamis di era Demokrasi Parlementer berubah ke fase-fasenya yang relatif statis pada Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru. Peran sentral negara, kalau bukan elite kekuasaan, sangat memengaruhi pola pengaderan politik di partai-partai dan masyarakat. Iklim ketidakbebasan tidak menjamin munculnya sosok pemimpin independen, kecuali yang serestu sentral elite kekuasaan. Pada masa Orde Baru pendekatan korporatis diterapkan. Pewadahtunggalan berbagai kegiatan dan profesi dilakukan agar mereka mudah dikontrol negara. Seleksi kepemimpinan hampir selalu melalui campur tangan negara.
Kendati demikian, antitesisnya muncul justru dari ranah masyarakat sipil (civil society). Ruang kebebasan yang sempit mampu memicu kepemimpinan perlawanan. Namun, mereka sekadar kelompok penekan yang marjinal. Negara terlalu kuat masa itu kendati akhirnya masyarakat sipil mampu mendorong perubahan politik ke era reformasi. Dampak sentralitas elite kekuasaan dan kuatnya negara Orde Baru yang mampu membentuk kultur pengaderan politik sesuai caranya masih kuat di era kebebasan dewasa ini.
Paradoks
Apa yang kita jumpai sekarang masih diwarnai paradoks. Era kebebasan sudah terjadi, tetapi pengaderan tidak optimal. Apabila dibandingkan dengan pola kepemimpinan masa revolusi yang berpola magang, nyaris hal itu tidak begitu penting lagi kini.
Para elite partai menganggap pengaderan penting, tetapi mereka lebih meyakini hukum pasar. Dalam konteks kontestasi, kader internal sering kali tidak dianggap penting manakala terdapat tokoh luar atau dari partai lain yang direkomendasikan lembaga survei lebih tinggi elektabilitasnya.
Kalau dulu, dedikasi dan loyalitas itu penting dilakukan kader ke partai, lantas partai pun konsisten dalam memberikan insentif politik, pun tak takut kalah dalam kontestasi karena barisannya kuat, sekarang nyaris tidak penting lagi. Banyak kasus memberi tahu publik bahwa aspek dedikasi dan loyalitas yang telah dipenuhi oleh kader partai tidak memperoleh balasan yang sepadan dari elite kekuasaan partai yang berpola pikir pasar.
Elite itu tidak siap kalah dalam kontestasi, lantas sengaja mendukung kader lain yang tidak terkait dengan aspek dedikasi dan loyalitas. Pola pikir pragmatis itulah yang dominan.
Desakralisasi partai
Ada masalah pokok yang diabaikan di sini, ketika ideologi atau setidaknya identitas politik partai tidak lagi dianggap penting. Kini telah terjadi desakralisasi partai dari alat perjuangan ideologis menjadi sekadar kendaraan politik untuk tujuan praktis kekuasaan.
Kekuasaan hanya perlu diraih dan dibagi-bagi untuk memberlangsungkan pembangunan yang nyaris hanya bisa berjalan apabila struktur insentifnya kuat. Yang berkuasa harus pandai-pandai membuat struktur insentif, membagi-bagi ke seluruh pendukung agar stabilitas politik internal terjaga.
Tidak adanya tradisi oposisi politik yang kuat karena budaya dan sistem juga turut berpengaruh pada pola pengaderan dewasa ini. Kekuatan-kekuatan politik di luar atau di dalam pemerintahan rata-rata punya tradisi pengaderan yang sama. Jawaban cukup mudah untuk menjelaskannya, itu semua dampak sistem. Sistemlah yang membuat para elite politik tidak punya pilihan lain selain melakukan hal-hal yang klise dalam politik praktis. Karena ongkos dalam suatu praktik politik non-ideologis dewasa ini begitu mahal, mereka dituntut pandai-pandai beradaptasi.
Apakah gejala demikian menandai krisis pengaderan politik bangsa? Ataukah sekadar fenomena perbedaan pola pengaderan akibat tuntutan yang berbeda? Bahwa telah terjadi krisis pengaderan partai mungkin cukup tepat kendati bisa identik krisis pasokan pemimpin bangsa. Akan tetapi, harus diakui bahwa tuntutan kepartaian dewasa ini berbeda dengan masa lalu.
Partai-partai di Indonesia sudah masuk fase ketiga, fase persaingan atau kontestasi pragmatisme kalkulatif, bukan lagi perjuangan ideologis (fase pertama) dan fase pembangunan yang berpusat negara.
Fase masa kini punya peluang dan konsekuensinya. Karena bukan entitas yang dipandang sakral atau sangat ideologis, dan secara tuntutan harus mampu bersikap terbuka, partai berpeluang akomodatif bagi hadirnya kepemimpinan yang bersumber masyarakat. Sumber-sumber kepemimpinan masa kita bisa menjadi sangat luas, tak hanya penyedia magang di partai maupun organisasi nonpartai, tetapi juga individu-individu kreatif yang hadir dari tradisi era digital baru. Masalah pengaderan politik bangsa pun harus menjadi tanggung jawab bersama.
M ALFAN ALFIAN

Tidak ada komentar:
Posting Komentar