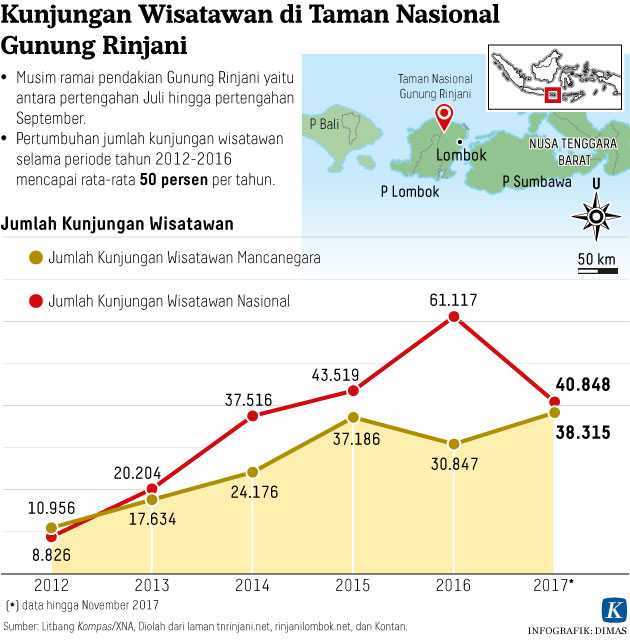Tahun 2004, John E Lewis, Asisten Deputi Direktur FBI, mengatakan ada ancaman serius dari teroris dalam negeri. Mereka individu maupun organisasi lingkungan yang ekstrem dalam menyelesaikan persoalan.
Menurut FBI, ada dua lembaga teroris domestik: Animal Liberation Front (ALF) dan The Earth Liberation Front (ELF). Kedua lembaga ini tidak sungkan menggunakan kekerasan dalam memperjuangkan hak-hak hewan.
ALF, misalnya, tidak segan-segan menarget produsen makanan, peneliti biomedis, bahkan penegak hukum dengan kekerasan fisik. Tahun 2003, personel ALF memasang alat peledak rakitan di perusahaan pengujian produk konsumen dengan hewan.
Tentu saja tindakan ALF yang menyebabkan kerusakan dan kematian itu sangat tidak dapat dibenarkan. Namun, di sisi lain, ada fenomena menarik dalam hal tingginya kesadaran sebagian warga AS untuk memperjuangkan hak-hak kehidupan hewan.
Para aktivis ALF dan ELF rela dicela, kehilangan pekerjaan, bahkan dihukum untuk memperjuangkan kelangsungan hidup hewan. Berbeda dengan Indonesia. Bagi sebagian masyarakat, keberadaan hewan, apalagi yang liar, adalah ancaman dan dagangan. Mereka diburu dan dibunuh. Kematian Bunta, gajah jinak di lokasi Conservation Response Unit (CRU) Serbajadi, Aceh Timur, salah satu buktinya.
Teroris lingkungan
Kematian Bunta menambah daftar panjang pembunuhan terhadap satwa liar. Dalam 10 tahun terakhir, konflik manusia-satwa liar merupakan titik kritis bagi kelangsungan hidup banyak spesies yang terancam punah, khususnya harimau sumatera dan singa asia. Namun, yang kurang terancam punah, seperti macan tutul salju, monyet merah, dan gajah sumatera, juga terancam. Di wilayah Leuser, Aceh, setiap tahun rata-rata terjadi 40 kasus konflik gajah dengan warga, diakhiri dengan kematian 31 ekor gajah (BKSDA Aceh 2015).
Banyak yang berpendapat, perusakan dan penghancuran lingkungan alam yang menyebabkan gangguan hingga kematian makhluk hidup dapat dikategorikan terorisme lingkungan (environmental terrorism). Meskipun demikian, pelabelan teroris untuk kejahatan lingkungan tidaklah mudah. Dalam "Kamus Terorisme" sekurang-kurangnya terdapat lebih dari 70 definisi, mulai dari penggunaan kekerasan terhadap individu yang tidak bersalah karena alasan politik hingga "alat kekerasan politik untuk mendapatkan perhatian, pengenalan, dan keterpilihan" (Thackrah, 2004).
Elizabeth Chalecki dalam "A New Vigilance: Identifying and Reducing the Risks of Environmental Terrorism" membedakan antara terorisme lingkungan dan eko-terorisme.
Terorisme lingkungan ia artikan sebagai penggunaan kekuatan melawan hukum terhadap sumber daya lingkungan di dalam kawasan (in situ) yang berdampak mengurangi, merusak ekosistem serta kemanfaatannya, dan atau menghancurkan properti lain. Sasaran terorisme lingkungan adalah sumber daya alam dan flora/fauna di dalamnya. Pembunuh Bunta masuk golongan ini.
Sementara eko-terorisme adalah tindakan penghancuran properti demi kepentingan menyelamatkan lingkungan dari perambahan manusia. Eco-terorisme membidik berbagai sarana seperti jalan, bangunan, dan infrastruktur lain dalam mempertahankan sumber daya alam.
Fokus pada SDA
Di tingkat internasional pembahasan tentang teroris lingkungan telah berkembang dengan fokus pada identifikasi risiko yang akan terjadi terhadap sumber daya alam. Bahkan
muncul pendapat di kalangan militer bahwa serangan atau gangguan terhadap sumber daya alam bukan saja menyebabkan lebih banyak kesulitan penghidupan pada manusia, tanaman dan satwa, melainkan juga kerusakan properti, kekacauan politik, hingga gangguan kelangsungan pembangunan dan perubahan iklim.
Istilah teroris muncul tahun 1790-an ketika Partai Jacobin bertindak represif dalam revolusi Perancis. Ironisnya, tindakan ini untuk mendukung keadilan, kesetaraan, dan demokrasi.
Setelah dua abad, istilah teroris bermetamorfosis dalam konteks perusakan lingkungan atau sumber daya alam meski aksi dan praktik teroris lingkungan sudah berlangsung sejak
Perang Dunia II. Tahun 1944 pasukan Jerman membanjiri 200.000 hektar lahan Belanda sehingga warganya gagal bercocok tanam.
Di samping itu, aksi teroris lingkungan pada dasarnya tidak hanya dilakukan individu, kelompok, dan perusahaan, tetapi juga negara. Contohnya ketika Pemerintah AS membolehkan pasukannya menggunakan 20 juta galon herbisida dosis tinggi untuk menghancurkan tanaman tutupan hutan tempat persembunyian pasukan Vietnam Utara.
Contoh lain adalah ketika Pemerintah Irak tahun 1991-2003 membangun drainase di "Madan" Marsh, yang menghilangkan ekosistem lahan rawa seluas 20.000 kilometer persegi yang merupakan mata pencaharian hampir 500 juta warga (Simon M Berkowicz, Environmental Security and Eco Terrorism, 2010).
"Ecocide"
Di Indonesia, tindakan perusakan sumber daya alam lingkungan berlangsung masif dalam berbagai bidang dan tingkatan. Dari perambahan hutan, perburuan satwa, pengeboman ikan dan terumbu karang, hingga pembakaran hutan dan pencemaran sungai. Dilakukan oleh warga, kelompok, perusahaan, bahkan tidak jarang mendapatkan dukungan legal aparat.
Sudah lama pula berbagai pihak mengklasifikasikan perusakan lingkungan ini sebagai bentuk aksi teroris bukan lagi kejahatan pidana atau perdata. Bahkan BPLHD Jabar mewacanakan perlunya lembaga khusus (Densus 99) yang menangani kelompok perusak lingkungan yang karakternya seperti teroris.
Tugas pokok dari wadah ini adalah memburu pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan, seperti pembakar hutan dan lahan, pembuang limbah industri, dan pelaku illegal logging.
Wacana BPLDH Jabar soal Densus 99 didasari pandangan bahwa kejahatan lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia tidak lagi cukup dilihat sebagai pelanggaran hukum semata. Terlebih dengan kurang efektifnya lembaga hukum mencegah dan menanggulangi kejahatan lingkungan sehingga menyuburkan perusakan lingkungan.
Banyak perkara pelanggaran lingkungan hidup, seperti pembakaran hutan, pencemaran limbah, penebangan liar, perusakan alam hayati, pengabaian hak-hak masyarakat adat, dan pelanggaran tata ruang, yang justru terhenti atau kalah di tingkat peradilan. Hal ini terlihat pada kasus putusan Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan, yang menolak gugatan pemerintah terhadap PT Bumi Mekar Hijau terkait kebakaran hutan dan lahan tahun 2014 dan 2015.
Studi World Resources Institute 2015 menunjukkan hilangnya tutupan pohon hutan primer Indonesia yang mencapai 55 persen atau 4,5 juta hektar akibat aktivitas perkebunan, pertambangan, dan penebangan kayu yang melebihi batas. Ironisnya, aktivitas ini dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan keterbatasan dari perundangan dan kebijakan, juga masyarakat biasa karena motif ekonomi maupun hak tradisionalnya. Situasi ini diperparah oleh ketimpangan dan ketidakadilan distribusi dan kontrol atas sumber daya alam yang
menyebabkan kemiskinan serta ketidakpuasan masyarakat lokal.
Tantangan pembangunan
Dapat dikatakan terorisme lingkungan merupakan tantangan serius dalam menunjang tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Tingkat kejahatan lingkungan sudah menempati urutan tertinggi di antara serangkaian ancaman keamanan trans-nasional pemerintah.
Sebagai contoh, dari semua kayu yang diproduksi di Indonesia, hampir 70 persen ditebang secara ilegal dan diduga melalui mekanisme perdagangan kayu (ekspor) bawah tanah antara Indonesia dan Malaysia. Kerugian negara diperkirakan 3 miliar dollar AS per tahun.
Dalam perkembangannya, pelaku kejahatan lingkungan tidak hanya dianggap sebagai teroris, tetapi juga termasuk tindakan ecocide karena merusak sumber daya alam secara intensif sehingga mengubah ekosistem.
Tahun 2010, Polly Higgins, pengacara bidang lingkungan, mengusulkan ke Komisi Hukum Internasional (ILC) agar kejahatan lingkungan dikategorikan sebagai ecocide.
Usulan dikenal dengan "Eradicating Ecocide" yang bertujuan mengubah statuta Roma agar menempatkan perusak lingkungan (ecocide) sebagai bagian dari kejahatan internasional yang dapat diadili Mahkamah Internasional. Dasar argumentasinya adalah kejahatan lingkungan merupakan bentuk tindakan yang mengganggu kemanusiaan, alam, dan generasi masa depan.
Kecenderungan global yang semakin keras menindak secara hukum perusakan dan kejahatan lingkungan (sumber daya alam) seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Indonesia.
Dalam situasi ketidakseimbangan antara intensitas kerusakan sumber daya alam dan lingkungan dengan keterbatasan dalam mencegah dan merehabilitasi, pemerintah dituntut menyiapkan langkah kebijakan dan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan agar kerusakannya tidak lebih parah.
Kematian Bunta diharapkan menjadi momentum itu. Jika tidak, kekayaan alam Indonesia tinggal legenda dan selanjutnya kita harus bersiap menerima bencana alam setiap saat.