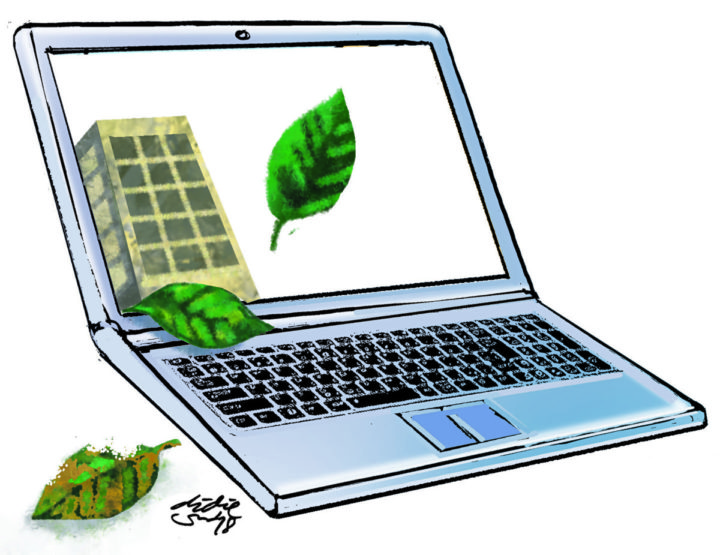
Kota-kota di Nusantara telah berlomba-lomba mengelola perikehidupan urban secara cerdas. Apalagi setelah Kemkominfo RI menggulirkan Gerakan Menuju 100 Smart City, sedikitnya 50 wali kota dan bupati menyatakan dukungan.
Dalam pembangunan kota cerdas (smart city), Menkominfo Rudiantara menekankan pemanfaatan teknologi informasi untuk melayani masyarakat. Menurut Rudiantara, kita harus mendefinisikan dulu manfaat apa saja yang akan diberikan kepada masyarakat dan baru mencari teknologi informasi yang relevan. Gerakan kota cerdas di satu sisi mendorong kota-kota menyelesaikan berbagai persoalan urban secara cerdas, di sisi lain memajukan potensi daerah secara cerdas pula.
Jerat pragmatisme
Secara antropologis, kota cerdas adalah sebuah kebudayaan. Koentjaraningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai kompleks sistem gagasan, sistem perilaku, dan benda-benda hasil karya manusia (budaya material) yang jadi milik diri melalui proses belajar. Perilaku serba digital dalam kota cerdas ditopang oleh budaya material berupa teknologi informasi dengan multi-aplikasinya yang semakin canggih.
Namun, sejauh ini, gagasan yang melandasi perilaku digital dan memotivasi penciptaan teknologi digital itu bersifat pragmatis. Alam pikir pragmatis menekankan pengutamaan kebermanfaatan, yaitu kebergunaan secara praktis semata. Manusia pragmatis tak mau repot-repot memikirkan soal kebenaran, sistem nilai, dan filsafat, apalagi hal-hal yang bersifat metafisis.
Pragmatriusme dalam pembangunan kota cerdas terlihat dari orientasinya untuk membuat hidup masyarakat semakin mudah, nyaman, senang, nikmat, sejahtera, dan bahagia. Jika pencapaian-pencapaian itu saja yang menjadi parameter keberhasilan, kota cerdas hanya akan menjadikan kota berteknologi cerdas, tetapi tidak berpenduduk cerdas. Sebab, cerdas itu lebih dari sekadar fasih memakai telepon pintar. Semakin canggih teknologi informasi yang diciptakan, penggunanya justru makin tidak perlu menguras otak karena beragam surplus kemudahan yang diberikan.
Mari kita renungkan ulang. Salah satu aplikasi kota cerdas mungkin akan memudahkan penduduk sehingga tak perlu pusing dan repot saat mengurus urusan-urusan kependudukan. Semua proses rumit berjenjang cukup dilakukan melalui telepon pintar dalam genggaman tangan kita. Lantas, apakah hal itu membuat penduduk lebih cerdas?
Dulu, kita harus mencari Pak RT, Pak RW, lalu antre di kelurahan, berdialog dengan Pak Lurah, dan melewati beragam interaksi sosial lain saat mengurus ini dan itu. Bukankah itu justru membuat kita punya kecerdasan sosial (social intelligent)? Bukankah hal itu melatih kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan adversiti (AQ) kita? Digitalisasi tidak hanya disruptif bagi sistem yang dulu melibatkan aktivitas banyak orang, tetapi juga mengganggu proses belajar masyarakat untuk memiliki kecerdasan interpersonal dan intrapersonal.
Faktanya, kehadiran teknologi cerdas terkadang justru membuat manusia berpikir dan berperilaku tak cerdas. Dulu, pada awal-awal teknologi internet diciptakan, manusia memanfaatkannya untuk membangun interaksi sosial yang relatif positif. Sekarang, manakala teknologi media digital begitu canggih, media sosial dan media daring justru menyuburkan hoaks, ujaran kebencian, hingga terorisme. Dulu internet membangun interaksi di dalam keragaman, sekarang jadi alat eksklusi sosial dan sarana provokasi konflik sosial.
Manusia ternyata lebih bodoh daripada laba-laba sebab tak pernah ada laba-laba membuat jaring, tetapi terjerat dalam jaringnya sendiri. Adapun manusia menciptakan jejaring budaya yang disebut Clifford Geertz sebagai jejaring makna (the web of significance) yang jadi bumerang karena menghegemoni dirinya.
Karena itu, para peneliti budaya mengembangkan istilah "peradaban". Arnold Toynbee (1965) mendefinisikan peradaban sebagai kebudayaan yang memiliki dimensi ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Kita membutuhkan kota-kota berperadaban tinggi yang canggih dalam teknologi informasi, tetapi penduduknya berbudaya luhur.
"E-learning"
Supaya kota cerdas berbasis kebudayaan, sejarawan Universitas Gadjah Mada, Joko Suryo, mengingatkan pepatah lama, "man behind the gun". Teknologi informasi adalah alat, senjata, budaya materi yang harus dikendalikan manusia.
Hanya manusia berbudaya luhurlah yang alam pikirnya diliputi gagasan-gagasan mulia—sistem nilai, filosofi, ideologi—yang arif menciptakan, memilih, dan menggunakan senjata itu dengan baik. Senjata yang sederhana sekalipun, jika berada di tangan penjahat akan memicu petaka yang besar, apalagi senjata canggih bernama teknologi digital.
Pembangunan kota cerdas mestinya sejak awal memosisikan kebudayaan sebagai panglima dan teknologi digital sebagai alat. Kebudayaan membuat kita cerdas mencipta, memilih, dan menggunakan teknologi digital yang tidak sekadar memberi kenikmatan pragmatis, tetapi mencerdaskan (kultural) masyarakat/bangsa. Contohnya, dengan bantuan aplikasi digital, kita dengan mudah menemukan arah dan lokasi.
Di Yogyakarta, misalnya, aplikasi digital memudahkan kita menemukan Jalan Malioboro di pusat kota. Tetapi, kota cerdas berbasis kebudayaan mestinya bukan hanya memberikan kemudahan navigasi, juga memberi petunjuk yang lebih mencerdaskan. Sebab, nama Jalan Malioboro adalah bagian integral tata kota "sumbu filosofis" Yogya yang mengandung pesan moral yang sudah diapresiasi UNESCO. Malioboro adalah nama ajaran agar manusia membuang kejahatan "ma- lima", yaitu madat (mencandu, narkoba), madon (seks bebas), main (berjudi), minum (kemabukan), dan maling (mencuri, korupsi). Turis asing pun akan tertarik jika mendapat informasi kultural edukatif itu sebab mereka tak berkunjung sekadar mencari kemudahan.
Pembangunan kota cerdas berbasis kebudayaan semestinya bercirikan edukasi. Negara tidak hanya bertugas menyejahterakan, tetapi juga mencerdaskan bangsa. Jika sejahtera berarti hidup mudah dan nyaman, maka cerdas berarti terus meningkatnya kompetensi berpikir kritis, progresif, dan transformatif.
Jika tak berbasis kebudayaan, pembangunan kota cerdas di Indonesia hanya akan mengantarkan kota-kota jadi pusat-pusat modernitas global. Digitalisasi malah berpotensi melemahkan dan melenyapkan keaslian dan keunggulan kebudayaan kita. Sistem kota cerdas berbasis kebudayaan tidak hanya mencerdaskan penduduk urban, tetapi juga mentransformasi kota-kota kita jadi pusat-pusat peradaban yang melalui teknologi informasi mampu berdampak global.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar