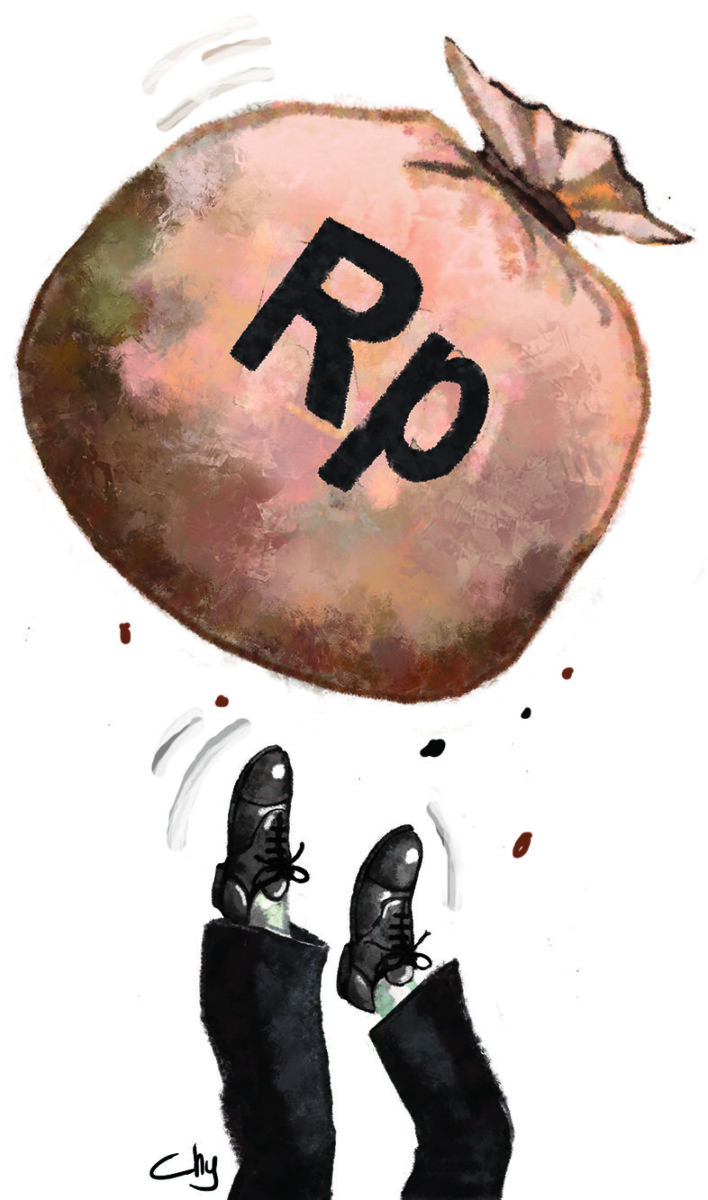
Selama masa kampanye pemilihan presiden, calon presiden Prabowo Subianto dan tim suksesnya gencar melontarkan tudingan bahwa utang pemerintah saat ini telah berada pada stadium gawat dan berpotensi menjerumuskan Indonesia menjadi negara miskin serta bangkrut pada 2030.
Baru-baru ini Prabowo juga menuding Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai "Menteri Pencetak Utang". Sebelumnya, mereka juga mengecap Presiden Jokowi sebagai "raja utang" karena dalam empat tahun memimpin negara, utang pemerintah meningkat drastis.
Pertanyaannya, benarkah utang pemerintah sudah berada pada stadium gawat dan bisa menyebabkan Indonesia jatuh miskin dan bangkrut? Jawabannya: Tidak benar! Hasil studi saya (2019) menunjukkan bahwa tudingan-tudingan negatif itu mengandung salah kaprah serius. Tudingan tersebut juga bisa menjadi bumerang bagi Prabowo sendiri.
Salah kaprah
Dari hasil analisis saya terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) selama 15 tahun terakhir, tampak bahwa tudingan bahwa jumlah utang pemerintah sebesar Rp 4.418 triliun (2018) sudah berada pada stadium gawat dan berpotensi menyebabkan Indonesia jatuh miskin dan bangkrut sangat berlebihan dan mengandung salah kaprah yang serius. Mengapa? Karena, untuk mengategorikan dan menyimpulkan utang dan keuangan negara berada dalam kondisi sehat atau sedang sakit serius (financial distress), ada tiga tolok ukur utama yang mesti digunakan.
Pertama, besaran rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) yang dihasilkan negara. Selama empat tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, rata-rata rasio utang terhadap PDB adalah 28,6 persen. Meskipun besaran rasio tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode 2010-2014 sebesar 24,04 persen, besaran tersebut masih jauh dari ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, yaitu maksimal 60 persen.
Selain rasio utang, rasio defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga bisa digunakan untuk menilai tingkat kesehatan keuangan negara. Selama ini, kebijakan penambahan utang baru setiap tahun selalu didasarkan pada rasio defisit APBN. Pada era pemerintahan Jokowi, rasio defisit APBN juga selalu berada di bawah ketentuan UU sebesar 3 persen, yaitu 2,58 persen (2015), 2,49 persen (2016), 2,5 persen (2017), dan 1,76 persen (2018).
Berdasarkan dua ketentuan yuridis tersebut, kondisi kesehatan utang dan keuangan negara kita sesungguhnya masih wajar dan aman. Dengan kata lain, kondisi kesehatan utang pemerintah masih sehat dan jauh dari indikasi sedang sakit serius seperti disinyalir oleh kubu capres Prabowo.
Perlu juga diketahui, rasio utang Indonesia saat ini adalah yang paling kecil di ASEAN dan juga termasuk yang terkecil di dunia. Mayoritas negara maju dan negara besar di dunia ini, seperti AS, China, Jepang, Inggris, Jerman, Kanada, Australia, India, dan Korea Selatan, rasio utangnya jauh lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Negara-negara tersebut bisa maju dan sejahtera karena menggunakan utang untuk investasi dan pembiayaan. Mereka pun mampu membayar utangnya karena utangnya dikelola secara baik. Tidak ada tanda-tanda negara-negara tersebut bakal bangkrut dan punah akibat dililit utang.
Indikator kedua adalah kemampuan pemerintah dalam membayar kewajiban jangka pendek dan utang jatuh tempo. Harus dipahami bahwa dari jumlah utang pemerintah sebesar Rp 4.418,3 triliun (2018), di dalamnya terdapat Rp 2.898,38 triliun (52,24 persen) utang yang merupakan warisan pemerintahan SBY. Pada awal April 2018, Presiden Jokowi pernah menyatakan bahwa selain diwarisi utang yang besar, pemerintahannya juga dibebani dengan bunga utang setiap tahun sekitar Rp 250 triliun, sehingga kalau empat tahun berarti bertambah menjadi Rp 1.000 triliun.
Hal tersebut menunjukkan tambahan utang pada pemerintahan Jokowi-Kalla sebesar Rp 1.519,75 triliun, tidak semata-mata hanya digunakan untuk investasi infrastruktur dan lainnya, tetapi juga digunakan untuk membayar utang dari pemerintahan SBY yang jatuh tempo beserta biaya bunganya. Dalam beberapa kesempatan, Menkeu Sri Mulyani juga mengatakan bahwa 44-70 persen dari utang baru pada pemerintahan Jokowi dipakai untuk membayar utang yang jatuh tempo dari pemerintahan sebelumnya.
Dengan demikian, sejumlah pernyataan keras capres Prabowo dan tim suksesnya yang menyalahkan Presiden Jokowi atas kenaikan utang pemerintah yang signifikan dalam empat tahun terakhir sesungguhnya salah kaprah.
Meskipun dibebani warisan utang yang besar dari pemerintahan sebelumnya, selama 2015-2018 pemerintahan Jokowi-Kalla melalui APBN selalu mampu dan tepat waktu dalam membayar kewajiban-kewajiban jangka pendek dan utang pemerintah yang jatuh tempo. Belum pernah terjadi Presiden Jokowi atau Menkeu Sri Mulyani mengeluh dan gagal menyelesaikan kewajiban membayar utang yang jatuh tempo. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan keuangan negara kita sesungguhnya sehat dan aman.
Indikator ketiga adalah efektivitas pemakaian utang dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek, meningkatkan investasi strategis dan kapasitas operasional, serta mewujudkan tujuan negara. Seperti telah saya bahas dalam artikel "Memahami Utang Pemerintah" (Kompas, 18/6/2018), tambahan utang baru pada era Jokowi-Kalla lebih banyak digunakan untuk menutup defisit APBN dan memperkuat likuiditas keuangan negara dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek.
Itu sebabnya, kita seharusnya patut bersyukur kepada pemerintah karena selama 2015-2018 Indonesia bisa terhindar dari bahaya krisis keuangan dan ancaman "negara gagal bayar" karena rasio utang terhadap aset (debt to asset ratio/DAR) negara kita sesungguhnya sangat tinggi, di atas 70 persen.
Selain digunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek, tambahan utang baru pada era Jokowi-Kalla juga digunakan untuk meningkatkan investasi strategis dalam wujud infrastruktur, seperti jalan, bandara, pelabuhan, irigasi, dan listrik, yang masif di seluruh pelosok Indonesia. Tujuannya, untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan efektivitas operasional ekonomi dan nonekonomi, serta mewujudkan keadilan sosial dan persatuan Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang.
Sejak 2017 dan 2018, hasil (return) dari investasi tersebut telah mulai dirasakan masyarakat luas. Secara ekonomi, implikasi positifnya juga mulai meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan efektivitas ekonomi dan nonekonomi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Peningkatan tersebut, misalnya, bisa dilihat dari kenaikan pesat nilai PDB dari Rp 10.569,7 triliun (2014) menjadi Rp 14.735,85 triliun (2018) atau naik 39,42 persen, pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dari 4,88 persen (2015) menjadi 5,17 persen (2018), serta peningkatan pendapatan negara dari Rp 1.550,49 triliun (2014) menjadi Rp 1.666.37 triliun (2017) dan Rp 1.942,3 (2018).
Seiring dengan mulai banyaknya proyek infrastruktur yang telah diselesaikan dan digunakan untuk berbagai kepentingan aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha, maka nilai PDB, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan negara diperkirakan akan kian meningkat pesat pada 2019 dan tahun-tahun selanjutnya. Peningkatan ini akan meningkatkan pula kemampuan pemerintah dalam membayar utang, menurunkan rasio defisit APBN, dan juga memperkecil rasio utang terhadap PDB, menyehatkan posisi keuangan negara dan menyejahterakan rakyat.
Bumerang politisasi utang
Dari perspektif teori sinyal (signaling), pernyataan-pernyataan subyektif dari capres Prabowo yang memolitisasi utang pemerintah bisa menjadi bumerang yang merugikan bagi dirinya sendiri. Selain memberi sinyal kepada publik bahwa pengetahuannya tentang utang pemerintah sangat lemah, berbagai kritik kerasnya justru memberikan "sinyal ketakutan" kepada publik. Masyarakat justru bisa menilai bahwa ia sesungguhnya sedang khawatir dan takut kalau terpilih jadi presiden, maka ia akan terbebani dengan warisan utang pemerintah yang besar dari pemerintahan Jokowi.
Singkatnya, politisasi utang pemerintah oleh Prabowo untuk "memojokkan" capres Jokowi justru memberi "sinyal ketidaksiapannya" kepada publik. Padahal, siap atau tidak siap, siapa pun capres yang bakal terpilih sebagai Presiden RI dalam Pilpres 17 April 2019 harus siap menerima dan menanggung beban utang pemerintah. Ia harus mampu membayar utang-utang lama yang akan jatuh tempo.
Prabowo sebaiknya belajar dari kearifan presiden-presiden Indonesia selama ini. Ketika BJ Habibie dilantik sebagai presiden pada Mei 1998, ia menerima warisan utang dari pemerintahan Soeharto Rp 551,4 triliun. Pada 20 Oktober 2004, ketika SBY dilantik menjadi presiden, ia menerima warisan utang dari pemerintahan Megawati Rp 1.298 triliun. Sementara ketika Jokowi dilantik menjadi presiden pada Oktober 2014, ia menerima warisan utang Rp 2.898,38 triliun dari pemerintahan SBY. Mereka tidak pernah mengeluh, pesimistis, dan memolitisasi utang pemerintah sebagai beban berat yang berpotensi memiskinkan rakyat dan membangkrutkan Indonesia.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar