Di satu sisi, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, dituding kubu capres nomor urut 01, Joko Widodo, sebagai bagian dari elite yang menguasai separuh lebih kekayaan nasional di bidang agraria dan karena itu tidak punya legitimasi moral untuk menggugat isu ketimpangan. Sebaliknya, kubu pendukung capres 02 mengkritik redistribusi tanah yang dibanggakan Jokowi sebagai petahana, hanya sertifikasi tanah belaka tanpa merombak struktur agraria yang timpang.
Munculnya isu ketimpangan agraria dalam perdebatan publik sebenarnya sangat positif karena telah menggugat ironi terbesar reformasi: proses demokratisasi politik justru mempertajam kesenjangan sosial-ekonomi. Di sektor kehutanan, misalnya, dari total lebih dari 26,17 juta hektar izin usaha pemanfaatan hutan (HPH dan HTI), 90,74 persen terbit dua dekade terakhir (KLHK 2018). Sebagian besar alokasi ini diperuntukkan bagi korporasi. Sayangnya, perdebatan publik ini, karena artikulasinya yang polemis, sama-sama tidak menyasar inti persoalan dari ketimpangan agraria.
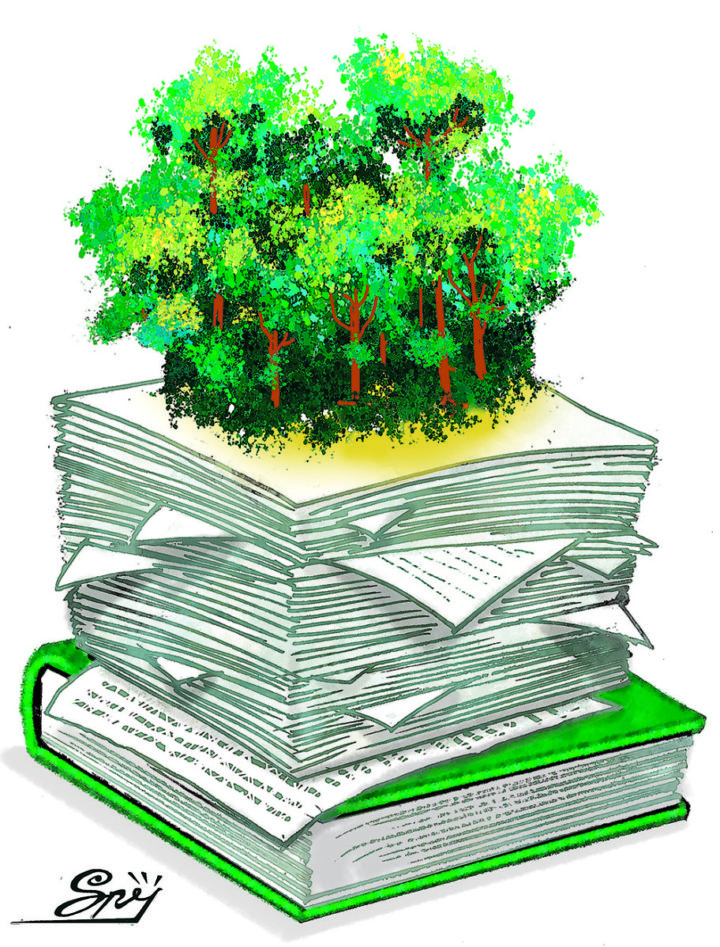
Ketimpangan distribusi
Dua jenis ketimpangan agraria harus dibedakan agar isu ini bisa dibahas lebih jernih. Pertama, ketimpangan distribusi, yakni kesenjangan penguasaan lahan antar-kelas di dalam sektor usaha tani rakyat. Kedua, ketimpangan alokasi, yakni kesenjangan peruntukan sumber-sumber agraria antar-sektor, antara yang dialokasikan untuk korporasi dan untuk rakyat (Shohibuddin, 2019).
Berdasarkan Sensus Pertanian 2013, jumlah rumah tangga petani (RTP) di Indonesia lebih dari 26,13 juta. Dari jumlah ini, 55,95 persen petani gurem (menguasai lahan kurang dari 0,5 ha) dan 31,68 persen petani kecil (menguasai 0,5-1,99 ha). Sisanya 12,37 persen merupakan petani mampu yang terdiri atas 6,21 persen petani menengah (menguasai 2,0-2,99 ha) dan 6,16 persen petani kaya (menguasai lebih dari 3 ha).
Dari data sensus ini juga diketahui total lahan pertanian rakyat mencapai hampir 22,428 juta ha. Sebagian besar (38,49 persen) dikuasai oleh 6,16 persen petani kaya yang rata-rata menguasai 5,37 ha. Di posisi berikutnya, 33,77 persen lahan rakyat ini dikuasai petani kecil dengan rata-rata penguasaan lahan 0,91 ha. Lalu, 15,8 persen dikuasai petani menengah yang rata-rata menguasai 2,18 ha. Petani gurem yang merupakan mayoritas hanya menguasai 11,94 persen lahan rakyat dengan rata-rata penguasaan 0,18 ha. Dari data ini sudah terlihat jelas betapa parah ketimpangan distribusi di sektor pertanian rakyat.
Jika batas minimum 2 ha dijadikan patokan penguasaan lahan ideal (sesuai UU Land Reform No 56/1960), beginilah potret ketimpangan penguasaan lahan yang terjadi: 54,29 persen lahan pertanian rakyat dikuasai oleh 12,37 persen golongan petani yang menguasai lahan 2 ha ke atas, sementara 45,71 persen total lahan pertanian harus menampung 87,63 persen petani yang menguasai lahan di bawah batas minimum.
Jika data di atas dibandingkan dengan hasil Sensus Pertanian 2003, terdapat beberapa fakta yang menarik. Selama satu dekade ini, jumlah RTP di Indonesia berkurang lebih dari 5,09 juta (16,32 persen). Penurunan terbesar terjadi pada golongan petani gurem (mencapai lebih dari 5,17 juta). Anehnya, golongan petani kecil dan menengah juga berkurang, berturut-turut sebesar 163.419 dan 54.928 orang. Hanya pada golongan petani kaya terjadi kenaikan 298.832 yang membuat golongan ini menjadi 1.608.728 orang.
Teori modernisasi akan melihat penurunan jumlah RTP ini sebagai hal yang positif: beban sektor pertanian akan berkurang, RTP yang tertinggal akan bertambah penguasaan lahannya, sementara RTP yang keluar menjadi angkatan kerja untuk sektor industri dan jasa di perkotaan. Namun, asumsi linier ini ternyata tidak banyak terbukti. Keluarnya 5,17 juta petani gurem tidak diiringi kenaikan petani kecil dan menengah yang justru menyusut sebesar 1,94 persen dan 3,27 persen. Jutaan petani gurem itu sendiri keluar bukan karena peluang kerja yang lebih baik di sektor non-pertanian (pull factor), melainkan karena tidak tertampung di sektor pertanian (push factor). Mereka terpaksa harus mengadu nasib ke kota-kota dan bahkan ke mancanegara.
Kondisi ketimpangan distribusi ini cerminan dari stagnasi transformasi agraria di Indonesia akibat tak dijalankannya land reform secara serius. Padahal, land reform adalah mekanisme menciptakan apa yang dalam wacana kebijakan sosial disebut "keadilan dalam peluang", yaitu melalui jaminan titik tolak yang relatif sama bagi semua petani. UU No 56/1960 menerjemahkan "titik tolak yang relatif sama" ini dengan mengupayakan penguasaan lahan 2 ha sebagai batas minimum usaha tani rakyat.
Ketimpangan alokasi
Dalam UU Pokok Agraria (UUPA), "keadilan dalam peluang" ini disertai dengan dorongan mewujudkan "usaha bersama dalam lapangan agraria atas dasar kepentingan bersama… dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong royong lainnya" (Pasal 12 Ayat (1)). Atas dasar ini, konsesi tanah berupa hak guna usaha (HGU) bisa diberikan kepada koperasi atau kolektivitas lain milik rakyat untuk pengembangan usaha bersama komersial di bidang agraria.
Dengan demikian, ada dua jalur yang dibayangkan UUPA untuk mewujudkan transformasi agraria. Pertama, pembentukan kelas petani menengah yang kuat dengan penguasaan lahan minimal 2 ha yang diupayakan lewat land reform. Kedua, pengembangan usaha bersama pertanian komersial di kalangan masyarakat pedesaan melalui pemberian HGU kepada koperasi atau kolektivitas rakyat lainnya. Tentu saja, HGU bisa diberikan kepada korporasi, tetapi bukan berarti pihak ini menjadi prioritas utama.
Pada kenyataannya, dua jalur transformasi agraria inilah yang terus diingkari. Selama lebih dari lima dekade, semua rezim yang memerintah selalu bertumpu pada kekuatan modal besar. Akibatnya, kondisi ketimpangan agraria bertambah parah, khususnya ketimpangan alokasi. Menurut Winoto (2007), 56 persen aset nasional berupa tanah dikuasai oleh hanya sekitar 0,2 persen elite ekonomi. Yang menarik, simpanan uang di lembaga perbankan nasional memiliki proporsi ketimpangan nyaris sama: 56,87 persen dari total simpanan uang dikuasai oleh hanya 0,11 persen pemilik rekening kaya dengan simpanan di atas Rp 2 miliar (LPS 2017). Hal ini mengindikasikan bahwa kemakmuran segelintir elite itu diperoleh dari penguasaan sumber-sumber agraria dan eksploitasi berbagai kekayaan alamnya.
Di sektor kehutanan, ketimpangan alokasi ini amat mencolok. Dari semua jenis alokasi kawasan hutan, lebih dari 40,46 juta ha (95,76 persen) jatuh ke korporasi, hanya sekitar 1,74 juta ha (4,14 persen) diberikan untuk rakyat, dan lebih sedikit lagi (41,2 ribu ha atau 0,1 persen) untuk kepentingan umum. Ironisnya, ketimpangan agraria ini naik pesat di era Reformasi, khususnya selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014). Dalam periode ini telah terbit izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 288.225,13 ha (55,62 persen), izin pemanfaatan hutan untuk HTI 4.707.640 ha (46,93 persen) dan untuk HPH 10.220.493 ha (63,33 persen).
Di luar kawasan hutan, hingga 2016 luas HGU mencapai lebih dari 15 juta ha dengan 1,034 juta ha di antaranya dalam kondisi telantar. Selain itu, terdapat hampir 3,58 juta ha izin lokasi yang haknya belum ada juga telantar (KATR/BPN 2017). Apabila konsesi tambang diperhitungkan, ketimpangan alokasi akan lebih tajam lagi. Sebab, konsesi ini bisa mencakup kawasan hutan dan non-kawasan hutan.
Relevankah RAPS?
Tantangan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) yang dijalankan pemerintah adalah sejauh mana ia bisa merespons dua jenis ketimpangan agraria di atas sekaligus. Oleh karena itu, relevansi RAPS ini ditentukan oleh sejauh mana dampaknya bersifat korektif, netral, atau justru memperparah kedua jenis ketimpangan.
Apabila RAPS berhasil mempersempit jurang kesenjangan antarkelas dan antarsektor, barulah ia dapat disebut "reforma agraria sejati". Tetapi, jika dampaknya tak mengubah apa-apa (status quo), maka sebenarnya ia "reforma agraria palsu". Apalagi jika ia justru memperdalam ketimpangan yang ada, maka di sini ia dapat dikecam keras sebagai kebijakan "anti-reforma agraria".

Tidak ada komentar:
Posting Komentar