Tetapi yang menegunkan justru alasan di balik gagasan tersebut. Sebagaimana dikabarkan oleh Romahurmuziy, Ketua Umum PPP, alasan yang dikemukakan oleh Jokowi adalah untuk mencegah perpecahan yang dibakar dengan kebencian dan sentimen suku, agama, dan ras (kompas.com, Sabtu, 14 April 2018, pukul 07.18 WIB, "Mayoritas Partai Koalisi dan Relawan Tak Restui Jokowi Gandeng Prabowo").

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto (kanan) menyempatkan diri untuk berkuda bersama disela-sela pertemuan mereka di Padepokan Garuda Yaksa Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10). Selain sebagai bentuk silaturahmi, pertemuan itu juga untuk mendiskusikan berbagai permasalahan di Indonesia.
Kata Romahurmuziy, Jokowi berkaca pada apa yang sudah terjadi dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, yang ternyata luar biasa memecah belah masyarakat dengan sentimen dan kebencian kesukuan, agama, dan ras. Jokowi khawatir, jika di DKI Jakarta saja terjadi efek destruktif disintegratif masif yang parah, betapa mengerikan akibatnya apabila keadaan seperti itu terjadi pada luasan nasional dalam kaitan dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, yang saat penyelenggaraannya bersamaan dengan pemilihan umum legislatif.
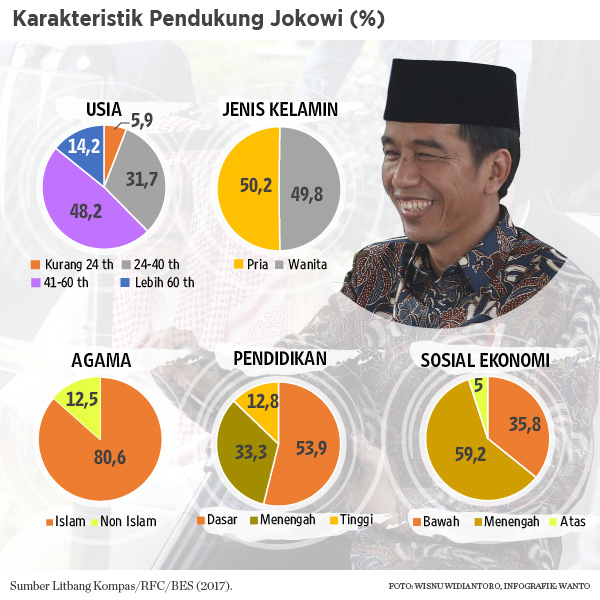
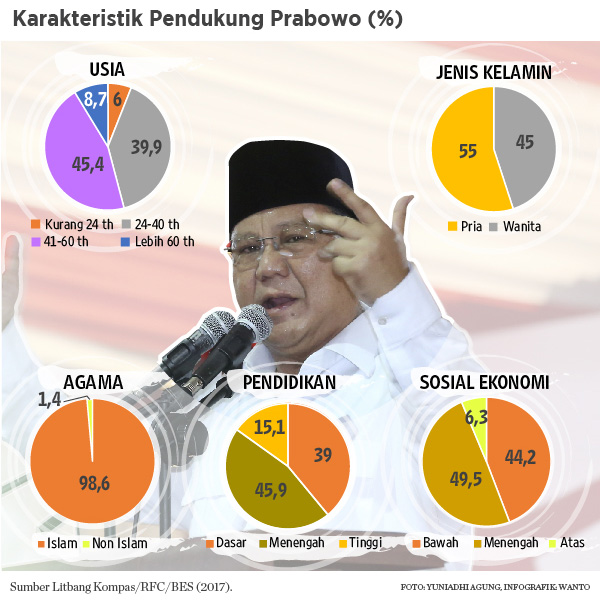
Mungkin kekhawatiran Jokowi adalah sekadar sebuah anggapan, yang tidak serta-merta merupakan kebenaran sahih; tetapi mungkin kekhawatiran itu adalahgut feeling, semacam perasaan intuitif yang berakar dalam pengalaman dan kebijaksanaan nirsadar, dari seorang politisi ulung yang adalah pemimpin sekaligus pencinta bangsa dan negaranya, yang selama ini tampak nyata berupaya merawat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Refleksi atas realitas
Oleh karena itu, alasan tersebut layak dan patut dianggap penting serta diperlakukan lebih dari sekadar sebuah asumsi. Ia adalah sebuah refleksi penting tentang suatu realitas yang sedemikian ironis dalam bangsa dan negara Indonesia hari kini, yaitu betapa ancaman perpecahan bangsa dengan ketertanaman kebencian di dalamnya.
Dan, itu terjadi bukan karena secara asali hamparan warga bangsa terpisah-pisah dalam berbagai kelompok yang baku memusuhi dan saling menghancurkan karena ketidakadilan dan kecemburuan. Yang terjadi justru kehadiran kelompok-kelompok elite luar biasa berambisi berkuasa, yang karena termakan oleh ambisi itu maka mereka menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Lalu, salah satu cara utama yang dihalalkan penggunaannya adalah pengobaran keadaan saling memusuhi, perpecahan, penanaman rasa baku membenci di tengah masyarakat dengan mengeksploitasi perbedaan suku, agama, dan ras.
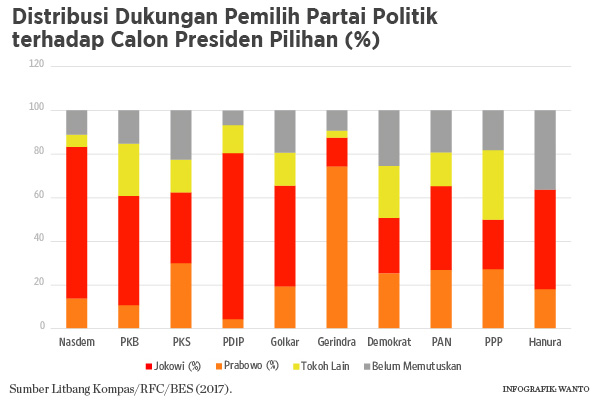
Mereka—para elite itu—dengan enteng beranggapan bahwa biar saja masyarakat dan bangsa terpecah belah, nanti sesudah berhasil meraih kekuasaan mereka akan dapat menyatukan kembali kelompok-kelompok masyarakat dan mengakhiri permusuhan serta kebencian. Padahal perpecahan dan tindakan saling memusuhi telah telanjur menciptakan trauma dalam pengalaman batin warga masyarakat. Ini adalah suatu keadaan patologik psikososial yang penyembuhannya tidak gampang.
Di mana tanggung jawab elite di negara dan bangsa Indonesia? Bolehkah mereka seenak kepentingan sendiri membuat kebohongan, memecah belah, mengobarkan permusuhan, menanamkan kebencian, tanpa dapat dimintai pertanggungjawaban?
Banyak elite di panggung- panggung wicara publik menyerukan kekhawatiran bakal terpecahbelahnya bangsa karena berbagai alasan, seolah mereka adalah penyeru peringatan bahaya yang bakal melanda masyarakat. Dengan menempatkan diri sebagai penyeru peringatan bahaya, kaum elite menobatkan diri seolah sebagai pihak yang mampu bertindak sebagai penyelamat bangsa dari disintegrasi; padahal mereka sendirilah yang menyumberi ancaman disintegrasi. Gambaran yang terbentang adalah sebuah hipokrisi yang parah di kalangan elite.
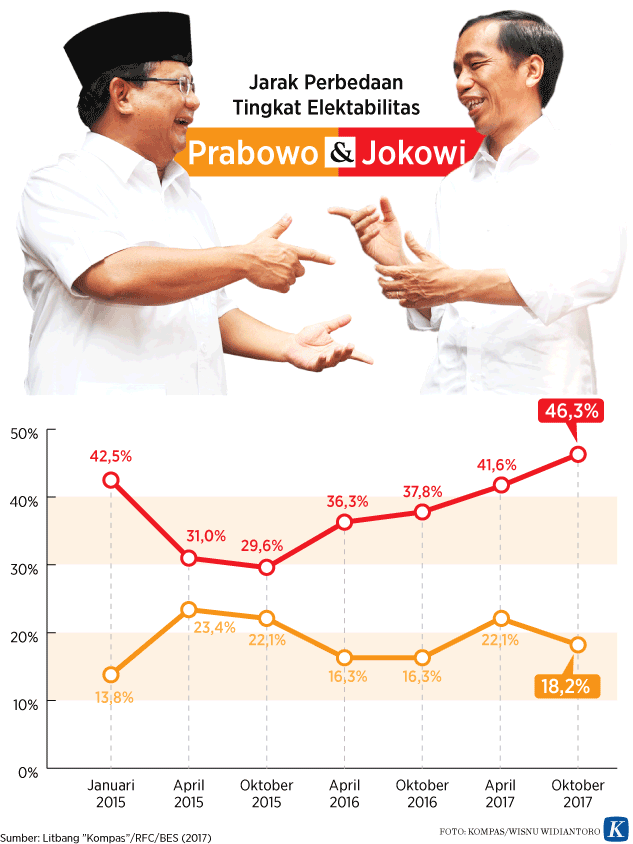
Keparahan hipokrisi terlihat kian kental tatkala disadari betapa gejala psikososial itu juga melanda masyarakat non-elite yang seperti merelakan diri digunakan oleh elite yang menjalankan skenario pembelahan masyarakat untuk meraih kuasa.
Kelompok-kelompok masyarakat seperti begitu enggan menggunakan akal sehat dan hati nurani buat menyadari kemunafikan yang sedang berlangsung; mereka kehilangan pikiran kritis dan hanya dilanda semangat berkobar untuk ikut belaka. Kendati kesalahan mereka tidak seberat yang dilakukan oleh elite, tetapi kelompok-kelompok masyarakat yang mau mengalami kematian pikir kritis dan membiarkan diri bersemangat untuk ikut saja, tetap saja salah. Terutama karena ihwal mempertahankan dan menggunakan pikiran kritis itu merupakan tanggung jawab setiap manusia, dan mematikan pikiran kritis diri sendiri adalah penanggalan tanggung jawab yang mendasar.
Kembali ke kejujuran
Kesalahan lain yang melanda masyarakat adalah mudahnya mereka melupakan kesalahan yang telah dibuat elite pemecah belah bangsa. Setelah masyarakat terpecah belah dan baku memusuhi, perguliran waktu yang tak usah lama dan ucapan-ucapan manis elite begitu gampang membuat masyarakat melupakan kesalahan mendasar elite. Sementara secara psikososial mereka masih menyimpan trauma perpecahan dan permusuhan yang belum tersembuhkan.
Bangsa lantas dikungkung dalam tiga serangkai patologi psikososial: hipokrisi, amnesia, trauma. Kombinasi absurd ketiga keadaan itu sangat mempersulit bangsa untuk mendapatkan kesehatan psikososial tingkat minimal yang diperlukan buat berlangsungnya pemerdekaan dan penumbuhkembangan bakat-bakat manusia. Bangsa menjadi terhambat dalam melaju mengarungi kemajuan, mengejar ketertinggalan, dan menjalani persaingan tak terhindarkan dengan bangsa-bangsa lain.
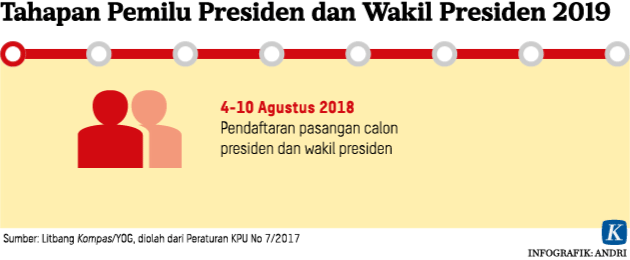
Saatnya kini rakyat menyadari kembali kejujuran yang selama ini tak mereka sadari lagi sebagai sebentuk kepemilikan nilai yang begitu penting dan berharga. Dengan kejujuran, rakyat perlu menolak untuk secara emosional dilibatkan dan diikutkan dalam perpecahan, baku memusuhi dan membenci, yang dikobarkan oleh elite. Tentang elite sendiri, dalam kondisi kini tak banyak yang dapat diharapkan. Kalau mungkin, penegakan hukum bagi elite yang memecah-belah bangsa dapat diterapkan dengan keras agar menjerakan; tetapi yang terpenting adalah rakyat mesti menolak diajak tidak jujur.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar