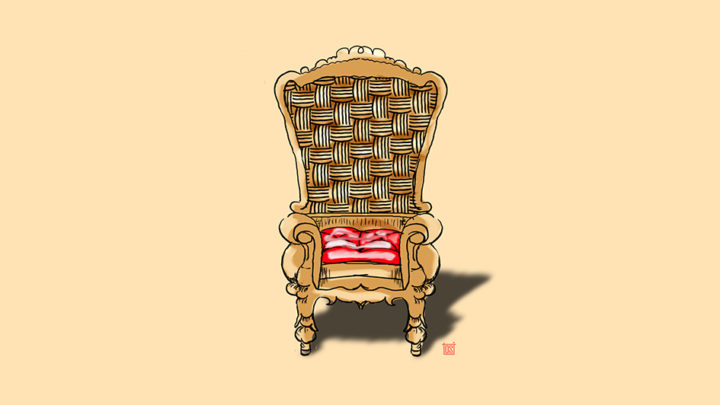
Pilkada
Munculnya sejumlah nama yang tersandung masalah korupsi mengindikasikan bahwa kualitas kandidat kepala daerah masih jauh panggang dari api. Fenomena tersebut tentu saja mengurangi bobot nilai dalam pilkada serentak 2018.
Bagaimanapun, kualitas kepala daerah akan menentukan sejauh mana nantinya hajatan demokrasi lokal menelurkan kepala daerah berkualitas, setidaknya antikorupsi. Jika banyak kepala daerah yang lebih sibuk menghadapi masalah hukum ketimbang konsolidasi politik dengan konstituen, dipastikan hak publik dalam mencerna visi misi kandidat tersendat.
Masih jauhnya kualitas kandidat di pilkada serentak tidak bisa lepas dari dua variabel penting, yakni buruknya regulasi dan permisifnya partai politik terhadap kandidat bermasalah. Regulasi yang ada saat ini cenderung menguntungkan parpol dan kandidat. Dikatakan menguntungkan karena kandidat yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau calon yang memang sejak awal sudah bermasalah bisa memaksakan diri untuk maju.
Hal ini dilakukan karena tak ada konsekuensi hukum yang akan membelitnya. Pasalnya, ketika mereka sudah terdaftar tidak bisa mengundurkan diri atau diganti oleh partai pengusung. Ini sesuai amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang melarang menarik calon sejak disahkan sebagai calon kepala daerah oleh KPU dan larangan pembatalan calon kepala daerah kecuali meninggal, bukan karena melakukan pelanggaran hukum tertentu.
Sementara bagi parpol, regulasi tersebut berimbas terhadap komitmennya dalam mengusung kandidat yang bersih. Artinya, regulasi tersebut telah membuka keran abainya parpol mencari kandidat yang tak berpotensi dibelit masalah hukum.
Parpol juga enggan meminang kandidat yang dikehendaki publik. Dalam posisi ini, logika yang dibangun bukan sejauh mana "mata batin" parpol memandang kelayakan kandidat dan konsekuensinya ke depan, melainkan parpol lebih memilih kandidat yang kuat secara finansial. Implikasinya, pertimbangan logistik jadi acuan utama dalam menentukan kandidat yang akan diusung.
Anasir di atas sangat mudah dideteksi dalam proses pencalonan kepala daerah. Tak sedikit tokoh potensial yang ingin maju merasa diperas oleh partai jika ingin mendapat rekomendasi. Tokoh non-parpol harus menyerahkan sejumlah uang kepada partai politik. Jika tidak, jangan harap akan memperoleh perahu politik.
Karena itu, tak heran banyak tokoh potensial layu sebelum menjadi kandidat. Di sinilah kemudian lahir kandidat yang tidak melalui mekanisme ketat di internal parpol, layaknya kader parpol yang ingin maju dalam pemilihan legislatif (pileg).
Memang terdapat perbedaan mencolok antara perekrutan kandidat kepala daerah dan calon anggota legislatif (caleg). Caleg biasanya melalui proses seleksi ketat dan sistem kaderisasi. Mereka harus paham betul ideologi partai dan harus melalui prosedur AD/ART yang berlaku.
Sementara bagi calon kepala daerah, parpol tidak perlu melakukan seleksi ketat layaknya calon DPR dan DPRD. Calon kepala daerah cukup memiliki modal popularitas, elektabilitas, dan bisa saja modal logistik. Inilah mengapa banyak kandidat yang dicalonkan oleh parpol, tetapi tidak memiliki ikatan ideologi. Pada akhirnya, partai bermetamorfosis menjadi organisasi politik penyedia "lowongan pekerjaan".
Tak sesuai ekspektasi
Sulitnya kandidat dengan kualitas mumpuni membuat dilema bagi pemilih. Di satu sisi, masyarakat menginginkan calon kepala daerah yang bersih dari masalah hukum. Namun, di sisi lain, kandidat yang bersih dari masalah hukum tidak mudah untuk maju karena problem prosedural-formal. Akibatnya, kandidat yang maju hanya itu-itu saja tanpa ada pembaruan keringat kerja-kerja politik, kandidat minus kinerja dan kualitas rendah.
Maka, tidak heran jika banyak kandidat yang tersedia hanya dari kalangan petahana, kandidat bermasalah, dan politik dinasti. Tidak sedikit juga kandidat harus berlumuran "dosa" politik akibat sanak keluarganya yang terlebih dahulu memimpin tersangkut masalah hukum. Inilah mengapa kualitas kandidat dalam pilkada acap kali bertolak belakang dengan ekspektasi publik.
Melihat keruhnya problem di atas, hajatan pilkada dihadapkan pada ancaman penting. Pertama, proses demokrasi hanya dikuasai kelompok kecil yang antidemokrasi. Para pembajak demokrasi mengartikan bahwa demokrasi sebatas proses pencoblosan di hari pemilihan.
Proses seperti itu diagungkan sebagai proses yang sangat demokratis karena publik sudah diberi hak untuk memilih kandidat yang disediakan oleh parpol. Setelah itu, hasilnya dikendalikan oleh kelompok kecil yang antidemokrasi.
Kedua, hajatan pilkada dikuasai oleh kaum oligarki dan para pemodal. Mekanisme pemilihan dan menentukan kandidat kita memang di desain secara demokratis. Namun, pada kenyataannya, elite politik dan pemodal yang menjadi dwitunggal tunggal penentu.
Publik tidak lagi memiliki kesempatan untuk memberikan masukan kepada parpol terkait rekam jejak kandidat yang dicalonkan. Sekali lagi, publik hanya mentok berpartisipasi di hari pemungutan suara.
Demi melahirkan kandidat berkualitas, ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama, revisi terhadap UU No 10/2016 terkait larangan menarik dan membatalkan calon kepala daerah harus segera dilakukan. UU tersebut didesain agar tersangka korupsi dapat diganti. Tujuannya agar calon yang tersedia bersih dari masalah hukum.
Kedua, rakyat harus dilibatkan dalam setiap proses pencalonan hingga akhir pesta demokrasi. Jika perlu, semua parpol melakukan konvensi pemilihan calon kepala daerah untuk menguji secara terbuka kualitas kandidat di mata publik. Dengan demikian, publik juga akan merasa memiliki tanggung jawab moral politik karena calon yang diusung oleh setiap partai atau gabungan sudah melalui seleksi secara mandiri.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar