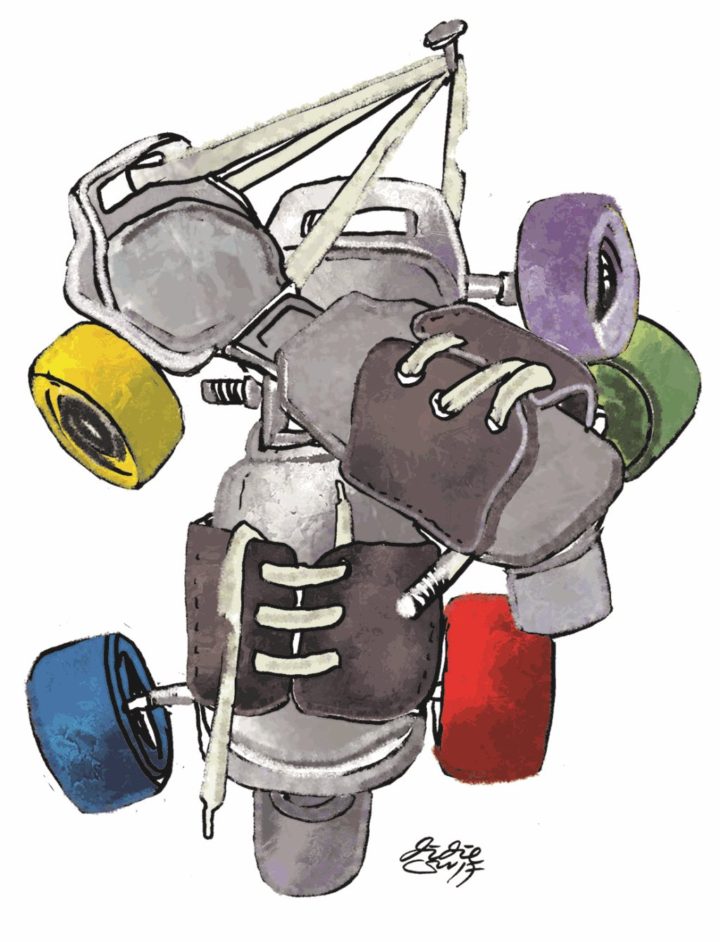Tiba lagi kita di pergantian tahun. Jika kita selalu sebut tahun yang akan dimasuki sebagai tahun baru, itu berarti bahwa tahun yang ditinggalkan sebagai tahun lama. Akan tetapi, tidak ada dalam pengetahuan masyarakat tentang tahun lama, setidaknya ia tidak pernah disebut.
Meminjam Jung (1990), hal ini bisa jadi merupakan ketidaksadaran kolektif tentang sebuah keyakinan bahwa masa depan adalah harapan, sedangkan masa lalu kesuraman. Harapan harus ditumbuhkan, kesuraman harus ditimbun. Inilah konotasi waktu yang terus berulang. Inilah mitos waktu (Barthes, 1976).
Dalam mitos waktu demikian, imaji penutur kiranya mengidentifikasi bahwa waktu melintas di atas interval linearitas. Ia membentang dari belakang ke depan. Bersama waktu, masa depan disongsong. Di situ, hidup manusia dilihat sebagai urutan peristiwa dalam narasi (Genette, 1989). Catatan seluruh urutan peristiwa itu lantas membentuk pengetahuan yang disebut sejarah.
Perspektif penghadiran "entitas waktu" pada linearitas sejarah tersebut dalam berbagai hal sering menyebabkan keengganan melihat ke belakang. Masa depanlah yang cenderung didengungkan. Itu sebabnya, sekali lagi, perayaan tahun baru lebih disukai ketimbang mengevaluasi masa lalu (tahun lama). Paling banter, tahun lama hanya dilihat sebagai sebuah kaleidoskop.
Membayangkan kemajuan
Itulah cara manusia modern menyikapi waktu. Modernisme, yang menjadi basis filosofi paradigma modern, mengajarkan bahwa masa lalu itu tidak perlu. Modernisme itu antisejarah, antitradisi (Barret, 1997). Pada percaturan global, perbincangan mengenai hal ini memang sudah kedaluwarsa. Pun demikian di sini, bagi segelintir pemikir, tema di atas juga sudah lusuh. Para seniman kontemporer telah lama hengkang dari perspektif demikian.
Akan tetapi, dalam kehidupan keseharian berbangsa, modernisme telah menjadi paham "melaten", menjadi semacam iman yang menubuh (embodiment). Ini karena lembaga pendidikan kita mengajarkannya hingga kini, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Kurikulum pendidikan sekolah dasar hingga perguruan tinggi boleh berganti, tetapi modernisme sebagai basis filosofisnya bergeming. Kita masih membayangkan kemajuan sebagaimana dulu dibayangkan oleh Sutan Takdir Alisjahbana. Kita harus mengejar kemajuan di depan, yang telah dicapai bangsa lain.
Itu sebabnya, visi universitas adalah menjadi kelas dunia. Sementara program studi yang fokus kepada kebudayaan sendiri tetap menjadi periferi. Di sekolah menengah, pengetahuan dan kekayaan tradisi masih tetap saja ditempatkan sebagai muatan lokal. Terdapat semacam ketakutan bersama, jika tidak menjadi maju seperti bangsa yang diandaikan maju itu, kita akan tergilas.
Oleh sebab itu, ukuran pencapaian pembangunan dalam berbagai bidang adalah nomor urut pada daftar hadir dunia, bukan kemandirian diri yang kokoh sebagai bangsa berkarakter. Presiden Jokowi mungkin menyadari hal ini sebagai kekeliruan sehingga ia selalu menggemborkan pendidikan karakter untuk merevolusi mental. Tapi, bagaimana mentalitas dan karakter bisa dibangun jika kultur dilupakan.
Identitas yang dibayangkan
Ambisi menjadi maju dalam pengertian tersebut akhirnya menyeret kita keluar dari apa yang ingin saya sebut "waktu kultural" yang terbingkai dalam jam kebudayaan. Kita keluar dari situ seraya membayangkan sebuah tempat yang bisa diraih sebagai alamat baru, identitas yang dibangun dari sebuah dinamika tidak berkesudahan: bangsa maju dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi. Imajinasi ini tidak hanya milik pemerintah, tetapi juga telah merupakan "kosakata" populer masyarakat.
Tentu kepemilikan pada daya fleksibilitas yang tinggi tersebut penting, tetapi satu hal telah dilupakan, yakni fleksibilitas itu bukan kekuatan tanpa modal dasar. Dengan kata lain, ia tidak dimulai dari ruang kosong. Beranalogi kepada Deleuze dan Guattari (1989), dalam superioritas wacana sosial (baca: global) yang mendominasi, sejatinya kita tetap memiliki "tubuh tanpa organ yang anti-oedipus" yang bersumber dari diri sebagai subyek yang terus menginterupsi.
Deleuze mengidentifikasi "hasrat skizoprenik" dalam tubuh tanpa organ sebagai kebebasan dan keliaran diri. Saya ingin menyebutnya sebagai kebebasan (ekspresi) kultural yang telah meng-alamiah (natural), yang secara genetis diwariskan dari generasi ke generasi. Ia tidak boleh punah apalagi dibuat menjadi punah. Alih-alih demikian, ia harus terus-menerus dibangkitkan menjadi semacam atavisme (penghidupan roh lama pada kebaruan).
Jika kita memaklumi bahwa kebudayaan yang ideal hari ini adalah sebuah instabilitas tak berkesudahan, ekspresi kultural sebagai atavisme itulah yang harus terus-menerus menjadikannya berada dalam ketidakstabilan tadi. Dengan kata lain, dalam tataran global, kebudayaan kita harus terus-menerus menjadi "pengganggu", bukan sebaliknya. Pada titik ideal dalam politik identitas, fleksibilitas adalah daya untuk mewarnai, bukan diwarnai; kekuatan memanggil, bukan dipanggil.
Keberagaman antropologis
Dengan cara itu, hemat saya, kita bisa menikmati pergantian tahun dalam konteks waktu kultural tadi. Harus dipahami bahwa waktu kultural kita tidaklah bergerak di atas interval yang linear, tetapi pada garis yang melingkar. Saya tidak sedang mengatakan bahwa sejarah selalu berulang. Hal yang ingin disampaikan adalah situasi bahwa sebenarnya kita tidak sedang hidup pada abad ke-21, tetapi dalam 21 abad sekaligus.
Di negeri ini, tradisi dan modernitas hidup berdampingan. Fetisisme antropologis dan fetisisme komoditas campur baur. Tuhan klenik dan Tuhan cyborg saling berkelindan. Indonesia adalah negeri keberagaman pada arti yang sebenarnya.
Fakta keberagaman sedemikian sejatinya bukan permasalahan. Sejak awal sejarah, kita telah lahir sebagai bangsa berumpun-rumpun. Keberagaman adalah soal hubungan dalam keberumpunan, relasi dalam kolektivitas. Relasi ini diniscayakan muncul oleh keikhlasan, oleh kebesaran hati untuk tidak membandingkan satu dengan yang lain. Di situ, keberbedaan dilihat sebagai ciri khas kelompok.
Berdasar hal itu, berabad lamanya keberbedaan telah diterima dengan mutlak. Tidak ada upaya saling memaksa, bahkan sekadar memengaruhi agar yang satu mengikuti yang lain. Orang Sunda
tidak pernah meminta orang Batak menjadi Sunda, misalnya. Jika pun terdapat kesalingpengaruhan, dasarnya adalah cinta.
Pernikahan kultur antara Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu (keluarga Presiden Jokowi) tahun ini bisa ditunjuk sebagai contoh. Penambahan gelar Siregar pada Kahiyang adalah peleburan keberbedaan dalam kesadaran kultural. Inilah keberagaman antropologis. Hubungan antaretnik sejak berabad lalu telah memberikan pelajaran ini.
Keberagaman politis
Namun, kini kita acap gagap melihat keberagaman. Ini karena, di luar waktu kultural, keberagaman tidak lagi bertumpu pada nilai-nilai kultural. Alih-alih demikian, tumpuan keberagaman kini adalah kepentingan. Saya ingin menyebutnya sebagai keberagaman politis. Dalam keberagaman politis, posisi diri di hadapan orang lain menjadi fokus utama.
Kita menghargai keberbedaan, tapi dalam relasi itu diri sendiri
(dapat dibaca: kelompok dengan homogenitas kepentingan) harus lebih unggul. Relasi ini lantas disahkan bersama dengan istilah "kompetisi". Sejauh ini, keberagaman politis sedemikian memang tetap bisa dipersatukan. Tapi,
dasar kebersatuannya juga politis. Lihatlah, kita dapat bersama dalam keberbedaan semata-mata diikat oleh fakta politis bahwa kita hidup di sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berkali-kali ikatan itu hendak lepas,
bukan?
Kehendak diri untuk unggul dalam keberagaman sedemikian lagi-lagi merupakan produk pendidikan modern. Dapat diperiksa, sistem pendidikan modern kita cenderung mencetak individu unggul ketimbang membangun kultur kebermanfaatan dalam kebersamaan. Benih-benih intoleransi bisa jadi juga berasal dari sini. Tentu ini sebuah ironi. Jam pelajaran sekolah menjadi momen bagi siswa untuk keluar dari waktu kebudayaan dirinya sendiri. Sudah sedemikian jauh. Tapi, tentu kita masih bisa berharap. Selepas jam istirahat, setelah tahun berganti, kiranya kita bisa kembali masuk ke dalam pusaran waktu kultural kita.
Selamat Tahun Baru!