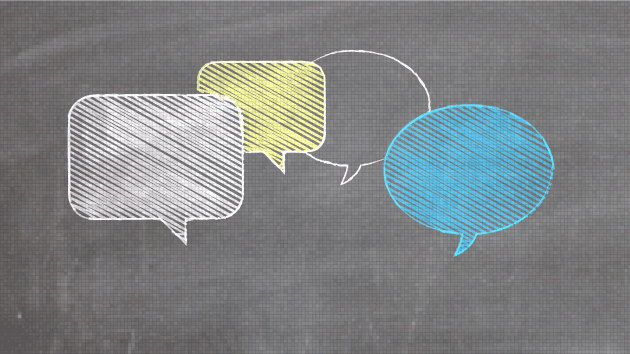
Seorang wartawan pernah mempertanyakan di ruang redaksi, kenapa tidak laik menggunakan kata kemahalanpada berita ekonomi dan bisnis untuk menerangkan harga barang yang dinilai terlalu mahal. Contohnya: "Rizal Ramli Sebut Biaya Meeting IMF-WB di Bali Kemahalan."
Sebenarnya, soal ini tak usah dipertanyakan untuk konteks jurnalisme media serius. Apalagi, kata yang dipersoalkan bakal diterapkan di rubrik ekonomi dan bisnis dengan format formal, dingin, dan analitis. Meski jargon jurnalisme-sastra sudah lama populer, wartawan tidak bisa dengan sewenang-wenang mencomot kata dari ragam cakapan untuk berita berbahasa formal hanya supaya tulisannya enak dibaca. Ada yang disebut konteks dalam proses menulis.
Pada media serius, kadang-kadang, ada sebuah rubrik yang berisi artikel-artikel pendek untuk bacaan ringan, biasanya tentang kejadian lucu dan menghibur. Pada Harian Kompas, sebagai contoh, rubrik itu bernama Kompasiana. Selain itu, ada rubrik Pojok. Dalam kedua rubrik ini kebebasan memilih kata lebih luas. Sentilan Mang Usil butuh ruang lapang dalam pemilihan kata agar komentar atau sindirannya mengena pada aneka problem berbagai kelompok sosial tanpa harus terjebak blunder yang tidak perlu. Juga, redaktur Kompasiana butuh keleluasaan memilih istilah agar sukses mengangkat sisi humor dari beragam peristiwa yang diceritakan.
Sekadar mengingatkan materi pelajaran di sekolah menengah, kemahalan adalah nomina dari kata sifat mahal yang menyarankan makna peringkat, contohnya, "Tingkat kemahalan harga suatu komoditas berbanding lurus dengan permintaan pasar dan berbanding terbalik dengan ketersediaan barang." Jikakemahalan dengan makna nonformal (terlalu mahal) diterapkan di laporan bisnis yang formal, risiko kerancuan makna bisa terjadi manakala terminologi formal menuntut akurasi pada aspek semantik, misalnya untuk keperluan statistik.
Pada waktu lain, seorang wartawan dengan bersemangat ingin memakai kata sebel dan bukan sebal buat judul berita di halaman muka korannya. Maklum, ia terbawa perasaan saat menulis laporan utama tentang suatu isu yang "menyebalkan". Hasrat itu dapat dimengerti. Perbedaan satu huruf saja dapat memancing emosi yang diharapkan meletup di hati pembaca.
Ketika orang menulis: "Sebel!" (dengan tanda seru), dengan serta-merta emosi yang hendak dia tunjukkan terejawantahkan secara efektif. Lain halnya dengan tulisan "Sebal!" (sekalipun ditegaskan dengan tanda seru), kadar emosinya, boleh jadi, tidak menyentuh titik kulminasi. Saya tidak berkesimpulan bahasa formal tidak memadai untuk mewadahi emosi spontan atau membangun humor. Kita hanya tidak terbiasa menuangkan emosi dengan bahasa formal yang penggunaannya terbatas untuk situasi yang cenderung serebral. Jadi, ekspresi spontanitas atau wacana humor pada ragam formal menuntut kekhasan situasional yang lain, yakni lingkungan dan kapasitas intelektual tertentu yang setara pada kedua pihak: pembicara dan penanggap.
M Subhan SD di Kolom Politik: "Politikus Sontoloyo" (Kompas, 27 Oktober 2018), menulis: "Presiden Jokowi tampaknyagemes…" bukan karena dia tak tahu bentuk yang baku. Kata tak sekadar mengemban makna leksikal yang dibakukan, tapi juga mewadahi emosi spontan yang hanya efektif apabila ada dukungan atmosfer sosial dan kultural yang khas, dan dukungan itu sering menuntut pengabaian formalisasi yang sudah diterapkan oleh leksikograf pada kamus.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar