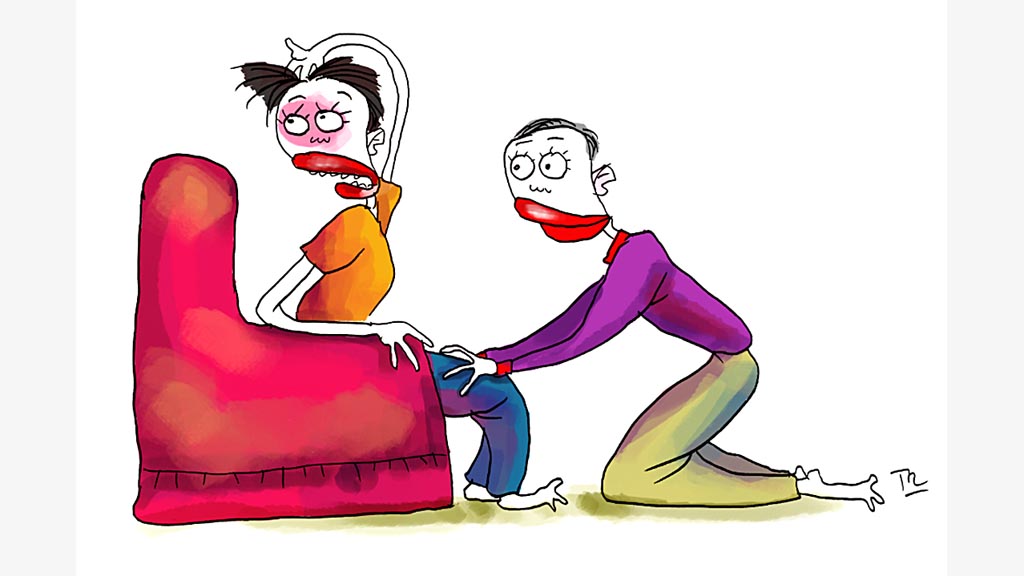Fenomena melemahnya nilai tukar rupiah dalam beberapa bulan terakhir hingga menembus angka lebih dari Rp 15.000 per dollar AS telah menimbulkan tanda tanya dan bahkan kekhawatiran bagi sebagian masyarakat.
Hal ini dapat dimaklumi, terutama mengingat faktor pengalaman krisis keuangan 1997/1998 yang telah berdampak secara multidimensional.
Berbeda dengan krisis 1997/1998, rupiah yang terdepresiasi saat ini lebih disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu perang dagang AS-China, kenaikan suku bunga The Fed, dan kekhawatiran dampak rambatan (spillover) dari pelemahan nilai tukar lira (Turki), peso (Argentina), serta sejumlah mata uang emerging economies lain. Sementara faktor fundamental domestik diyakini relatif kuat, tecermin dari pertumbuhan ekonomi triwulan II-2018 yang meningkat menjadi 5,27 persen, dari triwulan I-2018 sebesar 5,06 persen dan triwulan II-2017 sebesar 5,01 persen.
Sejumlah indikator makro lain juga relatif baik, seperti tingkat inflasi yang terjaga 3,18 persen pada Juli 2018 (yoy) dan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) kurang dari 30 persen.
Meski demikian, jika menyimak data defisit transaksi berjalan (current account deficits/CAD), angkanya naik menjadi 8,0 miliar dollar AS pada triwulan II-2018, dari triwulan I-2018 5,7 miliar dollar AS, sehingga CAD hingga semester I-2018 tercatat 2,6 persen dari PDB. Meskipun masih relatif aman karena di bawah 3 persen dari PDB, indikator CAD ini sangat penting untuk diperhatikan sebab merupakan indikator daya saing suatu negara, khususnya dalam konteks perdagangan dan investasi (aliran modal) di dunia. Defisit CAD berpotensi menjadi sumber vulnerabilitas dari sisi eksternal/nilai tukar, atau rawan menjadi obyek spekulasi.
Neraca perdagangan dan daya saing industri
Secara khusus, jika analisis difokuskan pada neraca perdagangan (trade balance) yang menjadi komponen utama pada neraca transaksi berjalan (selain neraca modal) selama tiga tahun terakhir (2015-2017), terlihat kinerjanya juga relatif baik karena membukukan surplus (ekspor melampaui impor) dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya yang selalu defisit. Khusus 2016 ke 2017, surplus tercatat naik dari 15,3 miliar dollar AS ke 18,8 miliar dollar AS meskipun di semester I-2018 surplus ini melambat.
Kendati demikian, sebaiknya kita jangan merasa senang atau bangga dulu dengan surplus dagang ini, terutama jika mempertimbangkan asesmen terhadap daya saing ekspor industri manufaktur domestik (nonmigas) dengan negara ASEAN lain (Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam), China dan India (Ridhwan dkk, 2015, 2016). Beberapa studi terkait yang dilakukan Bank Dunia dan lain-lain juga menyimpulkan hal yang relatif sama.
Pertama, dari sisi struktur/komposisi barang, selama 10-20 tahun terakhir produk ekspor terutama didominasi oleh bahan mentah dan produk setengah jadi yang mempunyai tingkat teknologi yang rendah (khususnya komoditas pertanian, perikanan, dan tambang). Akibatnya, nilai tambahnya juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan produk impor yang didominasi oleh produk manufaktur yang mempunyai nilai tambah tinggi dan elastis terhadap pendapatan, khususnya gawai/smartphone, otomotif, dan perangkat elektronik modern lainnya.
Impor untuk sejumlah barang konsumsi tersebut, industri nasional yang berorientasi ekspor juga masih bergantung terhadap impor bahan baku dan bahan modal. Keterkaitan manufaktur domestik dalam rantai pasok global (global value chains) masih terbatas pada jenis pekerjaan pendukung (supporting), seperti perakitan di industri kendaraan bermotor dan pengemasan, atau belum pada taraf inti (core), seperti pembuatan mesin mobil dan pembuatan desain/prototipe.
Kedua, dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah produk ekspor Indonesia hanya bertambah 83 item (dibandingkan dengan Vietnam 1.024 item barang). Selain itu, persentase ekspor Indonesia ke negara-negara berpendapatan per kapita tinggi (high income countries) seperti AS, Uni Eropa, dan Jepang hanya 53 persen atau lebih rendah dari negara pesaing di ASEAN.
Ketiga, tingkat kematian produk Indonesia (hilang di pasaran) sebanyak 311 relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Thailand (132), India (137), dan Malaysia (241), sementara China hanya 99 produk dalam rentang 2010-2015. Adapun produk yang bisa bertahan (surviving product) Indonesia berdasarkan besaran nilai ekspornya tentu adalah produk yang berbasis sumber daya alam (natural resources), khususnya minyak kelapa sawit, batubara, gas alam cair; sementara berdasarkan banyaknya pasar yang dituju (sebaran pasar), produk yang survive adalah paper dan paperboard, furnitur, dan barang seni/hasil pahatan (patung dan lain-lain).
Dengan menggunakan analisis product space (Hildago dkk, 2017) terdapat indikasi bahwa product space Indonesia kian menjauh dari core–nya, artinya kita mengalami penurunan jumlah produk yang berkeunggulan komparatif di dense forest (mesin, elektronik, garmen, tekstil, furnitur) sehingga rantai pasokan/supply-chain (supplier)-nya di pasar domestik juga kian berkurang. Ternyata keunggulan ini telah banyak "diserap/diambil alih" China. Konsekuensinya, dengan daya saing rendah pada kluster industri dengan proksimitas tinggi (dense forest), akan menyulitkan transisi ke kelompok pendapatan (income group) yang lebih tinggi (potensi masuk ke "jebakan kelas menengah").
Hasil studi penulis ini juga dikonfirmasi oleh temuan yang relatif sama oleh Ricardo Hausmann (Harvard, 2017) sebagai berikut. Pertama, terjadi perlambatan ekspor per kapita untuk manufaktur/nonmigas (2012-2015). Rodrick (Harvard) menunjukkan adanya gejala deindustrialisasi prematur di Indonesia, sebagaimana terlihat dari pangsa industri pengolahan terhadap PDB yang terus menurun, sementara sektor jasa justru meningkat.
Di China, sektor jasa berkembang setelah sektor industrinya tumbuh lebih pesat dahulu. Dalam fase pertumbuhannya, manufaktur Malaysia dan Thailand juga dimulai dari tekstil, lalu meningkat ke elektronik dan permesinan (1980-2017). Sementara Indonesia selama 30 tahun terakhir masih stuck di sektor tekstil atau belum banyak perkembangan produk dengan teknologi lebih tinggi.
Kedua, selama 2000-2015, nilai ekspor untuk produk "baru" dari indonesia hanya 4 item dengan total nilai ekspor 2,6 miliar dollar AS, sangat jauh jika dibandingkan dengan produk baru dari Vietnam sebanyak 51 item dengan nilai 51,7 miliar dollar AS dan Thailand 51 item dengan nilai 17,4 miliar dollar AS.
Untuk mengetahui faktor-faktor kunci apa yang menjadi tantangan/permasalahan yang menghambat daya saing/kinerja ekspor domestik, studi penulis (2016, 2017) dengan melakukan diagnostik daya saing perdagangan menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut adalah terkait faktor enablers (prakondisi), khususnya faktor sumber daya manusia yang berkaitan dengan rigiditas upah, faktor logistik khususnya interkonektivitas antardaerah/pulau di Nusantara, terbatasnya alternatif sumber pembiayaan ekspor selain bank dan terbatasnya fasilitas kredit murah bagi eksportir. Selain itu, masalah perizinan dan koordinasi antar-instansi.
Ketiga, dari segi akses pasar, meski mayoritas tarif bea masuk ke negara tujuan ekspor cukup rendah (di bawah 2 persen, kecuali ke AS), hambatan nontarif (non-tariff barriers) masih banyak diterapkan oleh negara-negara maju (AS dan Eropa) dibandingkan dengan Vietnam, Filipina, dan Thailand yang lebih lunak. Strategi pemasaran secara spasial (kewilayahan), yaitu dengan memanfaatkan kawasan industri (industrial park) dan zona ekonomi khusus (special economic zone), juga belum optimal, terutama karena belum terintegrasinya kawasan tersebut dengan infrastruktur pendukung (energi, konektivitas, dan lain-lain); serta kejelasan status pengelolaan lahan industri antara pemda dan badan/otorita khusus yang dibentuk oleh pemerintah pusat.
Strategi jangka pendek
Berangkat dari hasil temuan studi di atas, semua orang mungkin telah menyadari betapa kompleksnya (struktural) tantangan/permasalahan yang dihadapi untuk dapat meningkatkan kinerja/daya saing ekspor industri manufaktur nasional, terlebih lagi dalam kondisi ketidakpastian ekonomi global saat ini (perang dagang AS dengan China). Namun, kita tetap harus optimistis dan bersemangat untuk menyusun strategi yang aplikatif dan inovatif sehingga dapat terhindar (dampak minimal) dari turbulensi ekonomi dunia saat ini.
Untuk itu, mengingat kebutuhan kita terhadap penerimaan devisa yang mendesak (untuk menutup CAD), beberapa strategi kebijakan (quick-wins) berikut layak dipertimbangkan dalam rangka mendorong penerimaan devisa khususnya. Pertama, strategi pemasaran yang nonkonvensionaldengan memperluas/diversifikasi negara tujuan ekspor yang baru seperti negara berkembang di Asia (Kamboja, Laos, Myanmar), Afrika, dan kesepakatan perdagangan bebas (FTA) bilateral, misalnya dengan Australia, dan lain-lain. Selain itu, pasar domestik dapat lebih diperkuat mengingat jumlah penduduk sekitar 260 juta merupakan pasar potensial yang besar (internalisasi), khususnya melalui perbaikan interkonektivitas (integrasi) ekonomi antardaerah.
Kedua, penguatan strategi kebijakan untuk mendorong pengembangan home-industry atau skala usaha kecil dan menengah yang berorientasi nilai tambah dan ekspor. Bentuk dukungan terutama di sektor pemasaran, peningkatan kapabilitas SDM, penguasaan teknologi, dan aksesibilitas pembiayaan. Ketiga, pengembangan tenaga kerja terampil melalui pemberian kursus/training yang melibatkan user (industri) dan memanfaatkan sebesar-besarnya peluang training di luar negeri yang diberikan prinsipal industri yang investasi di dalam negeri.
Keempat, dalam jangka pendek, komoditas agro (perkebunan) dan perikanan yang kita miliki saat ini hanya perlu sedikit "dipoles" agar dapat diekspor, khususnya untuk yang mempunyai nilai tambah tinggi, seperti buah-buahan tropis (manggis, mangga, nanas, dan lain-lain), termasuk produk hutan yang eksotik, seperti minyak atsiri dan getah damar.
Di era digital dan globalisasi saat ini di mana kaum milenial yang mendominasi, mendorong pesatnya pertumbuhan leisure economy, termasuk melalui industri pariwisata, juga dapat menjadi andalan untuk meningkatkan devisa secara cepat. Mengingat kekayaan alam dan budaya kita yang sudah tersohor tetapi masih memerlukan dukungan promosi, koordinasi dan komunikasi baik di pusat maupun di daerah menjadi penting.
Sejumlah strategi kebijakan di atas kiranya dapat dipertimbangkan bagi pengambil kebijakan, terutama dalam jangka pendek, menyikapi ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi mengganggu stabilitas makroekonomi nasional. Namun, tentu, upaya stabilisasi dimaksud—pengendalian defisit transaksi berjalan dan stabilisasi nilai tukar—harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa dan tidak hanya diserahkan atau menjadi tanggung jawab otoritas moneter. Reformasi struktural merupakan faktor kunci untuk solusi permasalahannya, yang mau tidak mau harus secara kontinu dan konsisten dilaksanakan.