
Pemukiman padat penduduk di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta, Sabtu (3/2). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dari total 26,58 juta penduduk miskin di Indonesia, sebanyak 10,27 juta orang berada di perkotaan.
Kembalinya diskursus nasionalisme di sejumlah negara, setelah beberapa dekade globalisasi menjadi norma umum, menimbulkan sejumlah persoalan.
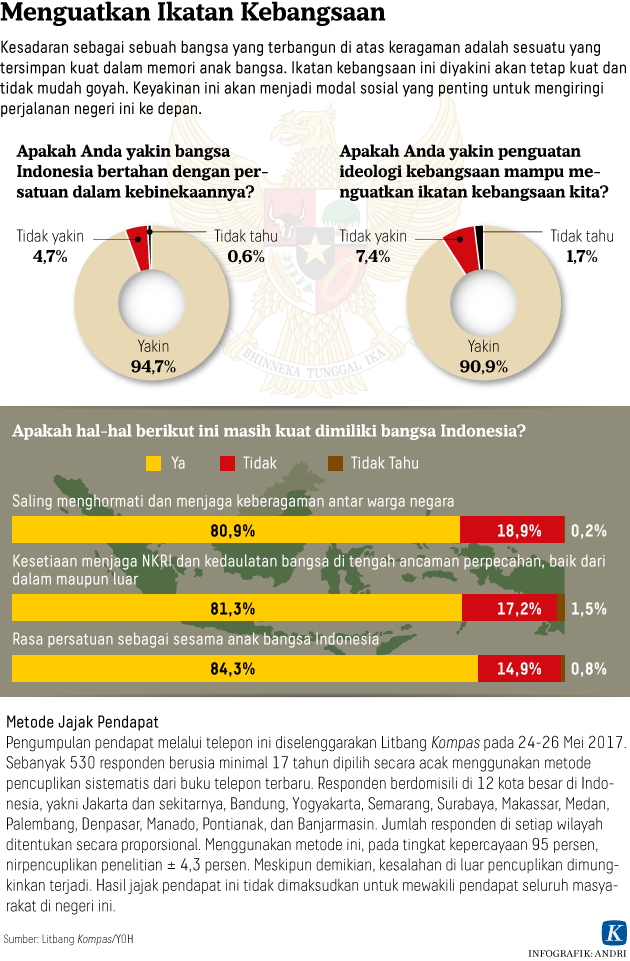
Dalam diskusi bersama harian Kompasdan Asia Institute, University of Melbourne, Australia, Februari lalu, mengemuka pendapat bahwa nasionalisme yang muncul saat ini disebabkan ada perasaan tertinggal di masyarakat akibat globalisasi.
Globalisasi dengan ekonomi liberalnya telah memberikan kemakmuran melalui perdagangan barang dan jasa serta arus uang tanpa hambatan batas negara. Pada sisi lain, globalisasi diakui menyebabkan terjadinya ketimpangan kemakmuran. Ada sebagian kecil orang mendapat manfaat sangat besar dari liberalisasi ekonomi. Sebagian besar yang lain, meskipun mendapat manfaat, tetapi tidak sebesar kelompok kecil tersebut.
Liberalisasi ekonomi mendorong swastanisasi berbagai layanan publik dan penghapusan subsidi oleh negara, seperti transportasi, penyediaan air bersih, pendidikan, dan kesehatan.
Di Indonesia, hal itu berawal saat Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia mensyaratkan penyesuaian struktural sebagai bagian kesepakatan bantuan dua lembaga keuangan dunia itu saat ekonomi Indonesia terpuruk ke dalam krisis pada tahun 1998.
Ketimpangan kemakmuran ditambah dengan ketidakpastian dan gejolak ekonomi global menimbulkan perasaan cemas pada kelompok kelas menengah. Di tengah situasi seperti itu, muncul kebutuhan mencari kelompok yang sama.
Nasionalisme mendapat tempat karena memberikan perasaan sama meskipun sebenarnya mengaburkan banyak perbedaan dan aspirasi di dalam kelompok. Karena itu, nasionalisme seperti itu dianggap mengabaikan hak-hak individu, suara masyarakat miskin, dan kelompok yang marjinal.
Nasionalisme saat ini berbeda dari saat Indonesia menuju merdeka. Kini lebih merupakan diskursus politik yang diproduksi dalam suatu kegunaan konkret. Hal tersebut tampak setidaknya sejak pemilu dan pilpres tahun 2014 dalam wujud kelompok nasionalis-nasionalis dan nasionalis-agama.
Kita melihat ucapan, jargon, atau simbol yang digunakan elite politik saat menggunakan isu nasionalisme untuk menakar reaksi masyarakat. Elite-elite politik yang sama dapat menggunakan simbol-simbol nasionalisme dan agama secara bergantian.
Menjelang pilkada serentak pada 27 Juni 2018, sentimen nasionalisme belum tampak dimanfaatkan oleh para elite politik di daerah. Namun, beberapa pihak melihat kemungkinan digunakannya kembali isu nasionalisme pada pilpres tahun 2019.
Melihat potensi isu nasionalisme mungkin dapat mengaburkan perbedaan serta meminggirkan kelompok marjinal dan hak-hak individu, kita mengimbau agar para elite politik dapat mengelola isu tersebut bukan sekadar untuk meraih suara.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar