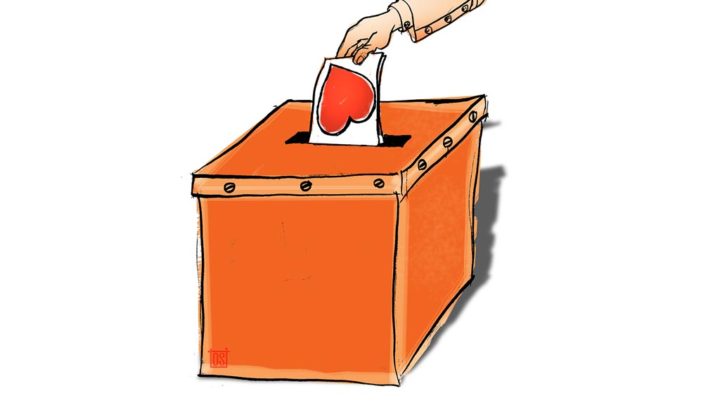
Ilustrasi: Pilkada.
Tajuk Rencana harian Kompas (28/6/2018) berjudul "Kemenangan Rakyat" membabarkan warta pemilihan kepala daerah serentak di 171 wilayah yang dinilai berlangsung aman dan lancar.
Pada bagian lain, Kompas mengingatkan, "Siapa pun yang nantinya akan dilantik sebagai pemimpin di daerah harus mengingat dari mana kekuasaan itu datang. Melalui kendaraan partai politik, kekuasaan itu datang dari rakyat. Karena itulah kekuasaan yang diperoleh dari rakyat harus dimanfaatkan untuk memberikan kemaslahatan bagi sesama". Di sana juga ditegaskan: rakyat pemberi kuasa jangan dikhianati!
Tajuk Rencana yang ditulis harian Kompas menjadi relevan untuk membincangkan rendahnya kualitas budaya komunikasi pasca-pilkada serentak 2018. Mengapa menjadi relevan? Sebab, secara komprehensif hal itu dapat diamati atas hilangnya moralitas dan akal sehat penghuni alam raya ini. Tengaranya akibat pergeseran nilai budaya yang menyebabkan nilai luhur budaya Indonesia terpinggirkan. Penyebab lain, ditengarai minimnya pagu mutu budaya komunikasi dialogis antarmanusia dengan sesamanya. Semuanya itu berujung pada miskinnya kualitas budaya komunikasi dialogis.
Dalam perspektif budaya visual, manusia tidak lagi diposisikan sebagai subyek pengguna bahasa. Sebaliknya, bahasa sehari-hari yang dianggap komunikatif dalam konteks ini adalah bahasa verbal bernuansa nyinyirisme, terorisme, dan ego sektarianisme.
Klimaksnya saat proses komunikasi dialogis kehilangan akar budaya luhurnya. Artinya, para pelaku komunikasi lebih mengedepankan proses lelaku egoisme individual atau golongan. Kepekaan dan kepedulian terhadap harkat hidup kemanusiaan yang beradab seolah hablur ditelan angin puting beliung egoisme. Semua lapisan masyarakat gagap menjalankan sebuah jalinan komunikasi dialogis yang komunikatif.
Dampaknya, fenomena miskomunikasi senantiasa menghantui proses komunikasi dialogis antara masyarakat dan pejabat penyelenggara pemerintahan, anggota dewan dan elite politik. Sengketa membara acap mencuat di kalangan warga masyarakat dalam kelompok heterogen.
Perbedaan persepsi sering mengganjal ekspresi komunikasi dialogis antara orangtua dan buah cinta kasihnya. Perang dingin pun jadi kabel penghantar konflik pasangan suami-istri. Permusuhan dan sentimen pribadi mewarnai interaksi sosial murid-guru, mahasiswa-dosen, dan anak buah dengan atasannya.
Di tahun politik ini, budaya komunikasi dialogis diperlukan kehadirannya. Kemunculannya senantiasa dinantikan demi menangkal miskomunikasi antarpihak yang berujung konflik sosial budaya. Dengan mengedepankan budaya komunikasi dialogis, para pemimpin bangsa, pejabat penyelenggara pemerintahan, dan anggota dewan dapat memetakan dan mengatasi konflik sosial pasca-pilkada yang menggejala di lingkungan masyarakat.
Lewat kerja budaya komunikasi dialogis, pejabat penyelenggara pemerintahan seyogianya terus-menerus melakukan proses dialog dua arah. Hal itu wajib dilakukan untuk mendapatkan hasil positif berdasarkan kebenaran hakiki.
Pada titik ini, mereka diharapkan mau mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka berkenan menjawab pertanyaan dan keluhan dari rakyat. Mereka dengan bersungguh-sungguh menjelaskan situasi dan kondisi yang ada secara kontekstual. Mereka diharamkan melakukan langkah sebaliknya: merasa paling benar dan senantiasa menghindarkan diri dari realitas tanggung jawab yang ada.
Libido lapar
Masalahnya kemudian, mengapa pejabat penyelenggara negara, anggota dewan, dan elite politik tidak membudayakan budaya komunikasi dialogis saat mereka menjalankan tugas negara?
Realitas sosial yang muncul di lapangan memberikan gambaran nyata atas masalah tersebut. Ternyata orientasi berpikir para pejabat penyelenggara pemerintahan, anggota dewan, dan elite politik masih bergerak di seputar wilayah perut. Mereka yang dipercaya sepenuh hati oleh rakyat Indonesia ternyata terserang sindrom libido lapar dan haus kekuasaan.
Ternyata dalam pikiran mereka terpatri upaya memuaskan rasa lapar dan dahaga kekuasaan. Upaya jahat yang dilakukannya dengan memperebutkan kursi kekuasaan jabatan publik. Hal itu diyakininya mampu menenangkan sekaligus mengenyangkan gejolak hasrat perut yang kelaparan atas kursi kekuasaan jabatan publik.
Demi memperoleh kursi kekuasaan jabatan publik, mereka mengatur siasat merebut kekuasaan. Hasilnya, dengan label penguasa, mereka dipastikan memiliki "hak prerogatif" mengelola bangsa dan negara ini. Atas nama kekuasaan, mereka mempunyai hak dan merasa paling benar mengatur semuanya.
Berdasarkan hal itu, mereka acap kali mengaplikasikan konsep kekuasaan adigang, adigung, adiguna dengan tata struktur yang terukur rapi. Pengejawantahannya lebih mengedepankan sikap arogan karena merasa paling baik dan benar. Kemudian muncullah sikap egoisme total.
Ketika egoisme total itu mengkristal, muncullah sebentuk kekuasaan bernuansa adigang, adigung, adiguna. Pada titik ini, rakyat merasa dikhianati. Para pejabat penyelenggara pemerintahan dan anggota dewan yang telah diberi amanah kekuasaan oleh rakyat guna mengelola dan menjalankan roda pemerintahan kemudian dinilai menjadi sekelompok penguasa yang tidak amanah.
Padahal, sejatinya rakyat mengharapkan pemikiran, teladan, dan langgam kepemimpinan para pejabat penyelenggara pemerintahan serta anggota dewan yang dapat menjadi payung teduh. Sebuah payung sosial budaya yang mampu memayu hayuning bawana alias memayungi rakyat secara beradab dan berkeadilan sosial.
Sumbo Tinarbuko Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta
Kompas, 6 Juli 2018

Tidak ada komentar:
Posting Komentar