Penyebabnya, politik elite tidak memberikan harapan banyak bagi pengokohan bangunan toleransi sehingga masyarakat mesti terus merawat nyala lilin di tengah kegelapan. Bangunan toleransi (dan kerukunan sebagai luarannya) selalu membutuhkan dua basis yang saling menguatkan, yaitu basis politiko-yuridis (dimensi struktural) dan basis sosial (dimensi kultural).
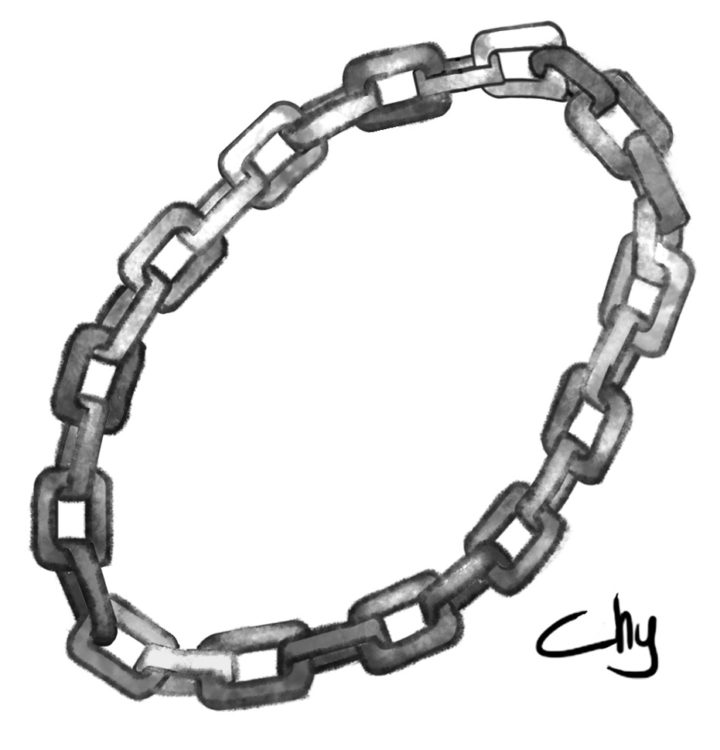
Dimensi struktural bangunan toleransi dan kerukunan berkaitan dengan regulasi yang disusun dan disediakan negara untuk menjamin dan menjaga agar perilaku antarsesama entitas partikular tidak mengganggu tertib sosial dalam tata hidup dalam keragaman identitas keagamaan. Sementara dimensi kultural berkenaan dengan kemampuan masyarakat untuk menjadikan toleransi sebagai etika kolektif dalam perbedaan identitas tersebut.
Masalah elite politik
Elite politik sebagai aktor kunci dalam membangun basis politiko-yuridis (toleransi dalam wajah produk legislasi negara dan pemerintah) secara faktual tak bisa terlalu diharapkan. Elite (politik) di tingkat nasional punya logikanya sendiri dalam menempatkan isu intoleransi dan radikalisme.
Dalam hampir dua dekade, elite politik dalam rezim pemerintahan apa pun (bahkan yang mendaku berideologi paling nasionalis sekalipun) selalu membuka ruang bagi negosiasi dengan kelompok-kelompok intoleran dalam tata politik pemerintahan. Dalam logika elite, toleransi adalah soal semburan wacana (verbal) belaka dalam ruang-ruang transaksi politik di ruang publik. Dalam konteks itu, toleransi seperti narasi kompleks yang abstrak lagi absurd.
Toleransi sejatinya ideal yang membumi. Toleransi merupakan ekspresi penerimaan dari satu terhadap yang lain, pengakuan dari diri (self)akan keberadaan liyan (others), dan kehendak masing-masing identitas yang berbeda untuk hidup berdampingan secara damai. Dalam kerangka toleransi, jika pun ada ketidaksetujuan terhadap kepercayaan dan keyakinan yang melekat pada identitas yang berbeda—baik di ranah simbol, tradisi, norma, bahkan ritus—ketidaksetujuan tersebut dihaluskan (sublimated disapproval)(Little, 2008).
Bahkan, meskipun entitas partikular tertentu (baca: mayoritas) percaya bahwa mereka memiliki kekuatan untuk ikut campur terhadap identitas lain yang berbeda (baca: minoritas), mereka secara sengaja memilih tindakan untuk menahan diri dari mencampuri pihak yang berbeda (Cohen, 2004), apalagi mengubah dan mempersekusinya.
Narasi toleransi sedemikian di kalangan elite nasional masih kerap menjadi perselisihan politis. Fakta-fakta kasat mata intoleransi pun kerap mereka sangkal. Bahkan, terlalu banyak elite menyoal setiap bentuk agenda promosi toleransi, hanya sebagai justifikasi sosio-politis atas pilihan mereka untuk mendayung kepentingan elektoral di atas lautan dukungan kelompok-kelompok intoleran atau ketakmampuan mempurifikasi aliansi politik mereka dari anasir kelompok yang secara terbuka kerap mengekspresikan perilaku intoleran.
Dalam konteks itu, penulis mengapresiasi sikap politik generik Partai Sosialis Indonesia yang hingga detik ini menarik batas demarkasi jelas dengan aktor-aktor dan narasi-narasi intoleransi. Sayangnya, potret politik elite demikian amat minor.
Bahkan, ekstremisme kekerasan (dalam bentuk aksi teror tragik yang sangat telanjang sekalipun, semisal aksi teror bom oleh pelaku sekeluarga di Surabaya) tak betul-betul jadi musuh kolektif peradaban nasional kita yang berkemanusiaan atas dasar sila kedua Pancasila.
Faktanya begitu banyak elite politik yang menyebarkan narasi-narasi permakluman dan pembenaran aksi teror tersebut, alih-alih menganalisasi dukungan pada penegakan hukum atas aksi teror yang terjadi dan menyalurkan energi kolektif bagi gerakan sosial antiterorisme pascaperistiwa itu.
Singkatnya, para penyelenggara negara (terutama yang duduk di kursi-kursi Dewan dan Majelis Senayan yang mulia) dalam wajah politisi sangat sulit untuk diharapkan memperkuat dimensi struktural toleransi. Penyelenggara negara yang partisan pastilah bersiteguh bahwa SKB Tiga Menteri yang restriktif terhadap Ahmadiyah tak mungkin diubah apalagi dicabut, meski Pasal 29 Ayat (2) UUD 45 nyata-nyata menyebut bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing."
Hanya mereka yang berwatak negarawan/negarawati, yang melampaui sekat-sekat kepentingan dan afiliasi politik, saja yang akan mampu memanggul mandat dan harapan penguatan basis politiko-yuridis toleransi. Kita berharap Pemilu/Pilpres 2019 akan menghadirkan figur-figur demikian di legislatif dan eksekutif.
Penguatan basis sosial
Dalam situasi demikian, penguatan basis sosial toleransi menjadi begitu strategis. Masalah intoleransi di level basis sosial utamanya berkenaan dengan dua kebutuhan dasar, yaitu literasi keagamaan dan perjumpaan lintas iman.
Benarlah matsal Arab bahwa manusia adalah musuh bagi apa yang tidak diketahui (Annaasu a'daa-u maa jahiluu).Begitu banyak tindakan intoleran yang didasari oleh ketidaktahuan mengenai diri dan liyan. Maka, literasi keagamaan merupakan salah satu agenda kunci penguatan basis sosial.
Literasi akan membangun spiritualitas, baik personal maupun sosial. Literasi akan mengurangi prasangka yang memicu psikologi kecemasan, ketakutan, dan keterancaman. Semakin tinggi literasi, skripturalisme yang mudah memicu 'sumbu pendek' dalam interaksi keberagaman akan semakin menipis. Literasi keagamaan akan membangun imunitas pemeluk agama dari derasnya penjalaran intoleransi dan doktrin ekstremisme kekerasan.
Dalam konteks inilah lembaga pendidikan, guru, pengajaran agama, taman baca masyarakat, internet dan media sosial, media arus utama, radio komunitas, dan saluran-saluran literasi lain memainkan peranan penting. Maka intervensi penguatan mereka jadi isu krusial.
Kebutuhan mendesak lainnya adalah memperbanyak ruang-ruang perjumpaan. Dengan itu, inklusivitas dan inklusivisme dapat dibangun. Ketika di tempat ibadah dan bahkan di sekolah-sekolah tertentu warga kita hanya berinteraksi secara eksklusif dalam kesamaan identitas, dibutuhkan lokus sosial lain seperti permukiman dan perumahan yang memberikan ruang bagi perjumpaan lintas identitas yang berbeda secara terbuka.
Perjumpaan terbuka antaridentitas akan memberikan pengalaman pembentuk kedirian bahwa perbedaan itu menguatkan bukan melemahkan, menyatukan bukan menceraiberaikan.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar