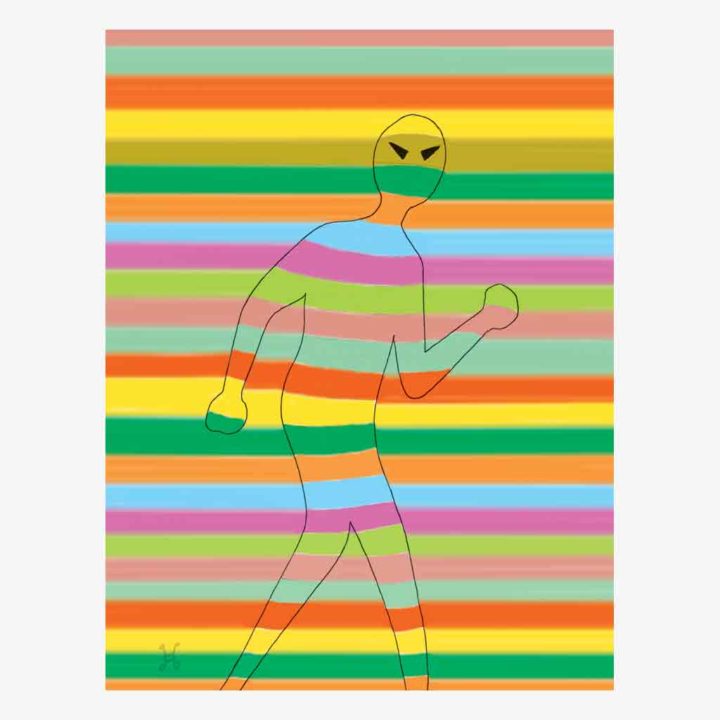
Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga. Pepatah lama itu masih cocok untuk meringkas rangkaian kasus Setya Novanto yang bisa disinetronkan. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan SN sebagai tersangka untuk kedua kalinya, dampak awal bagi SN yang paling nyata adalah karier politiknya akan segera meredup, kemudian hancur berantakan.
Kasus SN patut menjadi pelajaran bagi para penguasa bahwa kekuasaan yang menggiurkan yang pernah didudukinya ternyata tak bisa menyelamatkannya. Walaupun awalnya SN menggunakan jurus kepiting, "gigit sana-gigit sini", atau jurus gurita, "pegang sana atau pegang sini", KPK tetap bergeming.
Penegakan hukum seperti itulah yang masih menyejukkan dahaga keadilan di Republik ini. Penegak hukum lain bisa menjadikannya sebagai teladan keadilan, agar keadilan benar-benar tegak, walau langit akan runtuh sekalipun.
Kisah SN hampir mirip dengan kisah para pendahulunya di Sukamiskin. Para pihak yang melakukan korupsi seakan silih berganti. Satu ditangkap, regenerasinya seakan muncul kembali. Kalau kita tengok data KPK pada 2004-2016, 32 persen pelaku korupsi yang menjadi pasien KPK adalah para pemimpin politik, seperti anggota DPR, DPRD, gubernur, wali kota/bupati, dan wakil bupati. Mereka semua adalah buah dari sistem politik kita.
"Kaum penjahat"
Dari sekian kasus korupsi yang pernah terjadi, apa yang salah dengan sistem politik kita yang telah berubah sejak 1998. Dua puluh tahun lalu, para mahasiswa dan semua elemen demokrasi dan rakyat berjuang menuntut penghapusan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun, hingga sekarang KKN sebagai tuntutan paling utama di antara tiga tuntutan rakyat lain yang diusung oleh para mahasiswa pudar dan bahkan mengalami "kematian".
Sistem politik kita mengalami fase-fase yang sulit. Konsolidasi berjalan di satu sisi, tetapi di sisi lain demokrasi juga mengalami perusakan dari dalam. Bukan lagi defisit demokrasi, tetapi situasi demokrasi kita saat ini mirip dengan demokrasi "kaum penjahat".
Ramalan itu sudah pernah dilontarkan LIPI dan The Ford Foundation dalam seminar bertema "Toward Structural Reforms on Democratization in Indonesia: Problems and Prospects", 11-14 Agustus 1998, yang mengingatkan akan datangnya bahaya "kaum penjahat" dalam perubahan politik yang sedang terjadi di Indonesia.
Olle Tornquist menyebut negara-negara yang baru memulai transisi demokrasi dari otoritarianisme seperti Indonesia akan menghadapi tantangan hantu demokrasi "kaum penjahat".
Dalam hal ini, minimal ada beberapa ciri, yaitu, pertama, "demokrasi didukung oleh kaum militer dan sipil, di dalamnya para pejabat di semua tingkat mampu bertahan, menarik sekutu militer dan pengusaha, mengooptasi beberapa pembangkang, serta memobilisasi dukungan massa melalui populisme agama".
Ciri ini menunjukkan bahwa ada simbiosis mutualisme antara kekuatan politik lama dan baru serta militer dalam mempertahankan kekuasaan yang tersendiri di era demokrasi. Pada praktik demokrasi kita saat ini, hampir sebagian peluang kekuasaan dikooptasi tiga kekuatan besar, yaitu elite partai, pengusaha, dan kombinasi sipil-militer yang masih kuat pengaruhnya.
Ciri kedua ialah masifnya korupsi yang muncul di partai-partai politik (Linz, et al, 2001: 17). Partai politik menjadi wadah bersarangnya berbagai kepentingan kekuatan lama dan baru, yang tumbuh dan berkembang secara metamorfosis.
Masa transisi Indonesia ditandai oleh sulitnya mana yang dapat disebut sebagai kekuatan politik baru yang akan membawa panji-panji sumpah reformasi dan benar-benar dapat dibedakan dari kekuatan lama sebelumnya.
Ada kontaminasi
Ibarat kata orang, "baju ternoda, bekasnya tidak mudah lekas hilang", karena sebagian generasi yang memimpin politik era Reformasi adalah generasi yang secara historis tak dapat dilepaskan dari pengaruh hegemoni ideologi Orba. Kontaminasi ideologi, perilaku, dan cara-cara berpolitik tidak mengalami perubahan. Bedanya menurut bahasa gaul generasi now adalah cara komunikasinya, instrumen yang digunakan, dan kemasannya yang lebih modern. Padahal, isinya hampir sama, setali tiga uang.
Studi yang dilakukan oleh Syarif Hidayat (LIPI) menunjukkan demokrasi kita diwarnai oleh shadow state, di mana para penguasa menjadikan kekuasaannya untuk mengendalikan pasar dan bentuk-bentuk imbalan lainnya. Informal market juga menyokong, akibat adanya ketidaktaatan hukum karena pertukaran ekonomi tetap terjadi walaupun sudah ada larangan pada setiap pertukaran dan produksi apabila tidak menjadi pendapatan pemerintah.
Salah satu wujud dari shadow state ialah praktik pemerintahan di daerah yang dikuasai oleh orang-orang kuat. Muncul raja-raja baru, penguasa baru yang mengapitalisasi kekuasaan politiknya. Syarif menyebut bahwa para penyelenggara negara mengundang para investor nasional dan asing untuk bergabung dalam jaringan shadow stateyang dibangunnya.
Sebagai imbalannya, para pengusaha tersebut diberi perlindungan melalui otoritas formal si pejabat. Di situlah terjadi transaksi ekonomi dan politik tanpa harus melalui institusi formal negara.
Bukankah praktik-praktik seperti itu yang kita tolak 20 tahun lalu? Bukankah hal yang demikian itu pula yang kita sebut penyebab utama krisis ekonomi dan politik 1998? Sejumlah pertanyaan bisa kita tulis, tetapi mengapa seakan-akan praktik politik-ekonomi lama tidak berubah juga. Mengapa hal seperti itu situasinya malah marak terjadi, bahkan kadang-kadang tanpa malu-malu?
Semua itu salah satunya berhubungan dengan cara reproduksi kepemimpinan di tingkat nasional dan lokal. Kepemimpinan demokrasi kita sangat tradisional, diisi oleh proses persekongkolan antara pemilik modal, orang kuat, dan orang-orang yang punya pengaruh untuk menduduki kekuasaan politik dan partai politik. Prinsip pengisian organisasi dan pemerintahan modern nyaris terlupakan.
Lewat partai
Struktur partai sebagai organisasi reproduksi kekuasaan diisi orang-orang yang tak memiliki jaminan integritas. Harus diakui bahwa perubahan partai politik cenderung mengarah pada pengelolaan partai politik yang tidak berintegritas, masih jauh dari prinsip-prinsip good governance, karena pada praktiknya mereka menerapkan bad governance.
Ciri paling utama dari bad governanceyang merajalela sekarang antara lain, pertama, masuknya orang-orang yang tanpa kemampuan karena alasan political appointee, ke ranah kekuasaan dan komisaris BUMN hampir di semua lini.
Kedua, masifnya pola kolusi dari tumbuhnya bisnis staf ahli atau jabatan lain seperti sekretaris jenderal di kementerian/lembaga, pejabat eselon I, hingga bahkan IV, yang diisi orang-orang yang berkuasa. Semua itu adalah mimpi buruk dari cita-cita bersama reformasi saat menjatuhkan Soeharto. Itulah sebagian wajah bopeng dari kamuflase kolusi untuk memberi tempat bagi tim sukses dan relawan, tanpa memedulikan kapasitas dan kemampuannya.
Situasi jamak seperti itu semakin kokoh karena masih kuatnya budaya permisif masyarakat Indonesia, yang masih menghormati martabat seseorang dari kekayaan. Bahkan, dalam satu kasus di suatu daerah, salah seorang gubernur yang telah menjadi tersangka KPK begitu lepas dari tahanan disambut dengan karpet merah, puji-pujian, dan marhabanan. Demikian pula dengan kasus terpilihnya salah satu calon bupati pada Pilkada Serentak 2017, walaupun yang bersangkutan dalam kerangkeng jeruji KPK, dia pemenangnya.
Semua deretan peristiwa korup dan perilaku menyimpang di atas makin mengukuhkan tesis bahwa hantu demokrasi kita sesungguhnya adalah elemen-elemen yang mengaku demokratis, tetapi perilaku sesungguhnya adalah "kaum penjahat".
Tantangan Presiden
Presiden Joko Widodo yang terpilih pada Pemilu 2014 sebenarnya memiliki banyak modal untuk mendorong gerbong tata pemerintahan yang baik agar sistem politik kita sehat. Cita-cita pemerintah saat ini (Nawacita) ke-2 telah menggariskan "membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan tepercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan".
Sejalan dengan itu, membangun sistem politik yang tidak diisi "kaum penjahat" tidak kalah penting dengan infrastruktur tol laut, jalan tol, atau jembatan. Reformasi internal partai dan penataan partai pemerintah (government party) merupakan salah satu tanggung jawab kepemimpinan politik Presiden, karena sebagian politisi yang kena operasi tangkap tangan dan korupsi adalah partai pendukung pemerintah/presiden. Tanggung jawab itu konsekuensi logis sistem presidensial.
Oleh sebab itu, tantangan Presiden Jokowi saat ini adalah untuk memastikan, apakah institusi-institusi demokrasi di era Reformasi seperti partai politik, lembaga antikorupsi, komisi konstitusi, dan aktor-aktor yang memiliki pengaruh pada perkembangan demokrasi (government, civil society, dan kekuatan-kekuatan masyarakat sipil) menjadi aktor yang mendukung penguatan institusi demokrasi ataukah sebaliknya merusak demokrasi, melalui praktik-praktik korupsi.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar