
Yonky Karman
Dalam esainya "The End of History" (1989, 1992 bentuk buku), Francis Fukuyama, sosiolog Amerika, menjabarkan hipotesisnya tentang kemenangan demokrasi liberal dan pasar bebas bersamaan dengan berakhirnya era Perang Dingin antara blok Barat (AS dan sekutunya) dan blok komunis (Uni Soviet dan sekutunya).
Dalam perkembangannya, hipotesis itu digugurkan dua fakta yang di luar perhitungan Fukuyama. Yang pertama, bubarnya negara Uni Soviet berganti dengan Rusia di bawah Putin, yang tetap komunis dan muncul sebagai sebuah kekuatan baru yang tidak bisa didikte AS. Juga China yang komunis, semakin kokoh tak tergoyahkan, menantang hegemoni AS. Ideologi komunisme sintas dengan mengadopsi kapitalisme dan pasar bebas.

Geledah Rumah Terduga Teroris – Tim gabungan Densus 88, Brimob Kepolisian Daerah Jawa Timur, dan Kepolisian Resor Malang menggeledah dan menyita sejumlah barang bukti dari empat rumah terduga teroris di Kabupaten Malang, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Masa penahanan terduga teroris merupakan salah satu hal yang menjadi sorotan pada draf revisi RUU Terorisme.
Kompas/Dahlia Irawati (DIA)
20-02-2016
Menurut Jacques Derrida (Spectres de Marx, 1993), runtuhnya komunisme di Eropa Timur hanya kegagalan sebuah eksperimen hantu Marxisme. Sampai sekarang, komunisme masih tetap menarik di tempat-tempat yang tinggi ketimpangan sosialnya. Untuk kita, ideologi komunisme sudah kehilangan daya tariknya. Kalaupun narasi hantu-hantu Marx berusaha dihidupkan, itu sarat dengan kepentingan politik elektoral.
Mondialisasi terorisme
Yang relevan untuk kita dan mendesak adalah mondialisasi terorisme yang mengatasnamakan agama seperti diusung Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS). Istilah mondialisasi (gerakan yang mendunia) dipinjam dari Derrida dalam dialognya dengan Giovanna Borradori (Filsafat dalam Masa Teror, 143).
Terorisme sudah lama ada, tetapi tak pernah diperhitungkan dalam politik internasional sampai Tragedi 11 September 2001. Sejak itu, terorisme kuasi-agama berhasil mendikte pola politik hubungan bilateral AS. Selama era Perang Dingin, politik hubungan bilateral AS didasarkan pada afiliasi suatu negara dengan komunisme.

Sejumlah aparat dari Brimobda Sulteng berjaga di depan Rumah Sakit Bhayangkara tempat dua jenazah terduga teroris disemayamkan di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (4/4). Setelah menembak mati seorang terduga teroris pada Jumat (3/4), Sabtu (4/4) sore, kepolisian kembali menembak mati salah seorang terduga teroris yang diduga kelompok Santoso Cs di Jalur Kebun Kopi, Kabupaten Parigi Moutong.
Antara/Basri Marzuki
04-04-2015
Pasca Perang Dingin, politik bilateral AS didasarkan pada afiliasi suatu negara dengan terorisme, bahkan parameter demokrasi yang biasanya dipakai AS ternyata bisa diabaikan seperti hubungannya dengan rezim otoriter Pakistan ketika bersama-sama memerangi pasukan Taliban.
Dalam optimisme Fukuyama, kejayaan pasar bebas dan konsumtivisme menjadi saluran hasrat berperang yang destruktif, sehingga perdagangan meningkat, terutama untuk produk-produk elektronik. Lagi-lagi di luar perhitungan Fukuyama, rezim Taliban justru melarang pemakaian segala produk elektronik.
Afganistan tidak takluk oleh kapitalisme dan pasar bebas, melainkan akhirnya oleh mesin perang terlatih dan super canggih AS, ironisnya menghadapi para pejuang yang mengatasnamakan agama.

Warga dari berbagai golongan dan lintas agama mengikuti aksi solidaritas #KamiBersamaPOLRI di depan Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (10/5/2018) malam. Sebanyak lima orang anggota Polri gugur dalam peristiwa penyerangan oleh narapidana terorisme di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Kompas/Priyombodo (PRI)
10-05-2018
Alih-alih berakhir, sejarah justru berulang. Itulah sejarah kekerasan, sejarah teror. Sejarah berulang tetapi kita lambat belajar dari sejarah. Ketika kita masih berdebat sendiri apakah benar ada kamp pelatihan teroris di Sulawesi Tengah, Pemerintah Singapura sudah menerbitkan Buku Putih yang mudah diperoleh publik tentang struktur dan operasionalisasi organisasi teroris kuasi-agama.
Sampai sekarang tidak satu bom pun meledak di negeri yang menjadi salah satu pusat perdagangan dunia itu.

Seorang peserta aksi solidaritas untuk korban bom di Surabaya, yang diselenggarakan di Taman Suropati, Jakarta, Minggu (13/5/2018) malam, membawa bendera merah putih. Mereka berharap agar masyarakat Indonesia tetap bersatu melawan terorisme.
Alih-alih sejarah berakhir, mondialisasi terorisme kuasi-agama memulai sejarah baru dunia yang dihantui perang dengan modus baru melawan suatu kekuatan organisasi sel-sel tanpa bentuk, bukan perang antarnegara, tanpa penumpukan senjata. Musuh negara adalah warga sendiri yang memiliki ideologi berseberangan.
Sel-sel teroris memiliki mobilitas tinggi. Lokasi kediamannya sulit terdeteksi. Publik baru sadar lokasi mereka ketika aksi bom bunuh diri sudah terjadi atau ketika bom yang sedang dirakit meledak di kediaman sendiri. Senjata yang dipakainya mulai dari propaganda di media sosial sampai senjata konvensional dan bom rakitan, mungkin suatu kali senjata kimia atau senjata kuman.
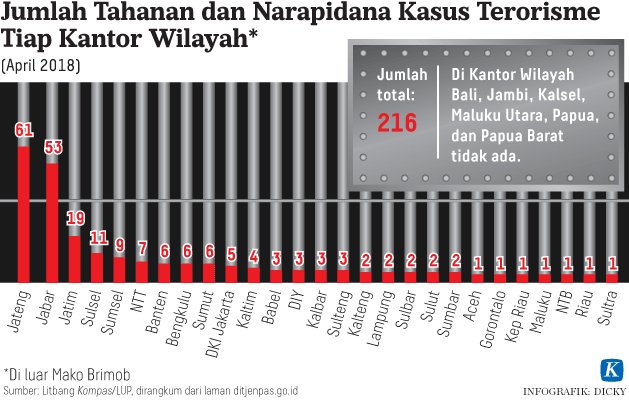
Aksi teror tidak hanya menyasar masyarakat sipil, tetapi juga polisi sebagai aparat negara di garda depan. Penegak hukum antiteror yang sangat terlatih disandera dan gugur justru di markas komando. Orang beribadah di Bait Tuhan menjadi sasaran bom. Benteng pertahanan rasa aman masyarakat hendak dijebol. Ada desain besar rekayasa sosial untuk menjadikan rasa takut sebagai hantu kehidupan, yang lebih nyata daripada di layar lebar.
Teror untuk negara
Kita tidak bisa hanya berlindung di balik retorika bahwa negara tidak akan kalah oleh terorisme. Target aksi teror memang bukan mengalahkan negara, melainkan menebar rasa takut. Antarkelompok masyarakat menjadi saling curiga. Rasa saling percaya tergerus. Rakyat akhirnya meragukan kemampuan pemerintah untuk menjamin rasa aman. Investor pun ragu-ragu berbisnis di Indonesia.

Suasana pemakaman Iptu Luar Biasa Anumerta Yudi Rospuji Siswanto di Taman Makam Pahlawan Kusumatama II, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Kamis (10/5/2018). Iptu Yudi merupakan salah satu anggota Polri korban aksi penyerangan oleh narapidana terorisme di Rumah Tahanan Cabang Salemba, Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (9/5/2018).
Dengan menumpuknya keraguan rakyat kepada pemerintah, diharapkan terbentuk opini bahwa pemerintah ini lemah (kalau perlu, layak diganti). Dengan menggerogoti otoritas negara, kaum teroris berharap negara melunak dalam perang melawan terorisme. Meski tidak besar, sel-sel teroris nyatanya dihadapi negara dengan alokasi sumber daya manusia dan dana yang besar sekali.
Fokus pemerintah untuk membangun negeri dibuat terpecah dengan berbagai program kontrateror. Persoalan terorisme adalah gangguan serius sehingga negara gagal fokus pada fungsi pokok "melindungi segenap bangsa Indonesia … untuk memajukan kesejahteraan umum" (alinea IV Pembukaan UUD 1945).

The situation at the house of First Insp. Yudi Rospuji Siswanto's parent in Penggarutan village, Bumiayu district, Brebes, Central Java Thursday (10/5/2018). Yudi was one of the five police personnel killed during terrorist attack at Mako Brimob detention center in Kelapa Dua, Depok, West Java on Wednesday.
Dari mana kekuatan kecil itu memiliki motivasi besar meneror negara, bahkan sampai rela mati? Keyakinan agama. Memang keyakinan agama tidak sama dengan agama, tetapi tidak bisa sama sekali dipisahkan. Kesadaran religius begitu dekat dengan kesadaran diri, bahkan kesadaran kolektif, sebagai kesadaran pertama (primordial), sebelum kesadaran berbangsa dan bernegara.
Secara historis, memang agama lebih dulu ada sebelum bentuk pemerintahan. Bahkan, ada keyakinan bahwa agama datang dari Tuhan sedangkan negara berasal dari konsensus manusia. Karena itu, untuk alasan yang lebih luhur dan universal (for a greater cause) orang beragama berani melawan (aparat) negara.

Sejumlah siswa sekolah di Kabupaten Badung, Bali, membubuhkan tanda tangan sebagai komitmen anti radikalisme dan terorisme di atas kain putih sepanjang 20 meter. Aksi ini merupakan rangkaian peringatan tujuh tahun peledakan bom Bali 1 Oktober 2005, di Nyoman Cafe, Jimbaran.
Benar arus utama agama di era modern tidak membenarkan kekejaman atas nama agama. Namun, agama di era pasar bebas juga bebas diyakini dengan berbagai cara, termasuk dengan cara-cara radikal. Teroris tak peduli aksinya dianggap biadab dan tidak dibenarkan agama, sejauh dibenarkan keyakinan agama. Bahkan, mereka menganggap yang paling tahu agama dan konsisten beragama. Karena yakin di jalan yang benar, mereka radikal dalam beragama. Dan, kesalehan mereka diakui lingkungan sosial.
Di AS juga ada kelompok radikal yang memperjuangkan terbentuknya suatu pemerintahan yang berdasarkan hukum-hukum agama (Frederick Clarkson, Eternal Hostility: The Struggle between Theocracy and Democracy, 1997). Namun, radikalisme agama di sana tidak mendapat lahan subur untuk berkembang sebab negara itu pada dasarnya sekuler.

Helmy Purnama Fauzi, simpatisan Negara Islam di Irak dan Suriah, yang menjadi terdakwa kasus terorisme terkait dengan peristiwa bom di Jalan MH Thamrin, Jakarta, mengikuti sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (15/11). Helmy divonis hukuman 4 tahun penjara.
Kompas/Yuniadhi Agung (MYE)
15-11-2016
Tidak begitu dengan Indonesia sebagai negara berketuhanan. Terorisme kuasi-agama merasa nyaman karena perjuangan politiknya dilihat oleh sebagian masyarakat sebagai perjuangan di jalan agama. Ada simpati masyarakat, bahkan secara terbuka. Sebagai bentuk radikal intoleransi, terorisme kuasi-agama kondusif di lahan praktik-praktik beragama yang toleran terhadap intoleransi.
Di sinilah akarnya. Toleran terhadap intoleransi. Ada porsi pemerintah, umat, dan pemuka agama. Hilangnya kewaspadaan dalam praktik beragama telah membuat anak-anak bangsa terpikat ideologi NIIS, pergi berjuang di luar negeri, kemudian kembali untuk memerangi bangsa dan negeri sendiri. Bahkan, orangtua berhasil menyatuhatikan anak-anaknya sehingga satu keluarga melakukan baiat bom bunuh diri.

Kepala Badan Nasional penanggulangan Teroris (BNPT) Komisaris Jenderal (Pol) Tito Karnavian (kedua kanan) dan Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT Irjen (Pol) Petrus Reinhard Golose (kanan) dalam The General Briefing on Counter Terorism di Jakarta, Selasa (19/4). Acara yang diikuti oleh sejumlah duta besar negara sahabat itu sebagai ajang bertukar informasi terkait penanganan teroris di tiap-tiap negara.
Kompas/Wisnu Widiantoro (NUT)
19-04-2016
Kompas, 16 Mei 2018

Tidak ada komentar:
Posting Komentar