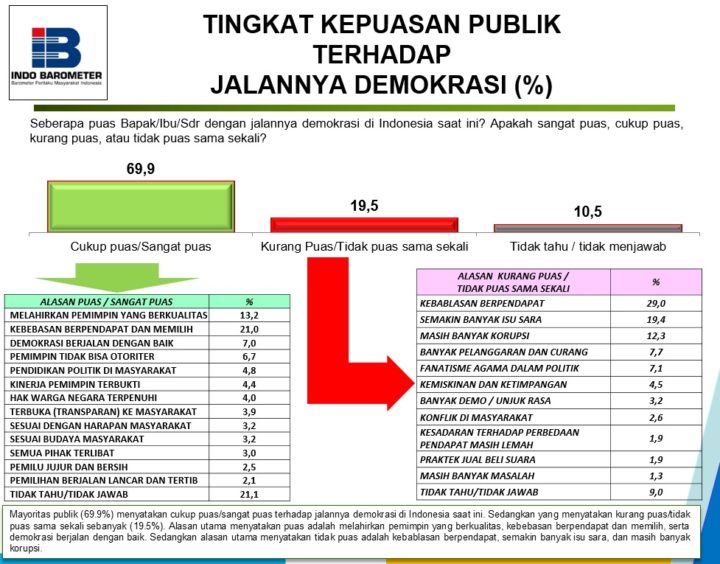
Setelah genap 20 tahun usia reformasi dan empat tahun berjalannya kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sekaranglah saat paling tepat untuk memberikan penilaian jujur tentang bagaimana penyelenggaraan kekuasaan mengawal dan berkomitmen terhadap demokrasi.
Oleh karena itu, apa yang telah dilakukan Presiden baru-baru ini menemui komunitas media sosial, korban pelanggaran HAM, ataupun para akademisi dan pengamat politik adalah tepat. Mengingat kepemimpinan yang baik diukur dari tidak hanya kemampuan seorang pemimpin dalam bekerja, tetapi juga kemauan mendengarkan evaluasi atas apa yang sudah dikerjakan.
Pertemuan antara Presiden dan aktor-aktor strategis masyarakat sipil di satu sisi rentan dimaknai sebagai proses kooptasi politik. Namun, realitas politik tidak selalu bercorak penundukan dan kooptasi. Dialog bersama antara pemimpin dan rakyatnya juga bisa berlangsung dalam praktik komunikasi yang merdeka. Saat ini waktu yang tepat untuk duduk, mendengar, dan menyikapi aspirasi dari bawah oleh pemimpin. Sebuah langkah pembuka untuk meneguhkan komitmen atas proses demokrasi.
Sehubungan dengan pertimbangan atas komitmen penyelenggara negara terhadap proses demokrasi, setidaknya ada dua sisi dari satu keping mata uang demokrasi yang patut dipertimbangkan. Pertama, komitmen negara terhadap demokrasi sebagai pengelolaan tatanan sosial. Kedua, komitmen negara memfasilitasi demokrasi sebagai laku partisipasi.
Dalam perbincangan publik selama ini, demokrasi kerap dimaknai berbenturan dengan pengelolaan tata sosial. Penghadap-hadapan antara demokrasi dan tata sosial dalam konteks pengalaman bernegara di Indonesia memang dapat dimaklumi. Ini mengingat selama 32 tahun di bawah rezim Orde Baru, tata sosial selalu dimaknai sebagai pembungkaman saluran-saluran partisipasi politik. Merawat tatanan sosial pada masa lalu identik dengan teror kekerasan negara terhadap mereka yang kritis.
Namun, hal yang luput dipertimbangkan bahwa demokrasi dan hal-hal substansial di dalamnya, yakni kebebasan dan partisipasi, adalah buah dari keberhasilan pengelolaan tata sosial dalam negara demokrasi. Jadi, demokrasi bukan hanya perlu diperdalam, demokrasi juga perlu dilindungi dari kekuatan-kekuatan di luar dirinya yang berusaha menghancurkan tatanan demokrasi.
Dalam konteks seperti ini, beberapa kebijakan pemerintah untuk menangkal ancaman terhadap tata sosial negara demokrasi, seperti Perppu Ormas dan UU Antiterorisme, dalam dirinya tidak harus dimaknai bertentangan dengan demokrasi. Sebab, hadirnya rasa aman dalam negara demokrasi adalah prasyarat utama demokrasi.
Landasan penting bagi tugas selanjutnya adalah jaminan kesetaraan ataupun kebebasan politik dari setiap warga negara. Yang absen dari inisiatif perundang-undangan dari negara adalah argumen-argumen demokrasi untuk menghubungkan tugas menjamin keamanan negara dan penyelenggaraan tatanan demokrasi.
Karena itu, patut pula negara belajar pada negara-negara Eropa, seperti Jerman, Inggris, atau Yunani, yang memperkuat argumen demokrasi untuk bertindak tegas terhadap kelompok fasis sayap kanan yang mengancam demokrasi.
Demokrasi dan partisipasi
Demokrasi sebagai pemenuhan hak-hak warga negara dan keterlibatan partisipatoris warga bukanlah imperatif abstrak, tetapi hidup dalam laku budaya masyarakatnya. Oleh karena itu, selain pengawalan atas tata sosial, demokrasi hanya dapat hidup dalam praktik kehidupan berkomunitas, yang ditandai hadirnya solidaritas sosial sebagai napas hidupnya.
Satu hal yang patut dipertimbangkan terkait dengan eksplosi fanatisme dan sikap antidemokrasi, terutama di kalangan kelas menengah urban, adalah absennya solidaritas bersama. Hal ini dapat ditemui, misalnya, dalam kehidupan di kampus-kampus. Maraknya ketertarikan mahasiswa baru terhadap fenomena fanatisme beragama terjadi dalam suasana alienasi sosial, ketika komunikasi yang terbuka dan lintas budaya tidak terjadi, dan setiap orang berlindung di balik kepompong identitasnya untuk dapat eksis secara sosial.
Tentu negara tak boleh diam. Inisiatif-inisiatif yang dapat dilakukan oleh negara berupa fasilitasi atas kerja-kerja budaya antarkomunitas sosial untuk menggali lebih dalam tradisi-tradisi yang menyejarah dan berakar pada memori kolektif kewargaan, memperkuat solidaritas dan partisipasi sosial agar demokrasi dapat tumbuh sehat dan dinamis.
Kerja konkret yang dapat dilakukan dapat berupa mendorong institusi seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Direktorat Jenderal Kebudayaan, atau lembaga terkait agar membangun narasi demokratik dan hadir dalam komunitas sosial. Juga melibatkan mereka menggali tradisi historis berbudaya, bersama dengan budayawan dan akademisi lokal, untuk mengelaborasi kearifan dan pengetahuan di tingkat lokal, merenung dan berdialog bersama untuk merawat harapan dan menjaga ketahanan budaya berdemokrasi.
Strategi kebudayaan seperti inilah, misalnya, yang pernah diselenggarakan oleh AS pada era Franklin Delano Roosevelt (FDR) ketika mayoritas warganya mengalami krisis sosial sejak depresi besar 1929. Formulasi New Deal dari FDR untuk melawan krisis sosial tidak saja terbumikan melalui penguatan kebijakan struktural, juga strategi kebudayaan berupa pelibatan para budayawan, akademisi, tokoh masyarakat yang saling terkonsolidasi untuk merawat harapan melewati krisis dan menemukan kehidupan lebih baik (Nussbaum, 2013).
Langkah-langkah kebijakan strategis di atas tentu tidak mudah untuk diimplementasikan mengingat problem sosial yang terjadi di era reformasi tidak terlepas dari problem relasi kekuasaan yang menghambat capaian-capaian demokrasi.
Meski demikian, seperti pernah diutarakan intelektual inisiator cultural studies Raymond Williams, sikap progresif ditentukan oleh seberapa kuat kita berjuang di atas harapan dalam kondisi yang dianggap tidak mungkin, daripada meyakinkan bahwa ketiadaan harapan itu begitu pasti!
Airlangga Pribadi Kusman Staf Pengajar Departemen Politik Universitas Airlangga; Direktur Initiative Institute
Kompas, 12 Juni 2018

Tidak ada komentar:
Posting Komentar