
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjukkan pernyataan pengenaan tarif untuk baja dan aluminium impor. Ia menandatangani pernyataan itu, Kamis (8/3/2018) lalu di Gedung Putih, Washington DC. Inilah salah satu momen awal dari perang dagang dunia.
Bak mantra sihir, kata globalisasi ekonomi kian populer di tengah euforia bangsa-bangsa yang waktu itu baru saja menyelesaikan tujuh tahun perundingan Putaran Uruguay/GATT. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang juga lahir di akhir perundingan itu selain didesain menjadi badan dan forum resmi perdagangan dunia, juga difungsikan sebagai pengelola seabrek persetujuan yang telah dihasilkan sebelumnya dalam berbagai putaran perundingan di bawah payung Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT).
Kelahirannya kala itu juga bagai menyemai optimisme baru di tengah semangat untuk menata kehidupan ekonomi dunia melalui perdagangan yang adil dan dilakukan secara berkeadilan. Fair trade?
"Fair trade"
Mungkin juga sudah jadi pengetahuan umum, ketika sebagai kosakata baru, fair trade berkembang sebagai pangkal pikir dan titik tolak bagi sebagian bangsa dalam upaya membangun tatanan kehidupan ekonomi dunia yang baru. Bukan pula rahasia ketika kosakata itu lahir sebagai tandingan, sekaligus konsep perjuangan di tengah konsepsi perdagangan bebas (free trade) yang lama sebelumnya telah digunakan sebagian besar bangsa di dunia, dan tumbuh dari paham ekonomi klasik yang lama digelutinya.
Namanya saja berbeda. Gesekan atau bahkan benturan pasti ada. Walau norma umumnya dipahami, saling terbuka dan saling memberi, tetapi soal praktik, bisa lain lagi. Dengan alasan kepentingan nasional, atau apapun lainnya, kata fair atau adil juga mudah bertukar makna sesuai waktu dan kebutuhan.

Seorang pekerja berjalan melewati gulungan kawat baja di sebuah pabrik di Nantong, Provinsi Jiangsu, China, Selasa (3/7/2018). Ketegangan perdagangan antara China dan Amerika Serikat mengarah pada situasi perang dagang yang memengaruhi banyak negara.
Ketika benturan terjadi dan berlarut tanpa penyelesaian cepat, yang terbentang lantas bayang-bayang pertikaian dagang atau bahkan perang dagang. Perselisihan dagang Amerika Serikat (AS) dengan China, Uni Eropa (UE), ataupun dengan sekutu tetangga seperti Kanada dan Meksiko akhir-akhir ini, memberi gambaran hal itu.
Mereka bersitegang karena salah satu rekan dagang yang bertindak sepihak dengan alasan kepentingan nasional, lantas dinilai sebagai tak fair oleh pihak yang lain. Yang merasa diperlakukan tak adil, bersiap membalas. Pendek kata, dalam konteks fairness tadi—meskipun yang bertikai sama-sama pendekar free trade—masing-masing memaknainya secara berbeda. Dalam perdagangan bebas, kata adil secara leluasa dimaknai sesuai kepentingan.

Para buruh mengisi baja pesanan untuk dikirim ke Pacific Machinery & Tool Steel Company, Pacific Northwest, pada 6 Maret 2018 di Portland, Oregon. Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa dia bermaksud memberlakukan tarif impor baja dan aluminium, yang memicu kekhawatiran bahwa tindakan semacam itu dapat memicu perang dagang.
Sengketa yang tereskalasi menjadi perang dagang mungkin terjadi bila berlangsung tindakan balasan. Tindak pengenaan tarif bea masuk yang tinggi atau bea tambahan untuk satu atau lebih komoditi impor, dibalas dengan tindakan serupa walau bisa saja secara silang. Pembatasan pasar untuk satu atau lebih komoditi ekspor, dibalas pula dengan tindakan serupa, atau malah penutupan pintu bagi ekspor komoditi tertentu, atau pembatalan kontrak pembelian.
Secara esensial, tindakan balasan serupa itu lazim dilakukan hanya ketika pihak yang dirugikan memiliki perhitungan dan sikap yang matang, kebijakan yang kukuh, serta kekuatan nyata yang dapat diberlakukan secara efektif dan apalagi seketika. Proses dan formulasi sikap, kebijakan dan kekuatan yang lahir dari sinergi internal antara pemerintah dan pelaku ekonomi nasionalnya.
Dalam kondisi serupa, dan ini juga berlaku bagi Indonesia, bisa saja sikap, kebijakan dan kekuatan riil yang terbentuk memiliki fungsi deterrent dan perang dagang tak jadi berlangsung. Dalam kondisi seperti itu pula pemecahan yang saling menguntungkan biasanya bisa dihasilkan.
Kasus minyak sawit
Contoh kasus konkret tadi menjadi cermin yang baik untuk melihat bagaimana konsep fair trade sebaiknya ditimbang dalam hubungan dagang RI–UE. Arif Havas Oegroseno, mantan duta besar RI untuk Belgia dan UE telah menulis dengan rinci dan terang benderang di harian ini (4/6/2018) bagaimana unsur fairness ditinggalkan UE.
Pendukung perdagangan dunia seperti UE, penopang utama prinsip-prinsip WTO seperti non-diskriminasi dan transparansi, tetapi dalam dua bulan terakhir berteriak tentang keadilan ketika 'dizalimi' AS, justru selama itu pula—dan hingga kini—sedang bertindak tidak adil dan diskriminatif dalam kasus ekspor minyak sawit Indonesia.

Delegasi Uni Eropa (UE) mengunjungi Hutan Harapan yang merupakan hutan hujan tropis yang direstorasi PT Restorasi Ekosistem Konservasi Indonesia di Kabupaten Batanghari, Jambi, Rabu (18/4/2018). Delegasi Uni Eropa meminta keseriusan seluruh pemangku kepentingan menjaga keragama hayati hutan hujan tropis terutama dari perambahan hutan untuk dijadikan perkebunan sawit.
Kompas/Albertus Hendriyo Widi (HEN)
18-4-2018
Mengupas 10 fakta yang menelanjangi sikap tak adil UE terhadap komoditi andalan RI dengan data yang obyektif, mungkin baru sekali itu dipaparkan Havas ke publik. Pertanyaannya: lantas apa dan bagaimana? Berharap sikap tak adil UE berubah melalui pendekatan diplomasi, seperti selama ini, mungkin masih akan menjadi 'perjalanan jauh yang belum kelihatan ujungnya'.
Meminjam kata dari kazanah teater, bagai menunggu godot. Tanpa mengecilkan arti hasil pendekatan yang bernama penundaan, hal itu belumlah mengubah sikap UE. Impak yang ada hanya membantu mendinginkan keadaan. Sifatnya sementara. Mengapa demikian ?
Sikap UE yang secara substantif berakar pada kebijakan subsidi, erat berkaitan dengan faktor peran serta dukungan kelompok petani dan industri pengolah hasil pertanian seperti minyak kedelai, biji bunga matahari dan lainnya. Sikap tersebut berakar kuat dalam politik nasional negara-negara anggota UE ataupun non-UE lainnya.
Singkatnya, kebutuhan konkret untuk membela dan melindungi kepentingan nasional di negara-negara anggota UE ataupun non UE, adalah sikap politik yang sangat mungkin sulit dapat berubah hanya oleh pendekatan diplomatik.

Delegasi Uni Eropa yang diketuai Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend (batik biru) mengunjungi pengelolaan perkebunan kepala sawit berkelanjutan di perkebunan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, Senin (16/4/2018). Kegiatan yang difasilitasi Kementerian Luar Negeri itu bertujuan untuk memaparkan fakta pengelolaan sawit berkelanjutan secara langsung kepada Uni Eropa.
Mungkin banyak yang terkecoh oleh predikat negara industri, tetapi senyatanya dunia politik negara-negara Eropa tak pernah bisa lepas dari pertanian dan dukungan politik para petaninya. Topangan dan sekaligus sandaran politik yang bahkan menentukan. Subsidi bagai ijon politik para petani mereka. Karenanya, bila di Jakarta berkembang tesis bahwa itu semua baru resolusi parlemen UE, dan belum merupakan keputusan dewan eksekutifnya, lama kelamaan terasa bagai sekadar menghibur diri. Mudah-mudahan saja bukan malah menipu diri.
Menghadap sikap yang berakar dalam kepentingan politik nasional negara-negara UE, berlebihankah kalau juga disiapkan sikap serupa, yang secara subtantif juga merepresentasi kepentingan nasional Indonesia? Mencari pasar alternatif (sementara pasar ekspor minyak sawit lainnya yang besar seperti India juga mengalami hambatan karena India menaikkan tarif bea masuk) pastilah bukan kerja sederhana dan cepat menuai hasil.

Delegasi Uni Eropa (UE) mengunjungi Hutan Harapan yang merupakan hutan hujan tropis yang direstorasi PT Restorasi Ekosistem Konservasi Indonesia di Kabupaten Batanghari, Jambi, Rabu (18/4/2018). Delegasi Uni Eropa meminta keseriusan seluruh pemangku kepentingan menjaga keragama hayati hutan hujan tropis terutama dari perambahan hutan untuk dijadikan perkebunan sawit.
Kompas/Albertus Hendriyo Widi (HEN)
18-4-2018
Bersandar pada komoditi non migas lain sebagai pengganti kontributor sumber devisa ekspor, juga tak semudah membalik tangan. Apalagi, semua itu terjadi di tengah upaya besar menggenjot pendapatan devisa untuk memperkuat keuangan negara. Menggantinya dengan program hilirisasi domestik, dari dulu juga masih sekadar retorika kosong, yang seolah tidak sulit sama sekali. Singkatnya, yang namanya pengganti, serba tidak sederhana dan tidak semudah diomongkan. Lantas bagaimana ?
Kalau berusaha bersikap baik masih terus diplintir, kalau bersikap non konfrontatif dianggap lemah, dan kalau diam malah dianggap salah, mengapa tidak mengubah sikap? Bukankah kepentingan yang terancam secara tidak adil itu konkret? Kalaupun alasan yang ditembakkan adalah soal lingkungan, ataukah deforestasi, penyelamatan gambut, ataukah kehidupan masyarakat sekitar hutan yang termarjinalkan, bukankah argumentasi seperti diungkap Dubes Havas, dapat dibuka luas di forum manapun ?
Mungkin saatnya menimbang ulang apa Indonesia masih perlu meneruskan peran dan tampilan nice boy dalam banyak percaturan antarbangsa. Kalau masalahnya isu lingkungan, deforestasi atau pengelolaan gambut, bukankah kita bisa mengurus sendiri, atau dengan upaya dan sumber lain? Syukur-syukur, semuanya dapat dilakukan dengan daya sendiri dan dengan irama/tempo yang sesuai kemampuan dan kepentingan sendiri. Yang penting tanpa harus pagi sore berharap siraman janji bantuan yang nyatanya tak kunjung terpenuhi, tapi ujung-ujungnya malah menjerat gerak dan kepentingan nasional.
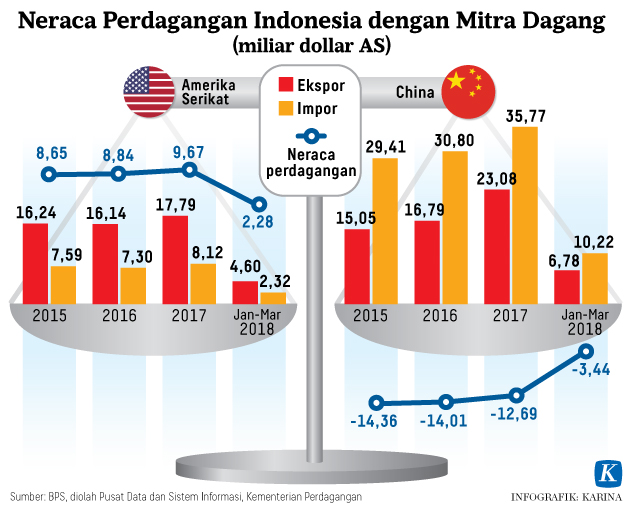
Sikap, kebijakan dan kekuatan berbasis sinergi nasional
Bersikap melawan tidak harus berarti akan berkelahi. Tetapi baik diingat, sikap UE dan China terhadap tindakan sepihak AS, juga berfungsi deterrent bagi kemungkinan terjadinya perang dagang di antara mereka. Namun yang penting, mewujudkan sikap, kebijakan dan tindak secara sama, berbasis sinergi yang konkret antara pemerintah dan dunia usaha/Kadin Indonesia, agar Indonesia juga mampu mewujudkan kekuatan deterrent tadi.
Bukan sekadar teriak ancaman boikot impor salmon, tetapi jangan-jangan belakangan diprotes sendiri oleh dunia usaha restoran dan hotel. Bukan pula sekadar ancaman pembatalan pembelian pesawat airbus ataupun komponennya, namun belakangan dikerubuti keluhan dunia penerbangan nasional. Bukan gertak pembatalan pembelian barang-barang modal, tetapi kemudian menghadapi keluhan dunia usaha industri atau investasi lainnya.

Lebih dari semua itu, pasti akan lebih baik bila pemerintah dan Kadin Indonesia memulai langkah untuk mewujudkan sinergi tadi. Sinergi yang mampu menghasilkan sikap membela kepentingan dengan kekuatan yang konkret dan berlandaskan kebutuhan bersama, dengan dukungan semua pemangku kepentingan. Sikap, kebijakan dan kekuatan yang nyata dan dapat dieksekusi.
Sikap, kebijakan dan kekuatan substantif yang secara bulat dan nyata didukung segenap masyarakat dan dunia usaha nasional. Bukan sinergi formal yang sekadar berujung pada kehadiran Presiden di kongres atau rapat kerja Kadin atau audiensi kepada Presiden di Istana.

Wakil Presiden Komisi Eropa Jyrki Katainen berbicara saat konferensi pers di Beijing, China, Senin, 25 Juni 2018. Wakil presiden badan pengurus Uni Eropa mengatakan Eropa dan China akan membentuk kelompok yang bertujuan memperbarui aturan perdagangan global untuk mengatasi kebijakan teknologi , subsidi dan keluhan lain yang muncul dalam upaya untuk mempertahankan dukungan untuk perdagangan internasional.
Bilamana mengamankan pendapatan ekspor terbesar, yang sekaligus menyangkut soal lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan rakyat adalah kepentingan nasional, mungkin saatnya pula semua benar-benar bicara sederhana dan jelas dalam soal ini. Sama sederhana dan jelasnya kalau bicara tentang pentingnya memelihara lingkungan, hutan dan gambut secara lestari, seraya terus memelihara aspek keadilan sosial.
Bicara sederhana dan jelas bahwa substansi kepentingan nasional adalah masalah internal, yang mesti diselesaikan dan didukung secara internal pula.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar