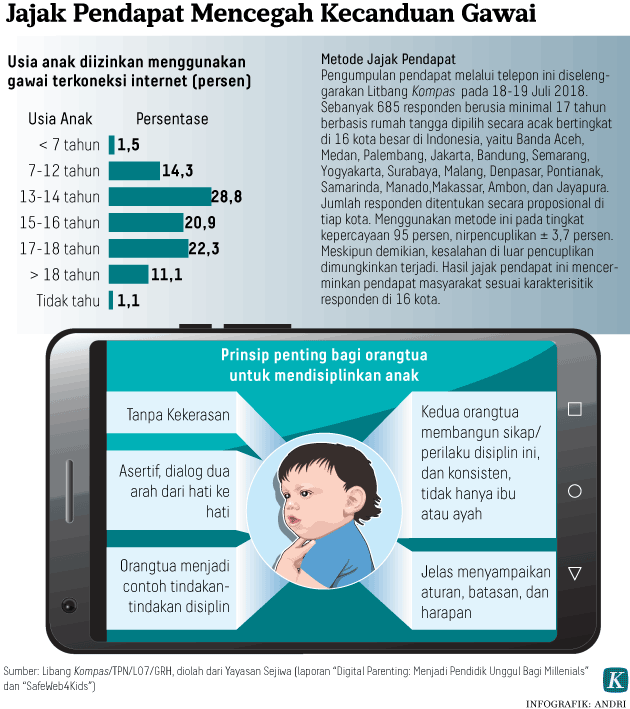
Sulit dipercaya tetapi sungguh terjadi bahwa gawai, seperti telepon genggam, telah menimbulkan permasalahan dalam masyarakat kita. Alat itu memang penuh pesona bagai tongkat ajaib yang dapat dipakai untuk memudahkan hidup kita. Namun, alat ini juga membuat penggunanya kecanduan seperti ketagihan narkoba. Anak-anak juga menjadi korbannya.
Orangtua bingung menghadapi perubahan perilaku anak-anaknya akibat ketagihan gawai (Kompas, 23-26/7/2018). Kita mulai sering membaca soal penyakit-penyakit baru akibat pemakaian gawai. Istilah seram, seperti internet-gaming disorder, cyberchondria, cybersex, cybersuicide, compulsive online-shopping,dan cyberbullying,mulai tercantum dalam klinik -klinik psikoterapi. Ujaran kebencian dan hoaks yang membuat gaduh jagat politis sebagian juga hasil patologis pemakaian gawai.
Sebaiknya, kita tidak melepaskan fenomena tersebut dari konteks yang lebih luas dan mendasar, yaitu cara berpikir dan cara berada kita di zaman ini. Sudah lama manusia terpesona dengan cara berpikir kalkulatif. Menghitung, seperti dilakukan dalam matematika, ilmu alam, bisnis, birokrasi, bahkan juga politik, didaulat sebagai kekuatan utama untuk sukses. Teknologi, termasuk information and communication technologies (ICT), mementaskan cara berpikir ini dan mengemasnya dalam tombol-tombol gawai.
Berpikir kalkulatif tentu sangat diperlukan. Kita sulit hidup tanpa menghitung. Namun, kerap luput dari perhatian bahwa cara berpikir ini mereduksi banyak hal sehingga kita tidak lagi sensibel terhadap persoalan eksistensial. Jika ia jadi dominan, kita menjadi enggan merenungkan makna hidup kita. Karena itu, metafisikus Jerman abad ke-20, Martin Heidegger, menyebut berpikir kalkulatif "ketidakberpikiran" dan bahkan "lari dari berpikir". Daripada cemas memikirkan perkara-perkara eksistensial, seperti alasan dan tujuan hidup kita, lebih asyik melarutkan diri ke dalam gim daring.
Lebih dari alat
Gawai adalah alat, sarana untuk tujuan-tujuan. Namun, cermatilah. Peranti itu berbeda dari alat-alat lain, misalnya cangkul. Cangkul tetap di luar diri kita dan tidak mengambil bagian-bagian diri kita. Kita tetaplah diri kita saat menghadapi cangkul. Tak demikian dengan telepon genggam. Kita tak mempermainkannya, melainkan bermain dengannya. Bersamanya kita berpikir. Juga tak jarang kita merasakan hal-hal melaluinya.
Sikap kita terhadap gawai berbeda dari sikap kita terhadap alat-alat lain. Kita tidak hanya memakainya seperti cangkul. Kita juga membiarkan diri dipakai oleh alat itu. Bagian-bagian diri kita, seperti isi pikiran, ungkapan perasaan, keyakinan, penilaian, gambar diri, diambil dan diolah oleh peranti itu. Kita bahkan rela menyerahkan rahasia dan kehidupan privat kita kepadanya. Telepon genggam telah menjadi semacam alter ego. Ia tidak hanya mengganti peran orangtua, guru, teman, pemilik toko; ia dikira dapat mengisi ceruk hampa jiwa. Makin defisit makna jiwa itu, selfie dan pamer diri makin rajin dilakukan. Makin pintar telepon itu, pengguna makin enggan memakai pikirannya sendiri.
Ke dalam gawai kita menyimpan relasi-relasi, komunikasi-komunikasi, dan juga uang kita. Kita takut kehilangan peranti yang telah menjadi alter ego bagi kita ini. Tanpanya kita gelisah karena takut ketinggalan informasi atau kehilangan kontak. Praktis kita telah mendelegasikan banyak hal kepadanya. Dia mengasuh anak kita, mengganti peran guru, teller bank, kasir toko, dan mungkin juga pacar. Akibatnya, kita melekat padanya dan membiarkannya memerintah kita. Tanpa disadari, hubungan kita dengan gawai tak relaks, tetapi tegang.
Jangankan kehidupan privat, politik demokratis kita akhir-akhir ini juga sulit dipisahkan dari telepon genggam. Apa yang disebut "suhu panas" tahun politik, yakni survei-survei elektabilitas kandidat, komentar-komentar nyinyir, hoaks, ujaran-ujaran kebencian, punya dasar materialnya pada banyaknya pulsa dan panasnya baterai ponsel. Copot baterai dan kartu SIM, maka kegaduhan pun reda, cyber army lenyap, dan mungkin jiwa bisa lebih bahagia. Akhir-akhir ini agaknya tidak ada alat yang lebih politis daripada telepon genggam, sampai-sampai media-media arus utama pun merasa perlu mengacu pada komentar warganet. Telepon pintar jelas merupakan alat menegangkan. Sayangnya, mogok ponsel belum menjadi gerakan politis.
Dapat dimengerti jika Heidegger menganggap teknologi adalah cara berada kita dewasa ini. Hal itu sangat pas untuk ponsel. Tak perlu membayangkan situasi terkoneksi secara komprehensif yang disebut internet of things (IOT). Besarnya populasi pengguna ponsel di masyarakat kita pun sudah cukup untuk membuat kita memandang dunia seperti ponsel. Misalnya, kita mengira tahu politik, tapi "tahu" di sini juga hasil filtrasi dan konstruksi survei, komentar, opini lewat sistem ICT yang sampai ke ponsel. Kita berada dengan cara terkoneksi dengan media. Dalam sistem interkoneksi itu bukan alat tersedia bagi kita, melainkan kita tersedia bagi alat sebagai alat yang juga siap memperalat hal-hal lain sebagai alat. Kondisi ini disebut Heidegger Gestell (terbingkai).
Membiarkan alat tetap alat
Kita perlu relaks dengan gawai. Relaks adalah sebuah sikap, dan sikap mengandaikan cara berpikir dan bahkan cara berada. Hampir mustahil melawan arus besar teknologisasi masyarakat, tetapi tidak mustahil mengambil sikap yang tepat terhadap alat-alat sehingga alat-alat itu tetap alat bagi kita. Jadi, kita tetap memakai telepon pintar, tetapi menggunakannya dengan pintar juga sehingga kita tetap bebas darinya.
Untuk menjelaskan sikap yang tepat itu, Heidegger bicara tentang Gelassenheit. Kata ini berarti membiarkan (lassen), ketenangan, penjagaan keseimbangan jiwa. Untuk kata Jerman itu, kita punya kata dengan muatan religius, "ikhlas" dan "keikhlasan". Ada kesadaran religius yang disimpan dalam kata itu, bahwa barang-barang di dunia ini nisbi terhadap Sang Pencipta, maka sewaktu-waktu harus kita lepaskan. Agar relaks dengan gawai, kita perlu bersikap ikhlas. Sikap ini tidak timbul dari berpikir kalkulatif, tetapi dari berpikir meditatif, berpikir dengan fokus dan peduli pada keberadaan kita di dunia ini. Kita—demikian kata Heidegger tentang peranti-peranti—"membiarkan mereka pergi setiap waktu" atau "membiarkan mereka sendirian saja sebagai yang tidak memengaruhi jati diri kita".
Kita membutuhkan telepon genggam. Ketika menyadari hal itu, kita sekaligus menyadari seberapa jauh kita telah diperhamba oleh peranti itu, sampai-sampai jati diri kita diubahnya. Telepon pintar di genggaman pengguna yang malas berpikir tidak menghasilkan manusia reflektif, tetapi manusia refleks. Refleks itu mekanistis dan memaksa memperalat orang lain. Sikap relaks membutuhkan rehat dari refleks. Gawai kita biarkan tetap sebagai alat dan tak perlu mengganggu integritas kita. Rehat dari refleks akan memungkinkan kita mendengarkan dan mencermati sekeliling kita lebih baik.
Gelassenheit, keikhlasan, membuka horizon baru yang lebih luas dan kaya daripada persepsi termediasi internet dalam genggaman. Mengacu Heidegger lagi, keikhlasan dan "keterbukaan terhadap misteri" adalah satu dan sama. Keikhlasan memungkinkan kita takjub dan bersyukur akan keberadaan kita sehingga ponsel tak lagi dipakai sebagai pelampiasan defisit harga diri kita. Baru dalam horizon keikhlasan ini, gawai akan tinggal sebagai alat yang tak merusak jati diri kita. Hubungan kita dengannya—memetik perkataan Heidegger—"menjadi sederhana dan relaks".

Tidak ada komentar:
Posting Komentar