Debat ketiga pemilihan presiden pada 17 Maret 2019 menjadi momen untuk menguji komitmen pendidikan mereka. Ada tiga persoalan fundamental pendidikan yang menjadi tantangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Pemahaman mendalam akan kegawatdaruratan persoalan, pemikiran rasional argumentatif didukung bukti- bukti yang meyakinkan, dan solusi rasional obyektif yang bisa dipahami publik, sangat dibutuhkan di tengah perdebatan yang cenderung jatuh pada model argumentum ad hominem (menyerang orangnya, bukan argumennya), dan simplifikasi tanpa argumentasi. Ketiga persoalan itu adalah sebagai berikut.
Pembelajaran otentik
Pertama, kualitas pembelajaran otentik. Pertanyaan dasarnya adalah bagaimana capres dan cawapres mendesain kebijakan pendidikan nasional yang efektif mengembangkan kultur pembelajaran otentik agar peserta didik dapat bertahan hidup dan bersaing di tengah tantangan global dan Revolusi Industri 4.0? Kualitas pembelajaran anak-anak kita tidak otentik karena sistem kurikulum kita saat ini mengunci proses pembelajaran dan pengajaran yang mematikan kreativitas dan inovasi.
Kurikulum membebani pendidik dan peserta didik dengan banyak mata pelajaran (terutama untuk sekolah dasar), luasnya isi materi pembelajaran, sehingga tidak memiliki prioritas apa yang dianggap penting dalam setiap tahapan proses pendidikan. Kurikulum saat ini membebani guru dengan berjibun administrasi sehingga tak fokus mengajar.
Sekolah terbebani pemenuhan delapan Standar Pendidikan Nasional yang tak semuanya terkait fokus pembelajaran otentik yang menjadi hasil pendidikan. Disparitas kualitas pendidikan antara pusat dan daerah masih tinggi. Situasi ini diperparah rendahnya kualitas guru. Ada 491.000 guru yang belum memenuhi kualifikasi sarjana strata 1, 736.000 guru honorer dengan kualitas pas-pasan yang terkatung-katung nasib dan pengabdiannya selama ini. Mereka ini selalu khawatir esok akan makan apa.
Dari sisi penyediaan calon guru, saat ini ada sekitar 1,3 juta calon guru, tersebar di lebih dari 300 lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang kualitasnya sebagian besar memprihatinkan, yang meluluskan rata-rata 250.000 calon guru setiap tahun, sementara kuota lapangan kerja terbatas. Guru pensiun diperkirakan sekitar 75.000 per tahun. Gambaran menjadi pengangguran sudah jelas terbayang dari lulusan LPTK ini.
Dari sisi penilaian, sistem penilaian kita sangat gelojoh dengan standardisasi, menjadikan individu bagaikan hasil produk industri yang ditera dengan standar yang sama melalui ujian nasional (UN), ujian sekolah berstandar nasional (USBN), sistem kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang menjadikan kita tidak bisa melihat lagi secara obyektif mana siswa cerdas, mana siswa yang kurang cerdas, karena secara minimal mereka akan memperoleh nilai yang sama dalam rapor sehingga obyektivitas nilai tak ada lagi. Kebijakan KKM juga menghapus konsep kecerdasan plural karena seolah setiap anak harus memiliki kecerdasan minimal dalam bidang-bidang tertentu. Ini jelas melawan kodrat manusia.
Era Revolusi Industri 4.0 seharusnya membuka mata kita untuk segera merevisi Kurikulum 2013. Apa kata dunia jika kita sudah hidup di tahun 2019, sementara kita mempergunakan Kurikulum 2013? Kesan ketertinggalan inilah yang akan kita punya! Lebih dari sekadar ganti nama, kompetensi dasar dalam Kurikulum 2013 juga belum mempersiapkan anak-anak kita menghadapi tantangan pendidikan era Revolusi Industri 4.0. Ini adalah tantangan pertama capres dan cawapres untuk meningkatkan kualitas pembelajaran otentik anak-anak Indonesia demi masa depan.
Visi kebinekaan
Kedua, pilpres telah memecah belah persatuan atas nama kepentingan politik. Politik identitas mengancam kebinekaan bangsa. Hoaks dan ujaran kebencian bertebaran di media sosial dan dunia maya. Indonesia yang bineka akan sulit bertahan jika politik identitas yang dimainkan kedua capres dan cawapres memolarisasi kelompok-kelompok berdasarkan kepentingan. Rusaknya kebinekaan, munculnya gerakan intoleran dan radikal, menjadi ancaman serius pendidikan kita. Bagaimana capres dan cawapres mendesain kebijakan pendidikan yang memperkuat kebinekaan, mengokohkan persatuan, menghargai perbedaan demi Indonesia yang damai dan sejahtera?
Ancaman atas ideologi dan identitas kebangsaan adalah nyata. Sejak 10 tahun terakhir, muncul gejala sekolah-sekolah menengah atas negeri menjadi pusat penyemaian intoleransi, eksklusivitas, anti- Pancasila, anti-kebinekaan, bahkan kekerasan dalam berbagai bentuknya (Farha Ciciek: 2008; Maarif Institute: 2011). Penelitian Setara Institute pada 2015 cukup mencengangkan. Pasalnya, 7,6 persen pelajar di DKI Jakarta dan Bandung setuju dengan ideologi dan sepak terjang Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). Riset ini juga mengungkap bahwa 8,5 persen dari 684 responden pelajar setuju untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan agama tertentu.
Pengalaman penulis membantu gerakan deradikalisasi untuk guru dan kepala sekolah di BNPT pada 2014 menunjukkan bahwa intoleransi dan radikalisme itu bisa berawal dari pucuk pimpinan di satuan pendidikan, yaitu kepala sekolah. Bahkan, ada indikasi beberapa LPTK menularkan paham intoleran dan radikal.
Pada 2016, Setara Institute menggelar survei toleransi pelajar Indonesia dengan melibatkan 760 responden pelajar SMA negeri di Jakarta dan Bandung, Jawa Barat. Survei menyimpulkan, 35,7 persen siswa memiliki paham dan pemikiran intoleran, 2,4 persen menunjukkan sikap intoleran dalam tindakan dan perkataan, serta 0,3 persen berpotensi menjadi teroris. Riset ini seharusnya menjadi tanda mulai gawat daruratnya persoalan kebinekaan di negeri kita. Bangsa ini tak akan bertahan jika generasi mudanya dijejali politik identitas yang memiskinkan wawasan kebangsaan dan mengeringkan spiritualitas yang menjadi sumber kekayaan rohani bangsa ini.
Prioritas anggaran
Ketiga, fokus prioritas anggaran pendidikan. Bagaimanapun juga, anggaran pendidikan adalah sarana utama berjalannya setiap kebijakan pendidikan. Bagaimana capres dan cawapres mengelola serta mengawal anggaran pendidikan yang tersebar di banyak kementerian dan hampir 63 persennya ditransfer ke daerah, sementara otonomi daerah justru menjadi ruang untuk menyelewengkan dana-dana pendidikan karena proses kepemimpinan daerah masih banyak diwarnai proses politik yang tidak sehat sehingga memungkinkan politisasi kepala sekolah dan guru yang akan mengganggu stabilitas kebijakan pendidikan?
Kita tidak dapat hanya mengandalkan keterpilihan kepala daerah yang memiliki komitmen kuat pada dunia pendidikan untuk menyelamatkan anggaran dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah, tetapi harus mendesain sebuah sistem kebijakan pendidikan yang memungkinkan daerah menjadi pelaku utama peningkatan kualitas pendidikan. Alasannya, karena merekalah yang persis memahami persoalan pendidikan di daerahnya, mengembangkan sistem anggaran keuangan yang yang akuntabel dan transparan, serta memberdayakan aparat daerah agar pendidikan daerah menjadi kunci kemajuan.
Apa yang bisa ditawarkan oleh capres dan cawapres untuk mengatasi persoalan ini? Saya berharap, dalam debat nanti, kedua capres dan cawapres membahas persoalan fundamental ini dan memberikan argumentasi rasional obyektif sebagai solusi yang dapat dipahami publik, jauh dari jargon-jargon, retorika kosong, kalimat klise, dan janji-janji manis yang tidak mencerdaskan.
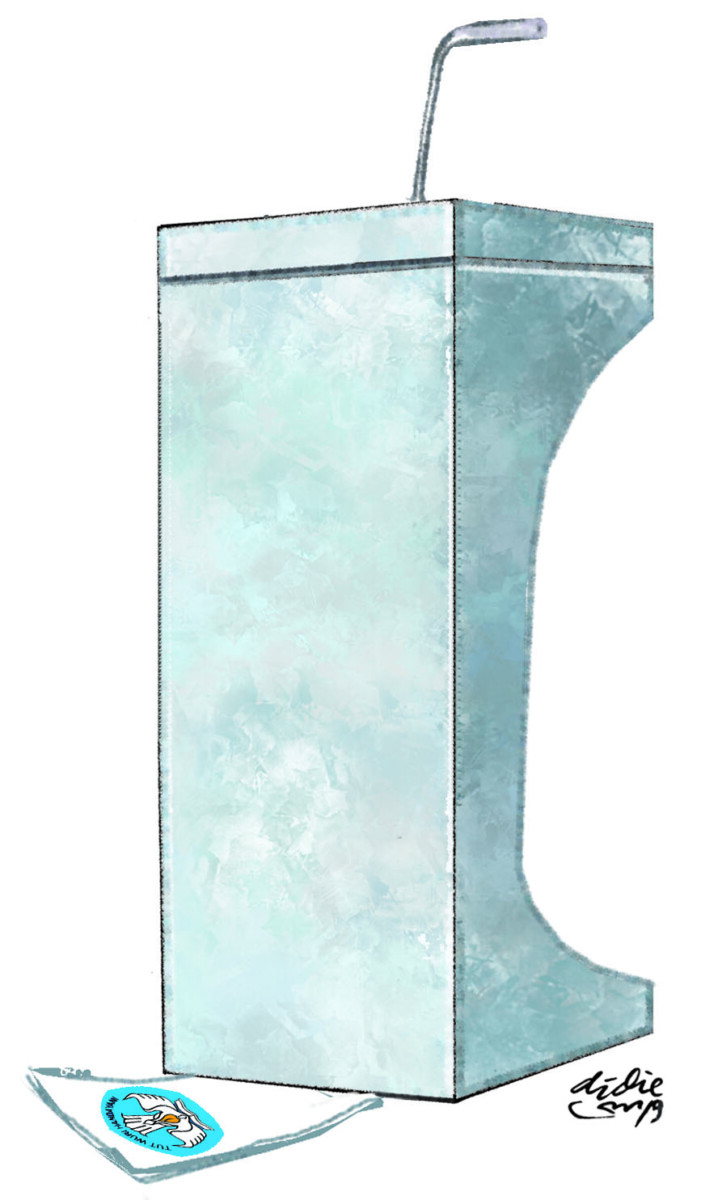

Tidak ada komentar:
Posting Komentar