Mars Yalal Wathon
Dalam artikelnya yang berjudul "Kematian Gus Dur dan Lahirnya Habitus Baru Kebinekaan Indonesia" (2016), Ahmad Suaedy menjelaskan bahwa penerimaan Pancasila dan kebangsaan secara penuh dalam tubuh Nahdlatul Ulama itu baru terjadi pada 1984, yaitu ketika Nahdlatul Ulama (NU) menjelaskan Pancasila dan kebangsaan dengan bahasa syariah.
Namun, semangat itu kini telah menjadi—meminjam istilah Pierre Bourdieu (1984)— habitus baru di organisasi ini. Sikap NU yang muncul belakangan ini terhadap Pancasila dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan implementasi dari habitus itu.
Memperteguh momentum tahun 1980-an tersebut, pada 2013, Gerakan Pemuda (GP) Anshor, yang merupakan sayap pemuda dari NU, menggali dan merekonstruksi mars "Yalal Wathon" ('Ya Ahlal Wathon', 'Wahai Anak Bangsa') berdasarkan penuturan KH Maimun Zubair, Rembang. Lagu yang menggelorakan semangat cinta Tanah Air ini sebelumnya hilang dari peredaran.
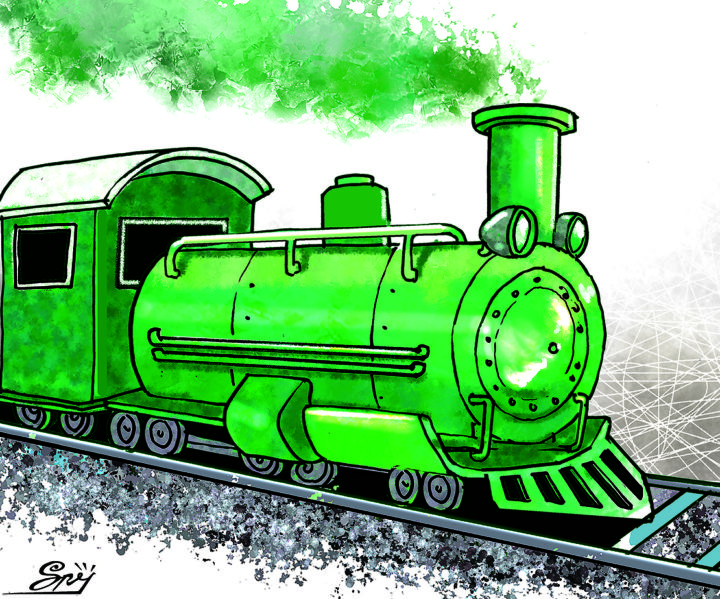
Sebelum 2013, mereka yang lahir dan tumbuh dari keluarga NU pun hampir tidak pernah mendengar lagu ini dalam berbagai pertemuan dan kegiatan NU. Ini adalah fenomena baru yang mempertegas bagaimana nasionalisme itu tumbuh dan mentradisi dalam organisasi yang pada 27 Februari-1 Maret 2019 ini melangsungkan musyawarah nasional (munas) serta konferensi besar (konbes) di Banjar, Jawa Barat, itu.
Jika dirunut lebih panjang lagi, paduan antara keislaman dan kebangsaan dalam tubuh NU itu juga bisa ditemukan dalam berbagai slogan dan nama yang dipakai di lingkungan NU. Nama Garda Bangsa, pasukan pengamanan sipil di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Pagar Nusa, seni bela diri di NU, serta tentu saja dengan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945, adalah monumen dan momentum penting yang mempertegas kebangsaan NU.
Maka, tak mengherankan jika organisasi ini terlihat sangat keras dalam melawan berbagai gerakan yang mencoba mengganggu negara-bangsa ini. Organisasi ini seperti terpanggil untuk cancut tali wondo melawan tuntutan pendirian khilafah dan keinginan beberapa orang untuk mewujudkan "NKRI Bersyariah".
Semangat yang begitu tinggi dari NU dalam konteks kebangsaan dan keindonesiaan ini memang kadang menjebak beberapa aktivis NU untuk menjadi— meminjam istilah Kevin W
Fogg (2018)—Revisionist NU History. Ini, misalnya, bisa terlihat dalam tulisan Yahya Cholil Staquf (2018) yang berjudul Islamist politics in "reformasi" Indonesia.
Dalam tulisan itu, Staquf menjelaskan bahwa pada tahun 1950-an dan 1960-an, Wahab Hasbullah dari NU berperan penting dalam menghalangi Masyumi yang berjuang untuk mengembalikan Piagam Jakarta dan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam.
Tentu saja klaim itu tidak berdasarkan pada data sejarah yang selama ini banyak tersebar, tapi lebih pada semangat kebangsaan yang ingin menunjukkan betapa nasionalisnya NU. Pada kenyataannya, pada waktu itu, NU turut serta mendukung upaya demokratis untuk kembalinya Piagam Jakarta dan upaya menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Tanpa harus "merevisi" sejarah seperti ini pun, peran NU dalam kebangsaan tak akan pernah diragukan.
Payung bersama
Semangat nasionalisme yang tinggi dari NU itu tentu saja perlu semakin diperteguh dengan semangat menjadi tenda bangsa atau payung bersama. Hal yang mudah menggelincirkan organisasi besar seperti NU, dan juga Muhammadiyah, adalah merasa sebagai Indonesia itu sendiri atau sebagai representasi paling otentik dari Nusantara. Padahal, Indonesia tidak bisa direduksi hanya menjadi Islam atau Jawa saja, atau bahkan kelompok santri saja atau NU dan Muhammadiyah saja, karena bangsa ini adalah majemuk dari segi pemahaman keagamaan, agamanya, etnisnya, dan sebagainya. Semua pihak memiliki kontribusi dan peran tertentu dalam membangun serta merawat bangsa yang tak boleh dinafikan.
Upaya menjadi tenda kebangsaan atau payung bersama ini setidaknya sudah dimulai oleh KH Ma'ruf Amin yang lebih banyak mempromosikan Islam Wasatiyyah (Islam moderat) daripada Islam Nusantara yang khas NU.
Ini yang perlu terus dikembangkan dengan, misalnya, menghindari klaim sebagai satu-satunya Islam yang benar atau keinginan menguasai semua kursi kabinet atau keinginan menjadi Indonesia sebagai "negara santri". Menjadi tenda bangsa bukanlah perkara mudah karena kadang harus membuat uneasy alliance dengan kelompok tertentu yang tak disukai atau tak seide. Tapi, ini adalah konsekuensi dan tantangan menjadi negara dengan masyarakat yang majemuk.
Memang banyak warga NU yang merasa bahwa mereka belum mendapatkan imbalan yang sepadan dengan kontribusi mereka dalam kebangsaan. Di gambar-gambar (relief) dan patung-patung museum yang terletak di kaki Monumen Nasional (Monas), misalnya, kontribusi NU dalam masa-masa revolusi tak tampak. Ada satu atau dua gambar tentang pesantren, tetapi tidak diasosiasikan ke NU. Sementara agama lain dan kelompok agama lain mendapatkan ruang yang lebih banyak.
Terakhir, NU adalah organisasi besar dengan pengikut yang berjumlah puluhan juta orang bisa memiliki pengaruh sosial dan politik yang sangat tinggi. Dengan kekuatannya yang besar itu, NU secara otomatis memiliki tanggung jawab yang besar terhadap negara Indonesia, baik dalam menjaga kebinekaannya maupun dalam kemajuannya.
With Great Power Comes
Great Responsibility.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar