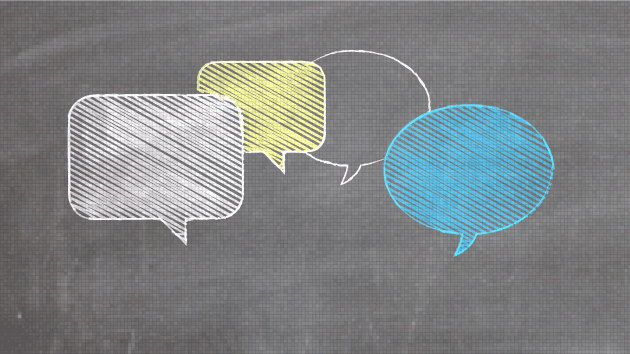
"Apa kabar Titi Gantung?" tanya seorang sahabat yang telah lama menetap di Bali. Tak seperti Titi Kuning, Titi Bobrok, Titi Rante, atau Titi Pahlawan yang juga ada di Medan, Titi Gantung punya daya tarik tersendiri. Banyak warga kota sore-sore menyempatkan melepas lelah atau bersantai di sana. Dia bukanlah penghubung jalan terputus oleh aliran sungai di bawahnya, tetapi oleh rel kereta api dari Stasiun Besar Medan, berdampingan dengan Titi Gantung itu.
Karena kereta api senantiasa hilir-mudik mengangkut penumpang ke berbagai kota di Sumatera Utara, sehingga memutus dua kawasan penting di kota Medan, yaitu Pajak Sentral sebagai pusat perbelanjaan dan Lapangan Merdeka serta Balai Kota sebagai pusat pemerintahan, oleh Belanda pada 1885 dibangun Titi Gantung. Ya, seperti jembatan layang yang kita kenal dewasa ini.
Dalam hal ini yang ingin kita bahas adalah istilah kebahasaannya. Istilah Titi Gantungdi atas sudah mulai diubah oleh media massa lokal, apalagi nasional, denganJembatan Gantung atau Jembatan Titi Gantung. Namun, warga kota Medan hingga kini tetaplah menyebutnya dengan nama yang telah ditabalkan pada mula berdirinya hampir 150 tahun silam. Bahkan, oleh sahabat yang disebut pada permulaan tulisan ini, penyair Frans Nadjira, yang sudah lama meninggalkan Medan dan perantau pula yang berasal dari Makassar.
Istilah bahasa di Medan kental dengan logat Melayu. Kata titi sinonim denganjembatan sehingga kontur jembatan titi gantung jadi rancu. Begitu juga dengan kompositum jembatan gantung janggal didengar di Medan. Sebagaimana diketahui, bahasa adalah alat komunikasi yang telah disetujui bersama di antara para pemakainya dalam suatu tempat atau lingkungan tertentu. Mungkin untuk kepentingan pemerintahan, banyak istilah yang kini diseragamkan. Istilah penghulu kampung diubah menjadi kepala kampung, kemudian kepala desa. Padahal, di banyak kawasan di sekitar Medan, istilah penghulu masih banyak dipakai walaupun sudah diubah menjadi pak kades. Pusat belanja terbesar di Medan, dulu disebut pajak sentral, diubah jadisentral pasar, diubah lagi pusat pasar.
Ada satu anekdot. Seorang pejabat dari Jakarta, namanya Samsul Bahri, dimutasikan ke Medan sebagai kakanwil Parsenibud. Dalam satu kunjungan dinas ke Nias, beliau memerlukan berbagai keperluan pribadi. Dia bertanya kepada sopir, di mana kira-kira komoditas itu biasa dibeli.
"Di pajak, Pak" jawab sopir spontan.
"Eh, bukannya di pasar?", tanya beliau heran, sembari dalam hati menggerutu, "Belum apa-apa sudah kena pajak!" Lebih mengherankan Pak Samsul lagi ketika Sang Sopir memperjelas Jawabannya. "Bukan di pasar, Pak! Di pajak. Kalau di pasar, kita bisa dilanggar!"
Setelah "buka-bukaan", barulah Pak Samsul Bahri paham sehingga tertawa geli. Di Medan pajak adalah tempat berbelanja;pasar berarti jalan raya; dan langgarmaksudnya tabrak! Pantas saja Sang Sopir takut membawa bosnya berbelanja ke pasar. Berbahaya dan bisa-bisa kena pecat dia!
Keberagaman bertutur bisa mengakrabkan sesama, sebagaimana dengan gembira diceritakan Sang Kakanwil kepada saya ketika itu.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar