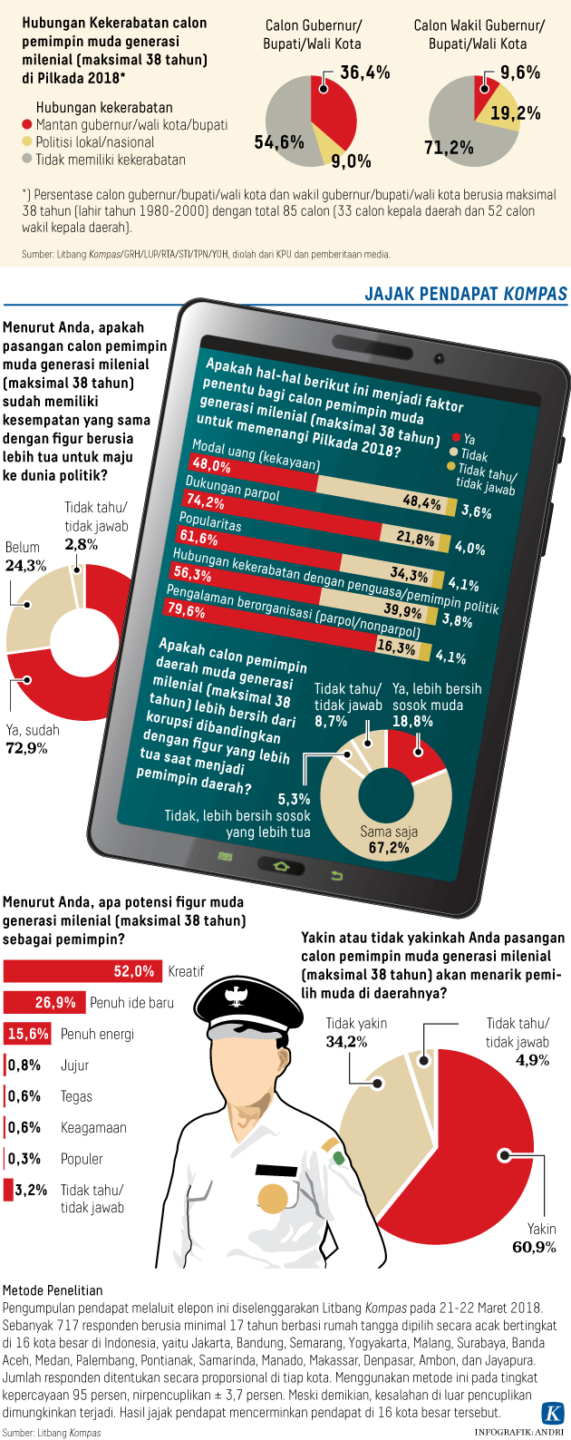
Munculnya tagar #2019GantiPresiden maupun #2019TetapJokowi di ranah media sosial menunjukkan polarisasi masyarakat yang makin mengkristal.
Semenjak Pemilu 2014, polarisasi masyarakat di ranah media sosial tak pernah selesai mencapai kata konklusi dan rekonsiliasi. Alih-alih usai pemilu kondisi masyarakat akan semakin kondusif, yang terjadi justru masyarakat semakin terbelah dan tersegregasi satu sama lain.
Kedua tagar tersebut sebenarnya berupaya menginisiasi munculnya gerakan politik nonpartisan sebagai alat penekan dan alat kampanye politik pada Pemilu 2019. Pola tersebut merupakan bentuk perulangan dari gerakan yang pernah muncul saat Pemilu 2014 dan juga Pilkada DKI 2017. Gerakan politik nonpartisan ini lebih efektif dalam mengusung calon dan mengintimidasi kompetitor dan pendukungnya daripada mesin partai politik. Hal ini karena gerakan politik nonpartisan sifatnya lebih awet dan terpelihara berkat adanya filterisasi isu dan informasi dalam media sosial secara masif berdasarkan preferensi individu. Oleh karena itulah ia berdampak pada semakin mengerasnya polarisasi dalam masyarakat kini.
Gerakan politik berbasis tagar memang berbasiskan pada politik memori, jejak digital, dan juga filterisasi isu. Ingatan menjadi komoditas politik yang senantiasa awet untuk kemudian diteruskan dan dipelihara dalam media sosial sehingga warganet pun dengan mudah terdoktrinasi sekaligus terpolarisasi karena isu berbasiskan ingatan politik sebelumnya.
Tentu politik jadi indikator penting adanya polarisasi suara dan aspirasi. Namun, mengapa setelah ajang politik formal selesai, malah justru perbedaan politik itu kian meruncing di ranah media sosial?
Hal itu yang kemudian menimbulkan adanya pembilahan dua kubu: antara yang "kecebong" melawan "kampret". Istilah yang bermakna peyoratif itu muncul ketika setiap kubu mengklaim dan menuduh sebagai haters dan lovers secara bergantian dalam menanggapi isu tertentu. Bahkan, hal itu kemudian diikuti tumbuhnya sikap emosional dan irasional di kalangan warganet Indonesia.
Dalam satu hal terjadi adanya pemujaan secara digital terhadap figur tertentu, pada saat bersamaan terjadi pula proses penghinaan secara digital yang dialamatkan pada figur tertentu pula. Afiliasi terhadap figur di media sosial sebenarnya masih menunjukkan bahwa patronase masih jadi keniscayaan dalam politik di Indonesia. Media sosial bagi kalangan kelas menengah telah menciptakan populisme dan chauvinisme secara bersamaan. Kondisi itulah yang menjadikan simbol dan sosok menjadi hal penting.
Melalui media sosial, kita bisa melihat fenomena itu dengan mudah, di mana dengan gampang orang menuliskan status, berkomentar, ataupun membagi informasi dan isu yang ujungnya adalah simbolisasi aktor di akhir. Sekali lagi, isu dan informasi yang berkembang di masyarakat lalu diunggah di media sosial, yang sebenarnya memperuncing polarisasi tersebut. Kita dengan mudah melihat pola pikir A dan B yang dilakukan oleh individu dan kolektif saling bersahutan, yang ujungnya adalah mengkristal pada figur tertentu.
Koalisi massa
Adanya pola kristalisasi masalah dan pola pikir reduksionis yang mengacu pada figur itu sebenarnya memperlihatkan pola penggunaan media sosial di Indonesia lebih condong mencari koalisi massa sebesar-besarnya daripada membangun tali silaturahim. Kecenderungan itu bisa terlihat manakala secara politis, entah itu status maupun daftar pertemanan, hanya diisi oleh teman dan relasi yang berpandangan sama.
Kondisi itulah yang menyebabkan rekonsiliasi digital tidak pernah muncul dalam percakapan di media sosial. Ada semacam bentuk kesengajaan ketika kondisi polarisasi ini semakin besar dan melebar. Selain kebutuhan politik yang memang jadi motor, kebutuhan pasar juga jadi alasan kenapa polarisasi media sosial tersebut dibutuhkan. Sebab, semakin banyaknya jumlah massa pendukung figur dan semakin membesar di media sosial akan berdampak pada semakin banyaknya buzzer yang disewa dan semakin banyak pula endorser yang digunakan. Tujuannya adalah memengaruhi pola pikir warganet kelas menengah di media sosial. Keduanya menjadi aktor penting untuk memastikan ingatan publik secara digital terpelihara baik.
Makna tagar dalam gerakan politik dunia maya memang bertujuan untuk justifikasi dan signifikasi bahwa isu itu penting dan krusial. Justifikasi itu berkaitan upaya menjadikan isu ini masalah besar dan signifikansi itu lebih banyak berbicara mengenai dampak yang akan ditimbulkan.
Munculnya #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi di media sosial itu sebenarnya hanya bertujuan pada kepentingan politik sementara. Hanya saja publik sekarang ini cenderung berlebihan memaknai tagar di media sosial akan berdampak besar pada negara, bahkan masalah akhirat pun menjadi topik. Pola pikir berlebihan tersebut pada akhirnya akan berdampak pemikiran konspiratif dan pemikiran destruktif secara bersamaan.
Kita bisa melihat bahwa kedua tagar tersebut sudah menyebar dan memengaruhi publik secara politis untuk kemudian saling mencurigai satu sama lain. Pada akhirnya, toleransi dan kebinekaan Indonesia yang telah dirawat sejak lama bisa rusak hanya karena kepentingan politik. Keefektifan gerakan politik daring memang efektif untuk merawat ingatan dan meninggalkan jejak digital yang membuat orang untuk menjadi partisan dengan sendirinya.
Pada akhirnya media sosial memang mendorong kita untuk jadi partisan secara aktif maupun pasif. Namun, jangan sampai pergunjingan tersebut sampai membutakan hati, pikiran—apalagi rasionalitas—hanya karena masalah politik.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar