Dalam permainan itu, sebagian di antara mereka melenggang aman-aman saja. Sebagian yang lain terjerat oleh paradoks ini: kata-kata atau frasa yang dari aspek makna verbatimnya tak bermasalah, akur dan kompatibel, tetapi sesungguhnya, begitu ditilik dari perspektif sejarah perkembangan demokrasi, kata-kata atau frasa itu kontradiktif.
Nasionalis religius adalah sebuah contoh kasus. Frasa adjektiva itu, dengan berbagai variannya seperti religius nasionalis, nasional religius, memukau para politikus di sejumlah negara. Mereka menggunakan adjektiva ganda itu sebagai nama partai politik.
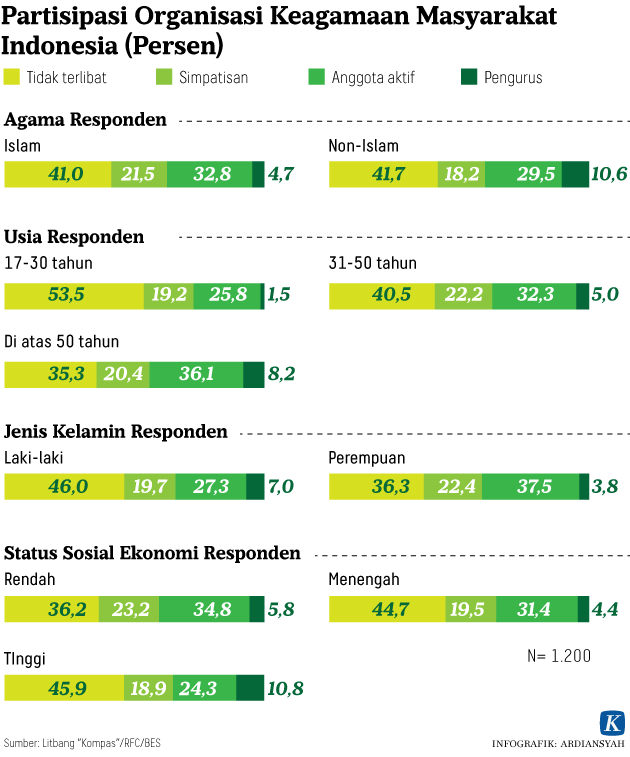 Di Israel pada 1956 sekelompok politikus dipimpin Josef Burg dan Haim-Moshe Shapira mendirikan Miflaga Datit Leumit, yang searti dengan Partai Religius Nasional. Penautan dimensi agama yang direpresentasikan adjektiva religius dan matra politik yang direfleksikan nasional pada nama partai itu tentu bertendensi. Mereka boleh jadi berupaya mengeksploitasi sentimen keagamaan publik lewat pemilihan kata-kata itu.
Di Israel pada 1956 sekelompok politikus dipimpin Josef Burg dan Haim-Moshe Shapira mendirikan Miflaga Datit Leumit, yang searti dengan Partai Religius Nasional. Penautan dimensi agama yang direpresentasikan adjektiva religius dan matra politik yang direfleksikan nasional pada nama partai itu tentu bertendensi. Mereka boleh jadi berupaya mengeksploitasi sentimen keagamaan publik lewat pemilihan kata-kata itu.
Rupanya, perkembangan politik yang kian demokratis-sekular tak memberi tempat bagi parpol yang memainkan sentimen keagamaan publik dalam perburuan kue kekuasaan. Parpol yang platform ideologisnya menghidupkan nilai-nilai Judaisme dalam aktivitas keseharian itu kian ditinggalkan pemilihnya, dan pada 2008 bubarlah organisasi pencari kekuasaan itu.

Sejumlah peserta gerak jalan kerukunan umat beragama berjalan bersama saat mengikuti acara gerak jalan dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama di Jakarta, Minggu (6/11). Kegiatan tersebut guna menumbuhkan semangat toleransi antarumat beragama.
Di Indonesia, nasionalis religius tak dipakai sebagai nama parpol. Namun, salah satu parpol yang pernah berjaya dan kini terpental dari tiga besar peraih suara dalam Pemilu 2014 menggunakannya sebagai slogan partai. Tampaknya pembesar parpol itu tak peduli benar dengan fakta historis perkembangan demokrasi, yang kian melonggarkan kaitan urusan politik dan ihwal keagamaan. Artinya, dua adjektiva itu bukannya kian merapat untuk bersanding tapi menjauh untuk memisah.
Namun, tak tahulah bila yang hendak dituju juragan parpol pengguna slogan itu adalah arah yang bertolak belakang dengan impian kaum demokrat yang dirintis Lock, Diderot, Jefferson dan Hitchens.
Arah yang melawan arus pemantapan demokrasi itu belakangan ini tampak nyata dengan semakin kuatnya seruan untuk mengadopsi pasal-pasal yang mengatur perkara perzinahan dalam perpsektif agama.
Nasionalis spiritualis
Menyandingkan nasionalis yang bertaut dengan perkara kebangsaan yang duniawi dan religius yang berkait dengan perkara keutamaan yang illahi justru bertabrakkan dengan pluralisme, yang memberikan ruang kesetaraan antara kelompok keimanan mayoritas dan minoritas.
Syukurlah, berbagai kekuatan prodemokrasi terus bergerak untuk melonggarkan relasi politik dan agama dalam praksis bernegara. Salah satu kekuatan itu berbentuk seruan Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru-baru ini dalam kancah pilkada.
Kepada politikus kontestan pilkada, KPU minta untuk menghindari politisasi agama dalam berkampanye. Hal ini membersitkan sinyal bahwa pemisahan urusan politik dan iman harus dijalankan sebab pemisahan itu, diakui atau tidak, memuat kebaikan dan manfaat.

Silaturahmi kepolisian ke tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan bisa menjaga kondusivitas masyarakat dan menambah keteduhan
Komisioner yang berkantor di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, itu maklum belaka bahwa politikus punya banyak akal menjual ayat-ayat keagamaan untuk menangguk suara orang-orang kurang tercerahkan, yang jumlahnya cukup melimpah.
Terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, mencampuradukkan urusan politik dan urusan keagamaan bisa menyesatkan publik, sebelum jadi petaka politik. Kumpul-kumpul massal beratribut keagamaan bisa dibelokkan menjadi ajang orasi politik. Sentimen keagamaan dimainkan untuk menghimpun ribuan orang, yang ujung-ujungnya mau pamer kekuatan untuk tawar-menawar kekuasaan.
Untuk keluar dari sengkarut politisasi agama dan agamaisasi politik, inilah solusi praktis: ubah slogan itu.
Mengganti slogan parpol bukan aib. Bolehlah usul ini dipertimbangkan: tukar adjektiva religius dengan spiritualis. Yakinlah, pengubahan itu berpotensi menambah jumlah pemilih. Sebab, mereka yang tak bereligi pun—tetapi mempraktikkan laku spiritual—bisa menjadi bagian dari parpol itu. Nasionalis spiritualis. Lebih inklusif.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar