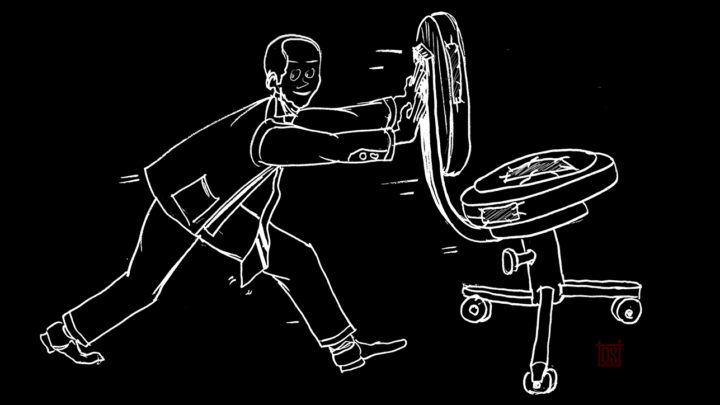
Selama beberapa tahun terakhir, populism(e) menjadi kata yang sangat populer. Diskursus dominan mengindikasikan bahwa populisme adalah "hantu" yang menakutkan. Ia disinyalir membahayakan masa depan sistem dan tatanan (masyarakat) demokrasi (liberal).
Mengapa populisme dianggap mengerikan? Apa saja dampak negatif populisme terhadap kelangsungan sistem politik dan demokrasi (liberal)?
Pemicu perpecahan
Populisme hadir dalam beragam bentuk. Ia bisa mewujud sebagai ideologi politik yang mengisi basis ideologi lain, seperti nasionalisme dan bahan baku yang jadi basis ideologi seperti agama, ras dan etnisitas (Canovan, 1999: 5-6; Mudde, 2004: 544). Ia juga bisa muncul dan digunakan sebagai sebuah metode, strategi, dan taktik dalam komunikasi politik (Moffitt dan Tormey, 2004: 386-394; Waisbord dan Amado, 2017: 1331).
Sebagai ideologi politik, populisme mengedepankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang membelah masyarakat menjadi dua kelompok besar, yang cenderung memiliki karakter homogen, tetapi saling berlawanan (antagonistik) (Canovan, 1999: 5-6; Mudde, 2004: 544). Populisme mengedepankan prinsip-prinsip anti-elitisme, klaim yang mengatasnamakan rakyat untuk menghantam para politisi dan institusi politik yang berkuasa. Juga untuk menjadikan kelompok-kelompok masyarakat dan politisi yang berseberangan sebagai "musuh"—bukan hanya sebagai kompetitor (Reinemann, dkk, 2016: 21-23).
Para politisi yang mengadopsi taktik dan strategi populisme tidak hanya gemar mengeksploitasi isu-isu yang terkait dengan identitas politik. Mereka juga menggunakan retorika politik yang bersifat vulgar, kasar, dan emosional. Mereka bahkan tak segan-segan mem-bully secara serampangan siapa saja yang dianggap sebagai musuh (Block dan Negrine, 2017: 181-183).
Untuk memperluas pengaruhnya, para politis tersebut mengemas pesan-pesan politik populisme dengan sederhana. Biasanya menggunakan gaya bertutur, ekspresi yang vulgar dan informal, atau dengan memilih kata-kata yang cenderung agresif dan provokatif (Engesser dkk, 2017; Erns dkk; 2017; Bracciale dan Matella, 2017).
Tsunami politik
Baik sebagai ideologi maupun taktik dan strategi komunikasi politik yang diadaptasi oleh aktor dan organisasi politik, populisme telah melahirkan gelombang tsunami politik baru di kawasan Trans-Atlantik. Di Amerika Serikat, peluang kemunculan partai baru yang mengadaptasi populisme memang tidak mendapatkan ruang politik yang memadai. Namun, kelompok-kelompok elite politik, para pelobi, aktivis, dan masyarakat yang menjadi penganut ideologi ini mampu mengantarkan Donald J Trump terpilih dalam Pilpres AS, 8 November 2016.
Selama beberapa periode terakhir, partai-partai yang mengadaptasi populisme sebagai ideologi cukup eksis di Eropa Barat. Di Inggris, partai garis keras, seperti British National Party (BNP) dan UKIP, memang gagal dalam membangun kekuatan politik di parlemen, tetapi mereka cukup berhasil dalam mendukung kelompok Brexit pada referendum 23 Juni 2016. Di Belanda, PVD yang dipimpin Geert Wilders memang tidak berhasil memenangi pemilu. Namun, partai ini cukup sukses dalam mengurangi basis dukungan partai-partai kanan dan kiri tengah dan melahirkan model pemerintahan koalisi yang cukup rapuh.
Di Perancis, populisme mampu mendelegitimasi pengaruh Partai Sosialis yang dipimpin mantan Presiden Francois Hollande. Populisme juga telah memperkuat pengaruh Front Nasional yang dipimpin Marine Le Pen. Namun, populisme juga turut mengantarkan Emmanuel Macron ke kursi presiden dan menjadikan La Republique En Marche sebagai partai baru yang berpengaruh di Perancis.
Di Jerman, populisme menjadikan AfD sebagai kekuatan politik baru. Populisme bahkan mampu menggerogoti basis politik CDU pimpinan Angela Merkel serta SPD yang digawangi Martin Scluz. Bahkan, hingga saat ini, gelombang populisme terus menjebak kedua partai tersebut dalam pilihan-pilihan yang sulit dalam membangun koalisi dan mengelola pemerintahan.
Arus politik populisme juga meruntuhkan legitimasi partai kanan dan kiri tengah dalam panggung politik di Italia. Arus politik ini tidak hanya telah memaksa Matteo Renzi melepaskan jabatan perdana menteri pada akhir 2016, pasca-referendum konstitusi. Lebih dari itu, gelombang ini telah menyebabkan Partai Demokrat yang dipimpin Matteo Renzi kolaps dan mengantarkan The Five Star Movement dan The Italian Northern League sebagai pemenang
pemilu. Namun, kedua partai tersebut belum berhasil menawarkan model koalisi dan arah pemerintahan secara meyakinkan.
Menghantui Pilpres 2019?
Dalam Pilpres 2014, sejumlah kalangan mencatat pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) secara masif mengembangkan model kampanye berbasis pesan-pesan populis, khususnya untuk membidik pemilih Muslim dan kelas menengah (Mietzner, 2014, 2015; Hadiz, 2017). Bukan tidak mungkin, fenomena tersebut akan makin masif dan intensif dalam Pilpres 2019.
Untuk itu, kita perlu memikirkan sejumlah langkah taktis. Para pemimpin parpol dan para king maker penentu pasangan capres-cawapres dalam Pilpres 2019 perlu memperhitungkan konsekuensi negatif atas polarisasi politik yang dari penggunaan pesan-pesan, strategi, taktik, dan gaya komunikasi politik dan kampanye politik populis yang berkembang menjelang Pilpres 2019.
Kita bisa merasakan adanya polarisasi politik yang cukup tajam pasca-Pilpres 2014 dan Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal ini dapat menjadi bahan bakar untuk membangkitkan gelombang populisme baru yang berbasis politik identitas di daerah-daerah di Indonesia.
Konsensus politik antar-elite perlu dilakukan untuk mengantisipasi menanggulangi dampak negatif gelombang politik populisme di Indonesia. Jika perlu, regulasi politik dan pemilu yang ada ditata ulang untuk merespons hal tersebut. Hal ini tidak lain agar sistem dan nilai-nilai demokrasi yang sudah berkembang di Indonesia semakin membaik.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar