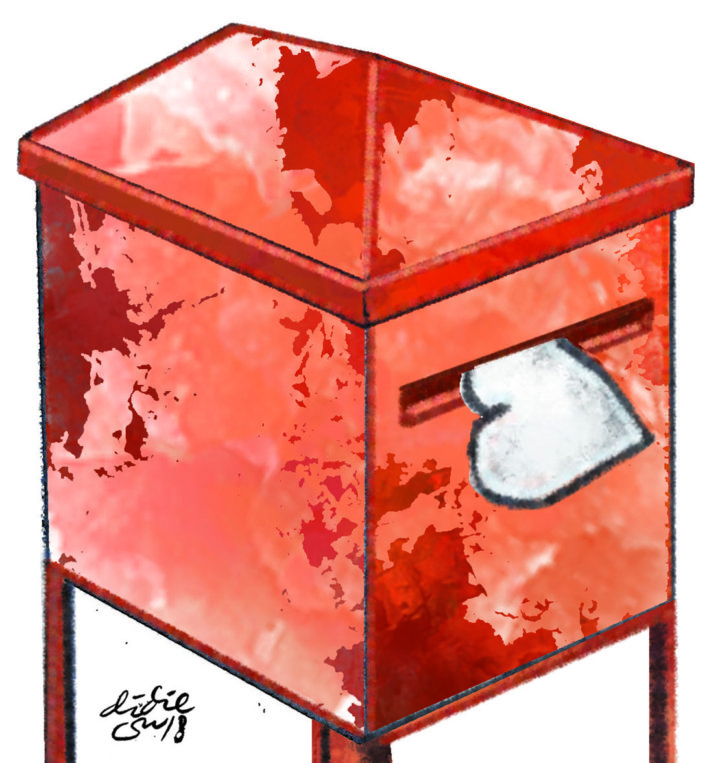
Selamat pagi, hati! Jujur, saya tak tahu harus dikirim kepada siapa surat ini. Saya tidak bisa membayangkan sebuah alamat, tempat di mana ada seseorang yang menyediakan sebuah "kotak pos" di dalam hatinya.
Saya mencoba mendongak ke langit, mencari-cari semacam gantungan, yang padanya bisa disematkan cita-cita, ditambatkan harapan. Namun, beberapa hari ini langit terasa merendah, seolah meminta agar cita-cita tak digantung terlalu tinggi. Awan yang melapisinya menjadi tembaga yang merah terbakar.
Bom itu! Ya, bom itu meledak (lagi!). Lagi dan lagi! Lihatlah, ledakannya telah mengubah udara menjadi api. Angkasa menjelma bara. Tapi, kepada siapa berita ini mesti dikabarkan?
Tanpa bendera duka
Di televisi, di telepon seluler, di rumah-rumah, di halte-halte, dan di mana pun yang masih tersisa tempat, tengoklah, semua orang justru sibuk berdebat. Segala yang bisa dihubungkan dengan peristiwa itu segera digatukkan; segala yang bisa memuaskan perasaan untuk sebuah pendapat yang diyakini benar serta-merta dipungut. Teriakan demi teriakan pun mulai terdengar. Pertengkaran demi pertengkaran terus meruncing. Kita semua lupa bahwa setan sesungguhnya suka jika kelakuannya didamprat dengan serapah, sebab serapah menjauhkan kita dari Tuhan.
Kemudian, seperti biasa, pemerintah pun datang dengan tindakan yang mudah diduga, mengucap belasungkawa di satu sisi dan mengutuk di sisi yang lain. Selebihnya adalah meneriakkan semacam perlawanan, "Kami tidak takut! Tidak ada ruang bagi teroris!" Tapi, adakah tindakan konkret dari belasungkawa yang acap diucapkan pada peristiwa yang berulang itu? Tak ada yang terdeteksi dengan pasti. Bahkan untuk sekadar instruksi "berkabung nasional", tak pernah terdengar. Tidak ada bendera setengah tiang dipancang!
Baiklah, kita coba memahami, pemerintah sedang bertindak atas nama teori: tujuan dari segala ulah biadab teroris adalah menebar ketakutan. Tapi, apakah melawan ketakutan selalu harus identik dengan kutukan, dengan bahasa yang dikeraskan. Sementara, nyawa korban pergi hanya diantar belasungkawa, dengan bahasa itu-itu juga. Dan, bukankah kutukan itu justru memicu nafsu dan ketegangan "politis", memantik pertikaian horizontal.
Demi Tuhan, saya mengharapkan perlawanan dalam wujud lain: pancangkan bendera setengah tiang, nyatakan berkabung nasional. Dengan itu emosi rakyat diikat. Bukankah sejarah telah membuktikan, hanya ketika bendera diacungkan semua rintangan bangsa ini bisa dienyahkan. Dalam negara yang berdiri di atas fondasi keragaman budaya, saat-saat seperti ini sangat dibutuhkan upacara dan tindakan simbolik yang merekatkan.
Tapi, kepada siapa kabar ini harus dialamatkan? Demi Tuhan, pada fase ini, tindakan teror itu sesungguhnya telah dimulai sejak dua bocah tewas di bawah Tugu Monas. Lihatlah, seperti para teroris, kita telah kehilangan kepekaan terhadap nilai dan makna nyawa manusia. Bukankah tak ada air mata untuk kedua bocah itu. Alih-alih menangis, jasad bocah itu justru ditimbun di bawah berita politik, nilai dollar yang meroket, harga sembako yang melambung, perebutan kekuasaan yang terus meruncing. Tak ada jeda bagi hasrat, tidak ada ujung untuk nafsu saling menguasai.
Terkurung di dalam bubu
Tentu saja tindakan polisi yang sangat sigap perlu diapresiasi. Terima kasih. Tubuh tempat di mana bom meledak itu dapat diidentifikasi polisi dengan superkilat. Segera viral sebuah foto keluarga: suami istri dan dua anak. Bukan hanya foto, tetapi silsilah dan hubungannya dengan organisasi teroris internasional segera bisa dilacak dengan meyakinkan. Luar biasa.
Kita pun tertegun. Sejenak tidak percaya. Tapi, menit berikutnya perdebatan justru bertambah pelik. Mau tidak mau, suka tidak suka, pertengkaran yang terkait dengan tema agama (Islam) kian merasuk. Polarisasi kian mengkristal. Perpecahan antara sesama kian mendekat ke bibir mata. Foto keluarga itu, ya, foto itu seperti menjadi bahan bakar yang disemprotkan ke angkasa, ke dalam udara yang telah menjadi bara.
Maka, kian jelas di situ. Terorisme adalah kejahatan luar biasa. Penangkapan atas pihak yang diduga pelaku tak serta-merta merupakan penyelesaian, apalagi bisa menenangkan massa. Alih-alih demikian, ia justru membuat suasana kian menegangkan. Sekali lagi, tanpa menghilangkan penghargaan terhadap kerja keras polisi, kita bisa menyaksikan dalam kasus bom Surabaya itu, yang ditangkap polisi adalah daging yang telah hancur.
Jika begitu, masih bisakah kita menjulukinya pelaku? Bukankah mereka pun pergi bersama korban? Jangan-jangan mereka juga korban. Dan, sebagai korban mereka diletakkan di tempat yang mudah diidentifikasi.
Dampaknya boleh jadi tidak kita perhitungkan sebelumnya: identifikasi yang cepat dan viralisasi yang dahsyat itu ternyata justru menandai sebuah kekalahan. Kita menangkap buih jika tidak mau dibilang terjebak di dalam bubu. Meringkus buih, sudah pasti, tidak bisa menghentikan ombak. Sementara di bibir pantai, para penjala tandang menjadi pemenang. Mereka bersorak menyaksikan kita bertengkar tanpa ujung di dalam perangkap. Bukankah seluruh pertengkaran itu tidak bermuara pada ditemukannya jalan keluar? Alih-alih demikian, dari daging yang hancur itu permasalahan justru kian bermetamorfosis.
Oleh sebab itu, diperlukan strategi lain. Jika teroris bekerja dengan memungut keributan dan ketakutan pasca-peristiwanya, mengapa ia diladeni dengan keributan juga. Mengapa tidak dihadapi dengan senyap.
Bukankah kita juga masih punya kewajiban mengantar jenazah, mengobati yang luka, dan membesarkan hati keluarga korban. Serta, melampaui semua itu, bagi negara, yang terpenting adalah menempatkan derajat manusia (korban) pada posisinya yang tinggi sebagai warga bangsa, sebagai tanda bahwa negara hadir di hadapan rakyatnya!
Barangkali momen untuk menyatakan perkabungan nasional memang sudah lewat; mungkin juga terlambat untuk memancang bendera setengah tiang. Hal yang masih bisa dilakukan, jika mau dan ikhlas, adalah menyatakan permohonan maaf kepada rakyat. Lepas dari kompleksitas persoalan yang berkelindan di seputarnya, hal yang pasti, peristiwa itu terjadi karena sistem keamanan negara yang rapuh.
Terorisme memang terjadi di mana-mana di dunia. Tapi, bom yang meledak beruntun di sejumlah tempat pada saat bibir kita belum kering membincangkan peristiwa "sejenis" sebelumnya (kerusuhan di Mako Brimob), kiranya baru terjadi di kita. Sungguh yang demikian adalah tragedi yang sangat memilukan. Maka, semoga surat setengah tiang ini bisa menjadi pengganti bendera duka yang tidak pernah dipancangkan itu. Beranalogi pada sajak Sapardi Djoko Damono, kepada para korban, ketahuilah, duka ini abadi untukmu. Demikian, hati. Selamat malam!

Tidak ada komentar:
Posting Komentar