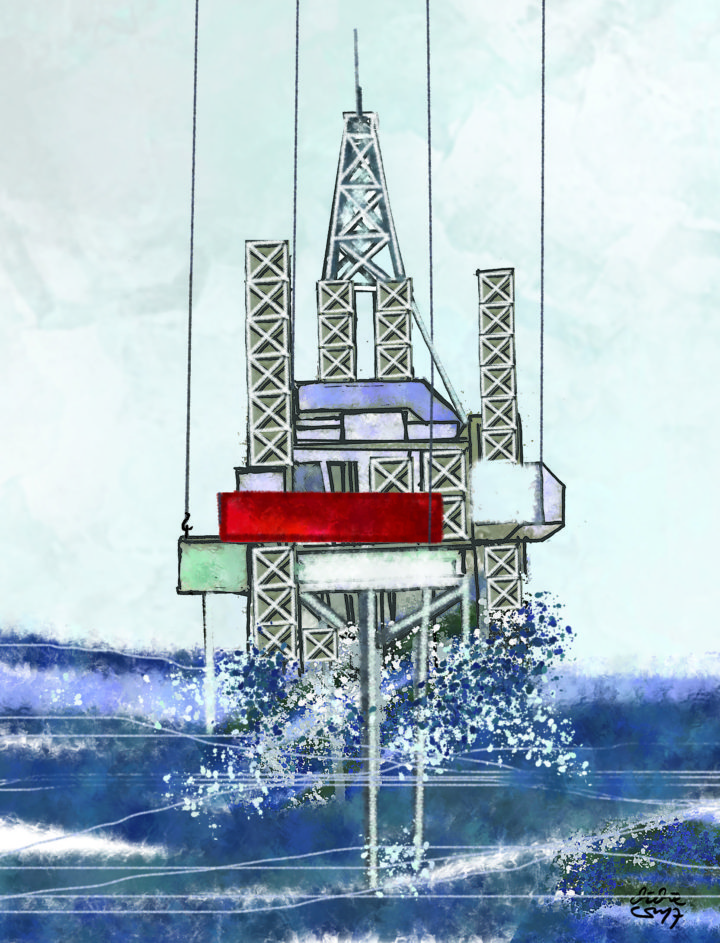
Defisit neraca perdagangan yang terjadi sejak Desember 2017—kecuali Maret 2018 yang surplus— menjadi perhatian serius karena berpengaruh terhadap stabilitas dan perkembangan ekonomi.
Defisit pada April mencapai 1,6 miliar dollar AS. Pada saat bersamaan, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi sekitar 4 persen sejak awal tahun (year to date) dan pertumbuhan ekonomi triwulan I di bawah perkiraan, yaitu 5,06 persen. Jika kita amati, defisit perdagangan terutama karena kontribusi defisit migas. Pada 2017 defisit migas mencapai 8,6 miliar dollar AS, sedangkan nonmigas surplus 20,5 miliar dollar AS.
Dalam periode Januari-April 2018, migas defisit 3,8 miliar dollar AS, sedangkan nonmigas surplus 2,5 miliar dollar AS. Tampaknya defisit migas masih akan terus berlanjut. Ironis untuk Indonesia yang kaya sumber daya alam, tetapi tak dapat mengatasi defisit migas. Ketakjelasan kebijakan menyebabkan Indonesia terperosok pada defisit migas berkelanjutan dan belum terlihat jelas jalan keluarnya. Kebijakan baru gross split justru kian menambah ketidakpastian dalam investasi migas.
Sementara itu, ekspor utamanya masih CPO, batubara, produk manufaktur pakaian, dan alas kaki. Dengan melambatnya permintaan ekspor serta meningkatnya impor bahan antara (intermediate goods) dan barang konsumsi, maka defisit membesar. Sekalipun demikian, meningkatnya impor bahan antara juga menunjukkan meningkatnya kegiatan industri sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan indeks PMI menjadi 51,6 yang berarti terjadi ekspansi (angka tertinggi sejak Juni 2016).
Solusi mengatasi defisit perdagangan yang berimplikasi luas terhadap stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi harus bertumpu pada kemampuan industri manufaktur untuk meningkatkan ekspor. Indonesia pernah menjalankan kebijakan menggeser industri substitusi impor menjadi berorientasi ekspor ketika harga minyak dunia sebagai sumber utama pemasukan negara turun drastis pada 1986. Ketika itu menteri perindustrian adalah Hartarto.
Dari Hartarto ke Transformasi Industri 4.0
Kebijakan industri Hartarto dapat meningkatkan ekspor, terutama industri padat karya, seperti pakaian, alas kaki, dan elektronik. Indonesia dapat memanfaatkan keunggulan komparatif dari jumlah tenaga kerja yang masih relatif murah untuk mendorong ekspor industri manufaktur. Kebijakan industri Hartarto tidak saja meningkatkan ekspor nonmigas, tetapi juga berkontribusi besar dalam mengembalikan pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen.
Sayangnya, kebijakan ini tak dikembangkan lebih lanjut oleh pemerintah masa reformasi. Bahkan, kebijakan industri menjadi tidak jelas dengan kembali pada upaya peningkatan kandungan lokal tanpa memperbaiki daya saing secara berarti sehingga industri manufaktur mengalami perlambatan. Banyak industri ekspor memindahkan operasinya ke Malaysia dan Vietnam ketika harus melakukan peningkatan dalam kandungan teknologi yang butuh keterampilan pekerja lebih tinggi. Minimnya insentif ditambah dengan kenaikan upah minimum yang terlalu cepat menambah dorongan untuk pindah.
Tingginya harga komoditas pada waktu itu membuat pemerintah dan dunia usaha terlena untuk memanfaatkannya dan mengalihkan perhatian dari industri manufaktur. Bahkan, banyak pelaku industri berpindah ke perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batubara karena lebih menguntungkan. Porsi industri manufaktur juga mengalami penurunan sehingga berkembang isu deindustrialisasi.
Pada saat Indonesia mengalami tekanan dalam defisit perdagangan, dan industri manufaktur semakin tertinggal, pemerintahan Jokowi dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (putra dari Hartarto) meluncurkan Transformasi Industri 4.0. Sekalipun terlambat, transformasi industri inilah yang harus kita lakukan. Kebijakan industri Hartarto (II) ini sekalipun mempunyai kesamaan dengan Hartarto (I) dalam meningkatkan sumbangan industri pada ekspor dan pertumbuhan ekonomi, jangkauannya lebih dalam lagi, yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri nasional. Faktor buruh murah tidak lagi dominan, tetapi pekerja dengan keterampilan yang lebih tinggi. Kebijakan ini sebenarnya tidaklah ambisius, tetapi memang menjadi keharusan untuk mentransformasikan industri nasional.
Dengan industri unggulan makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, elektronik, kimia dan otomotif, maka industri ini yang berpotensi besar (dan sedang berjalan) untuk meningkatkan sumbangan ekspor. Produk pakaian dan alas kaki selalu memberikan sumbangan berarti pada ekspor. Elektronik yang harus kembali memberikan sumbangan ekspor yang lebih besar dalam pola rantai pasokan global (global value chain). Investor yang meninggalkan Indonesia siap kembali dan industrial elektronik nasional siap untuk mentransformasikan industrinya lebih kompetitif dan terintegrasi dengan rantai pasokan global. Kawasan pusat industri elektronik, seperti di Karawang, Situbondo, dan Batam, sedang dalam proses revitalisasi ditambah dengan insentif yang lebih menarik.
Industri makanan dan minuman dengan pertumbuhan yang tinggi sudah sepantasnya meningkatkan sumbangan ekspor. Produknya cukup bervariasi serta dengan kualitas dan harga yang kompetitif. Industri otomotif juga sudah mulai melakukan ekspor. Bagi pabrikan utama otomotif semestinya sudah menjadi keharusan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi, paling tidak di pasar ASEAN.
Industri kimia masih butuh upaya lebih besar lagi untuk dapat memberikan sumbangan pada ekspor secara berarti.
Dukungan dan insentif
Bagaimanapun upaya meningkatkan ekspor nonmigas akan tereliminasi oleh berlanjutnya defisit migas jika perbaikan kebijakan migas tak dilakukan. Jelas bahwa hambatan dalam investasi migas memperburuk defisit ini. Jika kebijakan gross split dilanjutkan, maka insentif bagi investor harus diperbesar. Begitu pula insentif untuk melakukan eksplorasi. Pajak pada saat eksplorasi membuat investor tidak tertarik dan penerimaan pajaknya jadi tidak ada.
Insentif memang tidak dapat diberikan langsung kepada eksportir karena tak diperbolehkan WTO, tetapi insentif untuk investasi industri yang berorientasi ekspor dapat diberikan. Insentif bukan hanya yang baru, melainkan juga pada perluasan karena industri melakukan perluasan investasi sekaligus transformasi.
Dari aspek keuangan, kenaikan suku bunga untuk menjaga stabilitas rupiah tentu memberatkan dunia usaha. Namun, kebijakan penurunan suku bunga yang dilakukan Bank Indonesia sejak Februari 2016 sampai September 2017 sebesar 3 persen ternyata juga tak meningkatkan pertumbuhan kredit secara berarti. Permasalahannya, kesiapan sektor riil. Karena itu, sekalipun suku bunga meningkat, jika peluang perkembangan sektor riil jelas, dengan akses kredit lebih baik masih dapat meningkatkan pertumbuhan kredit dan ekonomi. Jadi, fokusnya pada perbaikan sektor riil terlebih dahulu.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar