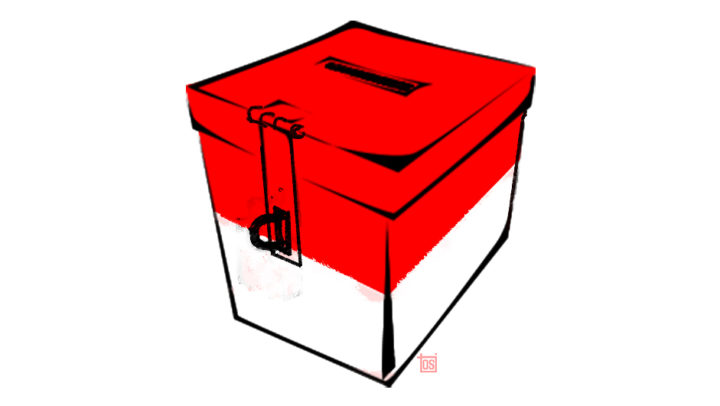
Pilkada
Mitos Dikotomi Parpol
Pilkada 27 Juni 2018 yang berlangsung aman, damai, dan lancar mencerminkan berlangsungnya penyempurnaan demokrasi model Pancasila di Indonesia dari waktu ke waktu.
Kekhawatiran akan dampak negatif politik populisme dan identitas yang diperkuat dengan ujaran kebencian, berita bohong, atau penyebaran paham radikal melalui media sosial setidak-tidaknya dapat dikurangi. Diharapkan politik populisme dan identitas secara bertahap dapat dihilangkan seiring dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran kebangsaan.
Dalam kurun waktu cukup panjang bangsa kita dihinggapi dan diracuni virus dikotomi pribumi-nonpribumi. Dikotomi itu pada hakikatnya mitos dalam rangka memecah belah bangsa. Syukurlah mitos itu lama-kelamaan berkurang dalam pola pikir anak bangsa.
Hal itu dimungkinkan baik karena kebijakan dan peraturan pemerintah yang melarang penggunaan istilah dikotomis itu maupun akibat pemahaman dan kesadaran masyarakat akan asal-usul mereka yang sebenarnya. Berbagai penelitian historis, arkeologis, dan genetika menguatkan keyakinan bahwa tak satu pun komponen bangsa berhak mengklaim diri sebagai penduduk asli 100 persen di bumi pertiwi. Maka, politisasi pribumi-nonpribumi tak layak jadi produk disintegrasi dan segregasi.
Pengalaman berbangsa dan bernegara setelah melalui beberapa kali pilkada, pileg, dan pilpres seyogianya jadi momentum menghapus dikotomi parpol berbasis
Islam dan partai politik berasaskan kebangsaan. Pola pikir yang mengelompokkan partai secara dikotomis sudah saatnya dilupakan sebab hanya jadi tipuan pemasaran untuk mendapat kekuasaan. Para politisi sebaiknya
menghentikan cara kampanye konvensional primordial yang tidak memberi pendidikan kebangsaan. Sebab, hal
itu hanya memprovokasi rakyat saling berselisih dan membawa korban material dan imaterial amat besar terhadap hasil pembangunan yang telah dicapai selama 73 tahun.
Dikotomi parpol layak dianggap sebagai peninggalan sejarah masa lampau. Ini saatnya para pemimpin bangsa dan politisi menciptakan masa depan yang lebih baik. Hindari jenis politik yang menyengsarakan rakyat.
Wim K Liyono Kebon Jeruk, Jakarta Barat
Personifikasi pada Bahasa Indonesia
Dalam bahasa Indonesia personifikasi sudah lumrah. Pada lagu "Nyiur Hijau", daun melambai-lambai. Umumnya yang melambai itu orang, tapi daun kelapa melambai-lambai. Itu salah satu bentuk personifikasi.
Burung disebut berkicau, tapi sering juga disebut burung bernyanyi. Yang menjadi saksi suatu peristiwa umumnya manusia, tetapi sering juga disebut bulan menjadi saksi bisu. Jadi, perbuatan benda atau hewan dapat pula dinyatakan seperti perbuatan manusia.
Gunung sering mengeluarkan asap, magma, dan lain-lain. Dapat pula gunung menjadi obyek personifikasi. Sering gunung dinyatakan mengalami erupsi. Saya sering heran, mengapa tak dinyatakan dengan istilah bahasa Indonesia gunung meletus. Padahal, erupt atau eruption dalam kamus bahasa Inggris juga diartikan meletus atau letusan. Maka, saya usul gunung dipersonifikasikan saja (dianggap orang) sehingga gunung dapat juga muntah atau batuk.
Yang sebaliknya dari personifikasi (mungkin dapat disebut depersonifikasi) juga lumrah dalam bahasa Indonesia, teru- tama untuk perbuatan atau
sifat tak baik. Perbuatan atau sifat orang dianggap perbuatan binatang atau sifat benda. Misalnya di tempat yang seharusnya bukan untuk tempat berkemih (buang air kecil) sering ada tulisan: yang kencing di sini anjing; atau sifat keras kepala seseorang dinyatakan kepala batu. Orang yang tidak tahu malu sering disebut muka badak.
Demikian komentar saya terhadap L Wilardjo di Kompas, 19 Juni 2018.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar