Para calon presiden dan calon wakil presiden serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dipilih secara serentak pada waktu yang sama. Apa dampak pemilu serentak bagi partai-partai politik? Adakah insentif pemilu serentak bagi rakyat? Sebagai konsekuensi logis pemilu serentak, parpol peserta pemilu tidak hanya memperjuangkan terpilihnya capres dan cawapres yang diusung, tetapi juga harus menyelamatkan suara parpol mereka di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Semua parpol tidak ingin gagal dalam pemilu legislatif (pileg) kendati, misalnya, harus gagal dalam pemilihan presiden (pilpres). Meskipun parpol berhasil meloloskan kandidat presiden dan wapresnya, belum tentu parpol yang sama bisa duduk di DPR jika total perolehan suara sah secara nasional tidak mencapai syarat ambang batas parlemen yang ditentukan oleh UU Pemilu. Problemnya, parpol yang tersisih dari DPR cenderung tidak memiliki posisi tawar-menawar politik yang cukup memadai kendati turut "berkeringat" dalam memenangkan sang capres.
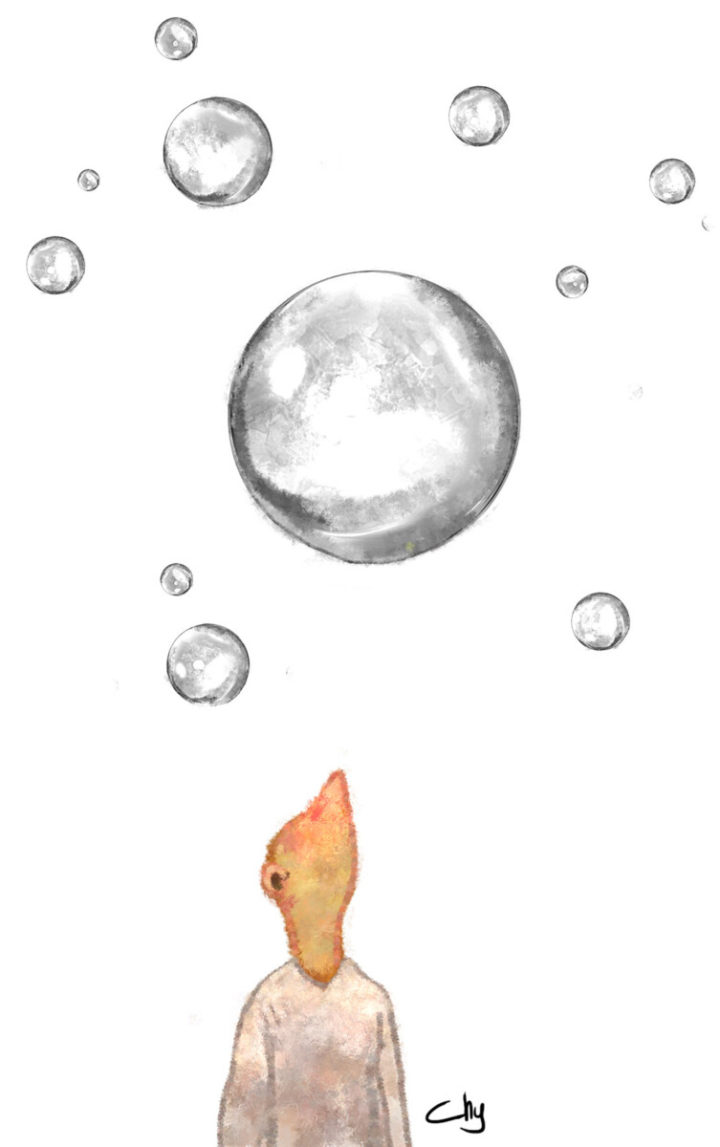
Kondisi berat pemilu serentak 2019 tersebut pada umumnya dipahami oleh parpol. Faktor jumlah parpol peserta pemilu yang semakin banyak (16 partai), ditambah lagi faktor meningkatnya persentase ambang batas parlemen dari 3,5 persen (Pemilu 2014) menjadi 4 persen (2019), membuat sejumlah parpol menyusun berbagai kiat dan strategi untuk mengantisipasinya.
Efek ekor jas
Selain faktor persaingan yang semakin ketat, secara teori, pemilu serentak (concurrent election) cenderung hanya menguntungkan parpol yang menjadi basis politik sang capres. Partai Gerindra yang mengusung sang Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai capres, lebih diuntungkan dalam pileg ketimbang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang juga mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno serta dua parpol pendukung (Partai Berkarya dan Partai Garuda).
Begitu pula dengan pencalonan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang lebih menguntungkan PDI-P daripada lima parpol pengusung (Golkar, PKB, Hanura, Nasdem, dan PPP) serta empat parpol pendukung (Perindo, PSI, PKPI, dan belakangan PBB) karena Jokowi merupakan kader partai bergambar kepala banteng tersebut. Kecenderungan itulah yang sering disebut sebagai efek ekor jas (coattail effect).
Untuk menghadapi kompetisi yang semakin ketat itu, menarik bahwa salah satu strategi parpol adalah membiarkan para caleg mereka mengampanyekan capres yang tidak didukung oleh partai secara institusi. Partai Demokrat, misalnya, meskipun secara institusi mengusung pasangan Prabowo-Sandi, para caleg dibiarkan untuk mengampanyekan Joko Widodo-Ma'ruf Amin jika dapil caleg yang bersangkutan lebih merupakan basis pendukung pasangan calon (paslon) bernomor urut 01 tersebut.
Hal yang sama bisa terjadi pada caleg partai-partai pendukung Jokowi-Ma'ruf yang lebih menyosialisasikan Prabowo- Sandi jika dapil mereka adalah basis pendukung paslon nomor urut 02.
Fenomena serupa sangat mungkin terjadi pada sebagian besar parpol kendati yang terungkap secara publik hanya beberapa caleg dari sejumlah partai, seperti dialami PKS, PAN, dan Partai Bulan Bintang. Yang berbeda adalah cara setiap parpol menyikapinya sehingga muncul kesan seolah-olah terjadi gejolak internal. Namun, tak bisa dimungkiri pula, gejolak internal parpol itu sungguh-sungguh terjadi, terutama karena keputusan pengusungan dan dukungan terhadap capres cenderung dilakukan oleh segelintir elite partai secara oligarkis.
Tidak mengherankan jika kita sering membaca berita, sejumlah calon anggota legislatif (caleg) dari parpol tertentu ternyata mendukung dan mengampanyekan capres lain yang tidak didukung oleh partai mereka.
Kecuali parpol-parpol yang menjadi basis politik capres dan karena itu menikmati efek ekor jas, yakni PDI-P (bagi Jokowi) dan Gerindra (Prabowo), tak satu pun parpol lain yang bisa memastikan peluangnya untuk lolos dari ambang batas parlemen 4 persen. Di luar PDI-P dan Gerindra, parpol besar dan menengah yang relatif "aman" mungkin hanya Golkar dan PKB.
Hampir semua lembaga survei mengonfirmasi potensi elektabilitas empat parpol tersebut. Golkar diuntungkan sebagai partai warisan Orde Baru berideologi "tengah" yang sudah berurat berakar dalam nadi politik sebagian masyarakat Indonesia, sementara PKB memiliki basis kultural Islam moderat yang relatif solid, yakni kaum Nahdliyin di Jawa dan Madura, Lampung, serta Kalimantan Selatan.
Kuburan massal parpol
Pertarungan parpol papan tengah dan bawah dalam Pemilu 2019 jauh lebih berat dibandingkan dengan Pemilu 2014. Persoalannya bukan semata-mata karena keberhasilan parpol dalam pilpres tidak menjamin sukses yang sama dalam pileg, melainkan juga karena penyebaran suara konstituen semakin melebar dan terfragmentasi dengan munculnya empat parpol baru, yakni PSI, Perindo, Partai Berkarya, dan Partai Garuda. Seperti pemilu-pemilu sebelumnya, kehadiran partai-partai baru ini sangat mengkhawatirkan parpol papan tengah dan bawah karena berpotensi menyedot suara mereka.
Dihadapkan pada situasi demikian, para caleg partai-partai di luar PDI-P dan Gerindra pada umumnya bermain "dua kaki", yakni berkampanye sesuai bendera partai mereka di satu pihak, tetapi juga turut menyosialisasikan capres yang tidak didukung oleh parpol mereka secara institusi. Walaupun demikian, berkampanye secara "dua muka" seperti ini bukanlah perkara mudah bagi para caleg.
Demi menyelamatkan suara parpol di dapil masing-masing, apa boleh buat, para caleg kerap kali harus menerima tuduhan sebagai politisi oportunis dan inkonsisten. Terlepas dari tuduhan-tuduhan miring tersebut, orientasi caleg lebih menyelamatkan suara mereka di pileg adalah sebuah pilihan "rasional" ketika aspirasi konstituen tentang capres di dapil berbeda dengan pilihan parpol.
Tak bisa dimungkiri, berbagai kiat dan strategi parpol tersebut diperlukan agar Pemilu 2019 tidak berubah menjadi bencana sekaligus "kuburan" bagi mereka. Sejumlah lembaga survei memprediksi hanya sekitar separuh dari 16 parpol yang bisa lolos ke Senayan. Itu artinya, Pemilu 2019 bisa saja akan menjadi kuburan massal bagi partai-partai yang gagal memenuhi syarat ambang batas parlemen 4 persen sesuai dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.
Dari hasil survei publik yang dilakukan oleh lima lembaga survei berbeda sepanjang Mei 2018 hingga Januari 2019, yakni LIPI (survei dilakukan awal Mei 2018), Indikator Indonesia (September 2018), Populi Center (September 2018), Litbang Kompas (Oktober 2018), dan Charta Politika (Januari 2019), hanya lima hingga delapan parpol yang diperkirakan lolos ambang batas parlemen. Partai-partai tersebut adalah PDI-P, Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, Nasdem, PPP, dan PKS.
Partai-partai selebihnya, apa boleh buat, harus terkubur bersama ingar-bingar Pemilu 2019. Meski demikian, perlu segera dicatat, pertama, prediksi lembaga-lembaga survei tersebut hanya berlaku pada saat survei berlangsung. Artinya, potensi elektabilitas partai-partai saat pemungutan suara nanti mungkin saja sudah banyak berubah dibandingkan dengan saat survei dilakukan.
Kedua, pada umumnya hasil survei-survei tersebut belum memperhitungkan potensi kesalahan (margin of error) yang berkisar 2,0 hingga 3,0 persen sehingga ada peluang parpol yang semula diperkirakan tidak lolos menjadi lolos ambang batas parlemen.
Ketiga, masa kampanye Pemilu 2019 masih berlangsung hingga 15 April 2019 sehingga masih terbuka peluang bagi partai-partai yang diprediksi gagal oleh lembaga survei untuk mendongkrak potensi elektabilitas mereka.
Merajut harapan
Perjuangan partai-partai politik merebut suara rakyat dalam pemilu tentu wajar-wajar saja. Akan tetapi, perjuangan itu semestinya bukan sekadar memenuhi syarat ambang batas parlemen agar bisa meraih tiket ke Senayan. Melalui pemilu serentak yang pertama kali digelar pada 2019 ini, publik juga berharap ada insentif politik yang signifikan, misalnya saja meningkatnya kualitas kinerja partai-partai di DPR. Harapan lain adalah meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas sistem pemerintahan presidensial sehingga cita-cita keadilan dan kesejahteraan rakyat semakin dekat untuk diraih.
Barangkali di sinilah letak problem pemilu-pemilu kita. Meskipun skema pemilu telah diubah dari terpisah menjadi serentak, hampir tak ada insentif politik yang dinikmati publik di balik keserentakannya. UU Pemilu yang baru tak menjanjikan insentif apa pun selain sekadar sirkulasi kekuasaan politisi di lembaga perwakilan.
Seperti pemilu-pemilu sebelumnya, sebagian parpol harus tersisih, sebagian lain bertahan. Begitu pula para politisi, meski tanpa kinerja dan prestasi jelas, sebagian wakil rakyat bertahan, sementara sebagian lain gigit jari karena harus angkat kaki dari DPR. Kehidupan politik pun berulang seperti sediakala. Pasca-pemilu, wakil-wakil rakyat sibuk sendiri di tengah impitan kehidupan sosial ekonomi mayoritas rakyat yang kian sulit. Rakyat akhirnya hanya merajut harapan dari pemilu ke pemilu. Lalu, sampai kapan kita menjadikan pemilu sekadar momentum sirkulasi kekuasaan elite politik?

Tidak ada komentar:
Posting Komentar