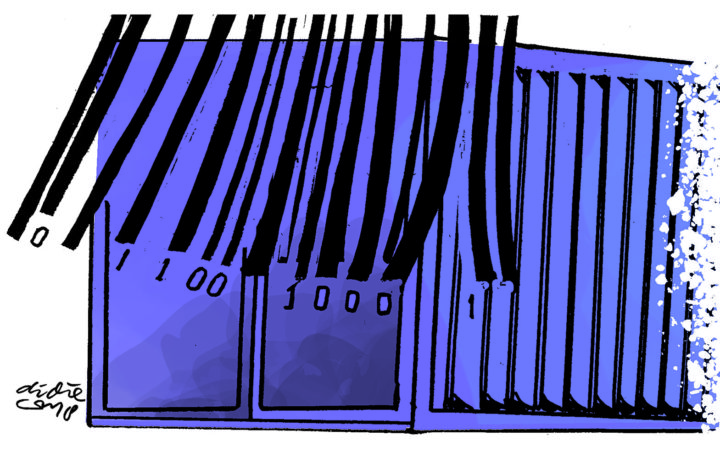
Perang dagang di antara dua raksasa ekonomi dunia, AS dan China, belum merupakan perang tarif, apalagi perang dagang dunia, diukur dari apa yang terjadi pada 1930-an. Namun, perkembangan terakhir, selain memprihatinkan, juga menyangkut masalah lebih mendasar sehingga perlu diwaspadai.
Banyak pihak, termasuk para pejabat tinggi pemerintah, yang menyebutkan ini sebagai salah satu masalah atau tantangan yang harus dihadapi Indonesia, tanpa menunjukkan apa arti perang dagang itu sesungguhnya dan masalah apa yang memengaruhi prospek ekonomi Indonesia.
Saya ingin membahas mengapa perkembangan ini mengkhawatirkan dan perlu diwaspadai dengan mengacu pada tulisan Profesor Jenifer Hillman, seorang ahli hukum dari Georgetown University dan mantan anggota Appellate Body, mahkamah yang mengadili pertikaian dagang melalui mekanisme penyelesaian sengketa (dispute settlement) dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Mahkamah ini beranggotakan tujuh hakim dan berwenang membuat keputusan terkait pertikaian dagang yang diajukan negara anggota setelah mendengarkan laporan sejumlah ahli dari kasus yang diajukan.
Dalam tulisan di New York Times (1/6/2018), Hillman menunjukkan bahwa rangkaian langkah yang dilakukan Presiden Trump dalam pertikaian dagang AS-China baru-baru ini mengandung berbagai cacat hukum karena melanggar aturan perdagangan internasional.
Langkah-langkah itu menyangkut, pertama, pada 23 Mei 2018 Trump menginstruksikan dilakukannya investigasi untuk menentukan apakah impor mobil dan SUV (sport utility vehicle) selama ini membahayakan keamanan Amerika Serikat. Kalau investigasi ini menyimpulkan impor mobil dan SUV memang membahayakan keamanan nasional, Pemerintah AS berhak mengenakan tarif tinggi atas impor itu.
Kedua, Trump membebaskan perusahaan telekomunikasi raksasa China, ZTE, dari pengenaan sanksi meski terbukti membuat laporan palsu serta berkali-kali melanggar larangan melakukan hubungan dagang dengan Korea Utara dan Iran. Ketiga, mengenakan tarif tinggi terhadap impor baja dan aluminium dari sejumlah negara mitra dagang yang sebelumnya dikecualikan, yakni Kanada, Meksiko, dan Uni Eropa (UE), sejak awal Juni 2018.
Pelanggaran ketentuan perdagangan internasional
Bahwa China melakukan berbagai langkah yang merugikan AS dalam hubungan dagang bilateralnya, seperti pengaturan kepemilikan saham perusahaan asing yang beroperasi di China dan pengalihan teknologi yang berkaitan dengan hak cipta (intellectual property right/IPR) serta langkah lain yang menyebabkan defisit neraca perdagangan AS dalam perdagangan bilateral mereka memang susah dibantah. Tahun lalu neraca perdagangan AS dengan China defisit 375 miliar dollar AS.
Upaya Trump menghilangkan defisit neraca perdagangannya dan mendorong kembalinya operasi perusahaan-perusahaan AS di China dan negara-negara lain tentu sah-sah saja. Akan tetapi, cara yang digunakan untuk mencapai hal itu bermasalah. Potensi timbulnya masalah menyangkut dasar hukum dari langkah-langkah itu. Instruksi Trump untuk investigasi apakah impor mobil dan SUV itu membahayakan keamanan nasional AS, serupa dengan penerapan tarif tinggi untuk impor baja dan aluminium, jelas melanggar ketentuan perdagangan internasional WTO.
Dasar kebijakan itu adalah Undang-Undang Perdagangan AS (Trade Act 1962) yang dalam Pasal 302 disebutkan presiden diberi kewenangan untuk mengecualikan dari ketentuan penurunan tarif impor dalam hal yang berkaitan dengan perdagangan alat-alat senjata dan nuklir atau dalam masa perang karena impor itu membahayakan keamanan nasional.
Sebagaimana diketahui, pengaturan perdagangan internasional setelah berakhirnya Perang Dunia II adalah melalui kesepakatan tarif dan perdagangan atau GATT, di mana para penanda tangan kesepakatan berjanji menurunkan tarif yang sangat tinggi sebelumnya. Seperti dalam sistem Bretton Woods untuk pembayaran, moneter dan pembangunan melalui Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, kesepakatan perdagangan dalam GATT dimotori negara-negara yang menang dalam perang dengan pimpinan AS.
Perundingan penurunan tarif dan rintangan perdagangan lain dilakukan melalui berbagai perundingan, dikenal sebagai Putaran Geneva (Geneva Round), Putaran Kennedy (Kennedy Round), Putaran Uruguay (Uruguay Round), dan yang terakhir sebelum pembentukan WTO, Putaran Doha (Doha Round). AS memimpin gerakan penurunan tarif melalui aturan perundangan perdagangannya. Pasal 302 ini mengatur kemungkinan pengecualiannya, yaitu dalam keadaan yang dianggap membahayakan keamanan nasionalnya.
Ironisnya, langkah ini dilancarkan untuk menunjukkan ketaatannya terhadap aturan perundangan. Hanya saja, menjadi aneh dilakukan pada 2018 yang kondisinya sudah jauh berbeda dengan 1960-an. Untuk mengatakan impor mobil, aluminium, dan baja mengganggu keamanan dalam negeri AS, jelas tak masuk akal. Penerapan tarif tinggi untuk impor sejumlah produk kepada sejumlah negara jelas bertentangan dengan prinsip utama perdagangan dunia sejak GATT dan dikokohkan dalam WTO, dikenal sebagai prinsip non-discriminatory, pilar utama perdagangan dunia.
Konyolnya lagi cara yang ditempuh sebenarnya tak jelas akan menghasilkan apa yang diinginkan. Secara konseptual mudah ditunjukkan susahnya mencapai sasaran yang ingin dituju melalui cara-cara ini. Justru dampak negatifnya lebih menonjol. Kebanyakan produk di masa kini dihasilkan melalui rantai pasokan (supply-chain) yang implikasinya terhadap perhitungan impor-ekspor jauh lebih kompleks dari cara pandang merkantilis yang tampaknya mendasari kebijakan AS dalam upaya menghukum semua mitra dagang yang dianggap bersalah karena menimbulkan defisit neraca perdagangan buat AS. Namun, buat Trump hal itu memang menjadi sikapnya, tak percaya pada hubungan multilateral yang katanya merugikan AS. Kebijakan America First bertentangan dengan WTO dan kesepakatan multilateral lain yang berdasarkan aturan yang disepakati semua pihak atau rule-based.
Negara-negara yang merasa dirugikan dengan langkah-langkah ini akan membalasnya dengan langkah-langkah retaliasi. China, Kanada, UE, serta Meksiko, dengan cara dan penekanan masing-masing, telah mengeluarkan pernyataan akan melakukan langkah balasan terhadap apa yang dilakukan AS ini. Dalam hal ini pertikaian dagang ini meski tetap tak setara dengan perang dagang tahun 1930-an, memang kian menunjukkan sifatnya sebagai perang. Perundingan yang dilakukan di Beijing dan Washington akhirnya tidak menghasilkan kesepakatan dan peningkatan tarif impor oleh AS sudah dibalas dengan peningkatan impor oleh China, bahkan oleh negara-negara mitra dagang terdekat AS sendiri, seperti UE, Kanada, dan Meksiko.
Tampaknya semakin besar potensi terjadinya ketegangan hubungan perdagangan yang lebih gampang berubah menjadi perang tarif dan perang dagang. Kalaupun tak sama dengan perang dagang 1930-an setelah diberlakukannya Smoot-Hawley Act yang berkembang menjadi depresi (dikenal sebagai the Great Depression, kecenderungannya kian jelas ke arah itu).
Mengenai langkah kedua, masalahnya adalah bahwa memutuskan untuk membebaskan perusahaan telekomunikasi ZTE —yang menurut pemberitaan karena menyangkut deal yang dilakukan China yang menguntungkan perusahaan milik Trump menyangkut investasinya di sektor properti di Bali di mana mitra Indonesianya memperoleh pinjaman dari China—sangat tidak etis karena ada konflik kepentingan dengan perusahaan keluarga.
Menjurus ke situasi berbahaya
Tanpa membahasnya secara mendetail, saya akan menyebutkan beberapa catatan yang pada dasarnya menggarisbawahi mengapa pertikaian yang menjurus menjadi perang tarif dan dagang AS-China ini—seperti telah dikemukakan pemerintah dan para pengamat—harus diwaspadai dan disiapkan langkah-langkah penanggulangan dampak negatifnya buat Indonesia. Juga pentingnya memanfaatkan peluang baru yang terbuka.
Perkembangan terakhir jelas menjurus pada situasi yang lebih membahayakan. Pemerintahan Trump telah memutuskan untuk memasang tarif 25 persen terhadap sejumlah produk China yang berteknologi dan komunikasi sesuai dengan tuduhan AS bahwa China telah mencuri pengembangan teknologinya. Langkah itu yang meliputi impor dari China senilai 50 miliar dollar AS, bersamaan dengan kejadian yang lebih tegas menunjukkan AS tidak peduli terhadap kesepakatan regional dan multilateral serta kelembagaannya.
Terakhir, dengan insiden pertemuan G7 di Quebec, Kanada, saat AS mengusulkan masuk kembalinya Rusia ke dalam kelompok G7, tak menandatangani pernyataan G7, dan ditambah lagi dengan pernyataan Trump bahwa sebagai tuan rumah pertemuan PM Kanada Justin Trudeau sebagai tidak jujur dan lemah.
Hal ini terjadi setelah rentetan peristiwa sejak awal pemerintahan Trump dengan keluar dari kesepakatan Paris tentang perubahan iklim, keluar dari Kemitraan Trans-Pasifik, keluar dari kesepakatan tentang denuklirisasi Iran. Semua ini kian menunjukkan sikap AS yang meninggalkan proses globalisasi dan kerja sama yang mendasarkan aturan kesepakatan (rule-based) regional ataupun multilateral serta menggantinya dengan kebijakan proteksi America First-nya.
Pertikaian dagang kedua negara raksasa dunia ini sudah berkembang minimal ke negara-negara mitra terdekat AS, bahkan India, yang justru seyogianya dirangkul AS untuk memengaruhi agar pertumbuhan China sebagai kekuatan ekonomi dan keuangan global tidak menumbuhkan dampak sampingan yang justru merugikan.
Bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, kondisi ini dilematis. Di satu pihak, China semakin jelas menunjukkan ambisinya menjadi pemimpin perekonomian dunia dengan program Belt and Road Initiatives (BRI) dan program Made in 2025-nya. Ini tidak bisa dibiarkan berjalan tanpa kekuatan yang mengimbanginya guna mengurangi dampak negatifnya pada perekonomian negara-negara lain. Di pihak lain, AS semakin menarik diri dari posisi kepemimpinannya karena semakin mundur dari globalisasi dan multilateralisme. Paling tidak, sebelum adanya keseimbangan baru ini, berarti ada ketidakpastian yang tinggi dan meningkat.
Semua ini ditambah dengan kebijakan moneter dan keuangan yang semakin jelas meninggalkan kebijakan keuangan longgar—mengganti quantitative easing dengan quantitative tightening—telah mendorong pernyataan-pernyataan tentang meningkatnya risiko keuangan dan ketegangan perdagangan, seperti disampaikan oleh Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde dan Global Economic Prospect terakhir dari Bank Dunia. Bahkan, George Soros mengkhawatirkan timbulnya krisis keuangan.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar