Namun, rasa-rasanya masih sulit memberi "label" perkembangan demokrasi Indonesia. Apakah sudah masuk tahap berikutnya, tahap penguatan lembaga-lembaga demokrasi, atau justru ke arah sebaliknya.
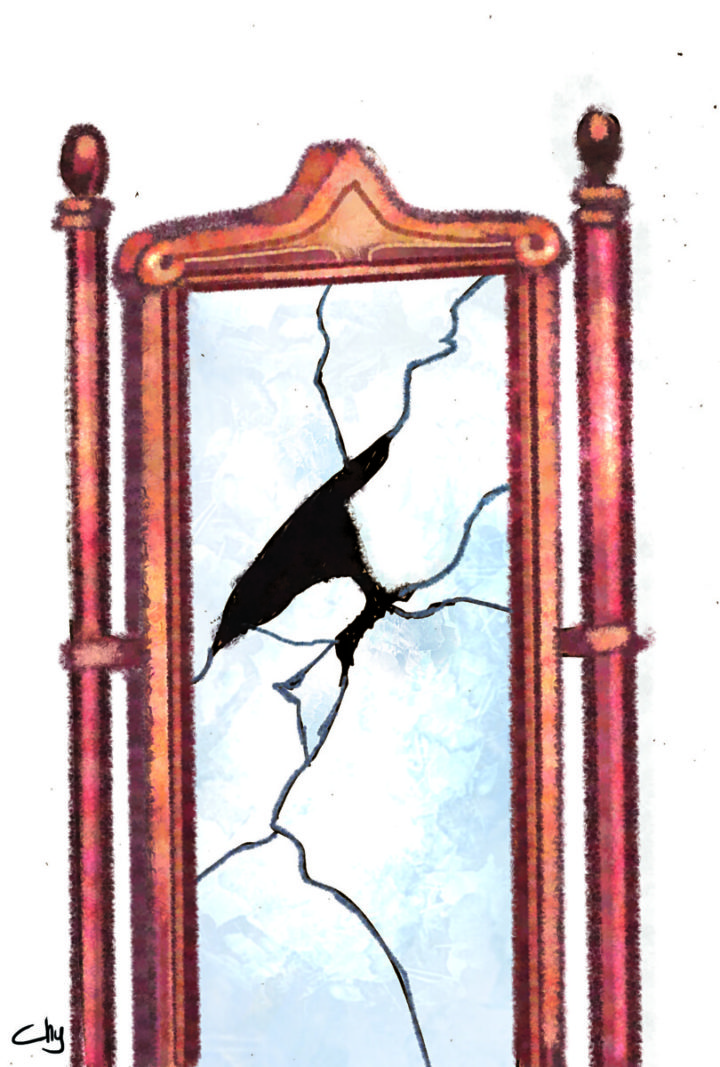
Mengapa sulit? Karena proses demokrasi kita cenderung mengarah pada demokrasi ilusif (elusive democracy), sebuah demokrasi yang sulit dipahami arahnya, apakah akan terjerembap pada demokrasi prosedural (procedural democracy) ataukah akan mencapai batas minimal demokrasi substansial (substantial democracy). Apa makna demokrasi ilusif dan bagaimana kita menandainya?
Kecenderungan demokrasi ilusif
Salah satu ciri dari demokrasi ilusif ialah terjadinya politik anomali dalam tahap instalasi demokrasi. Instalasi demokrasi, sebuah proses di mana institusi-institusi demokrasi tumbuh dan berkembang di era transisi. Tahapan instalasi demokrasi dilakukan setelah Pemilu 2004 hingga Pemilu 2009, yang ditandai dengan lahirnya amendemen UUD 1945 pertama, kedua, dan ketiga, serta sejumlah pembentukan institusi-institusi demokrasi lainnya.
Seiring dengan proses instalasi demokrasi, di sisi yang lain proses politik juga diiringi oleh maraknya politik anomali. Ciri dari politik anomali itu, antara lain, pada proses dan prosedurnya, sistem demokrasi sebenarnya bekerja. Namun, ruang demokrasi itu dimanfaatkan oleh orang-orang kuat, politik kekerabatan, dinasti politik, dan oligarki. Kekuatan-kekuatan politik sipil "tereduksi" karena semua esensi politik dan kedaulatan rakyat dikerangkeng oleh berkuasanya partai politik dalam sistem politik.
Dalam bahasa sederhana, suasana kehidupan berbangsa dan bernegara kita, wadahnya adalah demokrasi, tetapi nilai dan aktornya dikerumuni oleh politik tradisional yang sesungguhnya bukanlah aktor yang dikehendaki oleh demokrasi.
Hampir tidak ada "ruang kosong" demokrasi bagi kepentingan masyarakat madani (civil society) secara setara karena institusi yang tumbuh dari proses dan prosedur demokrasi diisi oleh kepentingan politik yang kuat dan dekat dengan kekuasaan serta diisi oleh aktor-aktor dari partai politik. Institusi demokrasi tumbuh, tetapi proses pembajakan oleh partai politik dan orang kuat juga tidak bisa dihindarkan.
Partai politik menjadi sumbu tunggal dalam pengisian ruang demokrasi, menentukan segalanya. Aktor-aktor penting dalam civil society "nyaris lumpuh" akibat terserap dalam jabatan-jabatan political appointee. Bangunan struktur pemerintahan (state formation) hampir membawa gerbong "orang yang ditunjuk secara politis", baik di pemerintahan maupun parlemen.
Pelumpuhan aktor civil society melalui pemberian wadah dalam politik praktis, baik sebagai political appointee, tim sukses, tim sukarelawan, maupun sejenisnya menyebabkan proses politik kurang mendapat pengawalan. Kritik sebagai bagian dari kehidupan demokrasi dianggap sebagai "ancaman" popularitas pemerintah sehingga demokrasi yang sejatinya memberi ruang besar terhadap kritik berubah suasana, kritik harus memberikan solusi.
Kita semua paham, demokrasi tanpa kritik akan menjadi "tirani mayoritas atau tirani kekuasaan." Sebaliknya, proses politik yang dikritik terus-menerus akan mengalami deligitimasi dan pada titik tertentu akan terjadi anarki. Kedua-duanya bukanlah pilihan, tetapi demokrasi memerlukan rule of law yang kuat, independen, dan tidak berpihak atau memihak. Tegaknya hukum "yang setara"—tidak tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas—menjadi garda dalam mewujudkan keseimbangan agar demokrasi berada pada garis yang sesungguhnya, bukan cenderung pada "tirani mayoritas/kekuasaan" dan juga bukan "anarki".
Demokrasi membutuhkan penegak hukum yang independen yang bekerja sesuai dengan motonya, "fiat justitia ruat caelum, hendaklah keadilan ditegakkan walau langit akan runtuh".
Melemahnya institusi demokrasi
Badan Pusat Statistik telah mengeluarkan laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2017. Ada tiga pesan penting dari laporan IDI 2017. Pertama, citra demokrasi tampak jelas dan kuat, tetapi minim kapasitas. Masifnya gerakan menghadirkan negara (state image) dan revitalisasi aturan main yang menyertainya mengabaikan penguatan kapasitas negara di kehidupan sehari-hari (state in practice) (IDI, 2017: 61).
Pesan yang kedua, bahwa perkembangan demokrasi kita mengarah pada masih minimnya fungsi lembaga-lembaga demokrasi. Pesan terakhir, bahwa ada kecenderungan demokrasi memberikan ruang bagi publik untuk memberikan suara dalam pemilu (vote), tetapi suara itu tidak memberi makna dalam proses kebijakan akibat proses politik minim voice. Rakyat yang memiliki kedaulatan (vote), suara dan aspirasinya ditinggalkan oleh wakil-wakilnya yang duduk di parlemen dan sebagian di pemerintahan.
Perkembangan seperti itu merupakan ciri lain dari demokrasi ilusif. Demokrasi menghadapi tantangan berat karena bangunan institusi-institusi demokrasi yang dilahirkan di era reformasi seperti partai politik, lembaga antikorupsi, komisi konstitusi, dan aktor-aktor yang memiliki pengaruh pada perkembangan demokrasi (government, civil society, dan kekuatan-kekuatan masyarakat lainnya) menjadi aktor yang mendukung penguatan institusi demokrasi ataukah sebaliknya.
Salah satu ciri penting secara teoretik suatu negara yang mengalami transisi disebut telah berada pada tahap konsolidasi demokrasi manakala pemerintahan demokratis yang terpilih, pemerintahannya berfungsi (governable) dan aktor-aktor politik (elite) menjadikan agenda penguatan demokrasi sebagai tujuan utama membangun sistem politik.
Dalam konteks itu, perubahan sistem pemilu, sistem kepartaian, dan sistem perwakilan di Indonesia masih cenderung bersifat tambal sulam. Perubahan regulasi yang terkait dengan sistem pemilu, kepartaian, dan perwakilan ternyata tidak memperbaiki watak lembaga- lembaga politik dan akuntabilitas elite politik hasil pemilu. Budaya korup dan perburuan rente justru semakin merebak.
Politik minus moral
Demokrasi ilusif juga ditandai oleh politik minus moral. Moralitas politik terabaikan akibat budaya politik rente masih "berkeliaran". Banyaknya politisi yang terjerat kasus korupsi dan operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan nilai-nilai good and clean governance (tata kelola yang baik dan bersih) yang melandasi praktik demokrasi yang diharapkan.
Keadaban politik di ruang publik juga minim narasi kebajikan. Tujuan untuk mencapai kekuasaan dengan segala cara menyebabkan demokrasi kita bisa kehilangan nurani kebajikan. Padahal, dalam proses dan tumbuhnya demokrasi pada suatu negara, budaya berdemokrasi harus dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, kebebasan, kejujuran, menjunjung harkat dan martabat manusia, penuh toleransi, serta menjauhi anarki—sikap ingin menang sendiri.
Praktik-praktik KKN yang akar tunjangnya tumbuh kuat pada masa Orde Baru belum sirna karena yang tumbang hanya Soeharto. Rezim Orde Baru mengalami metamorfosis dalam bingkai demokrasi liberal di era reformasi. Oligarki dan politik kartel tumbuh kuat (Mietzner 2015) (Ambardi 2008).
Akar oligarki seperti itu ternyata tetap saja tumbuh subur dan ironisnya, oligarki muncul pada hampir semua tingkatan, mulai dari organisasi sipil, keagamaan, hingga partai politik. Bahkan, struktur pemerintahan di daerah menunjukkan pola yang lebih rumit, tidak sekadar oligarki, tetapi sekaligus dinasti politik.
Refleksi tingkah laku berpolitik yang minim moral akan semakin menjauhkan demokrasi dari cita-cita utamanya, membawa kesejahteraan bagi umat manusia. Sampai kapan budaya politik kita terjerembap dalam kubangan budaya patrimonial seperti pernah disinggung Emerson dan berubah ke arah budaya demokrasi yang berpijak pada kompetisi yang adil, jujur, penuh damai, dan mencerminkan integritas? Cita-cita itu rasanya masih jauh.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar