Revisi UU ini sebenarnya berangkat dari hal sederhana tentang definisi terorisme. Definisi tentang terorisme yang sebenarnya tidak krusial, malah menjadi perdebatan yang alot selama proses dua tahun revisi UU No 15/2003 ini.
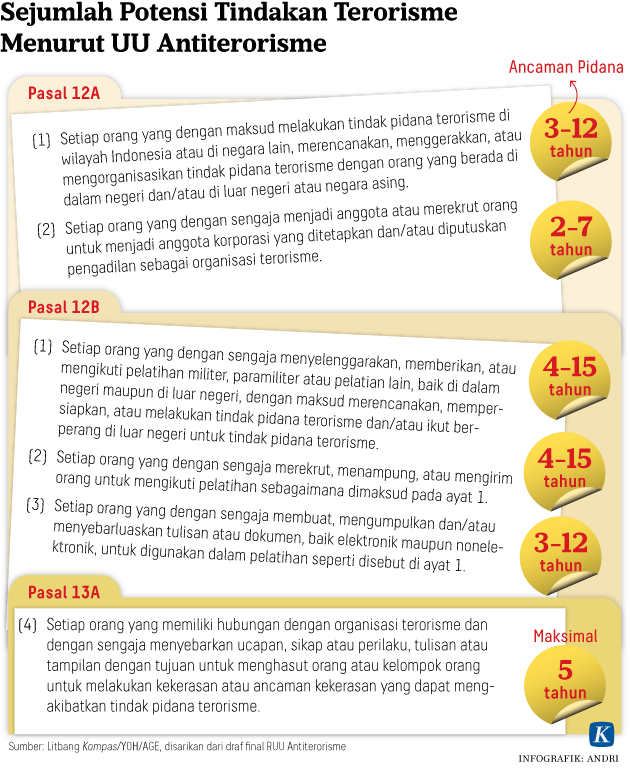
"Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan."
Definisi ini sebenarnya sudah cukup untuk kebutuhan legislasi, tidak seperti dalam definisi terorisme yang akademis di mana unsur-unsur millenarianisme, fundamentalisme dan radikalisme mesti dielaborasi lebih lanjut dalam kajian dan penelitian teoritik.

Pengesahan revisi UU No 15/2003 mengenai terorisme dinilai mendesak sejak kekalahan Negara Islam Irak Suriah (NIIS/ISIS) di Filipina dan Suriah. Sudah lebih dari 15 tahun UU anti teror ini tidak direvisi, sementara perkembangan terorisme semakin brutal, sadis dan gila. Teror menyeruak hampir di semua sektor kehidupan di banyak negara kebangsaan di berbagai belahan dunia.
Bahkan terorisme NIIS telah hadir di Jalan Thamrin (2016) dan Kampung Melayu (2017), Jakarta, di beranda terdekat di negeri ini. Kehadiran terorisme yang tak terpahami preseden dan motif lainnya di luar motif teologi eskatologis di mana kematian dipandang sebagai cara pintas memasuki surga. Kematian dipakai untuk menakut-nakuti musuh agama yang tak terdeskripsikan, dalam suatu "perang" yang tak pernah terdengar deklarasinya sekalipun.
Terorisme "tamkin"
Ada satu persoalan krusial yang belum terakomodasikan dalam UU Antiterorisme yang baru disahkan ini. UU baru ini tidak menerapkan konsep terorisme tamkin (terorisme teritorial) yang menjadi masalah terorisme penting abad ini. Terorisme tamkin inilah yang kemudian menjadi pangkal perseteruan antara Polri dan TNI dalam hal tugas pokok dan fungsi mereka untuk menangani terorisme.

Tim penyidik Polri memeriksa lokasi ledakan bom di Gereja Santa Maria Tak Bercela, Jalan Ngagel Madya, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (13/5/2018).
Kisruh pembagian wewenang di antara Polri dan TNI dianggap menempatkan Indonesia dalam risiko yang tak perlu. Ada perubahan signifikan terhadap sistematika UU, menambah bab pencegahan, bab soal korban, bab kelembagaan, bab pengawasan, kemudian soal peran TNI yang itu semua hal baru dibandingkan UU sebelumnya.
Memang harus juga diakui bahwa UU yang sebelum ini menghambat polisi untuk bergerak jika pelaku sudah terbukti sebagai pelaku terorisme. Kewenangan mencegah pelaku dalam aksi sangat lemah. UU yang terbaru dapat memberikan wewenang lebih pada Polri untuk melakukan fungsi pencegahan.
Penanganan terpadu dan efektif butuh payung hukum yang lebih kuat. UU ini malah memberikan peneguhan untuk lembaga yang menjalankan program deradikalisasi yang sebenarnya tidak perlu dimasukkan dalam UU.

Pemerintah Indonesia melalui DPR sudah berhasil merevisi UU No 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang tertunda akibat perdebatan alot seputar pembagian wewenang antara polisi dan militer.
Secara teoritik, pelibatan militer di dalam menangani terorisme sudah dibahas oleh banyak peneliti tentang kemunculan strategi qital tamkin (perang di daerah pembebasan) yang menjadi ciri khas kelompok teroris teritorial. Sebutlah seperti MIT (Mujahidin Indonesia Timur), GAM (Gerakan Aceh Merdeka), RMS (Republik Maluku Selatan), OPM (Organisasi Papua Merdeka), Abu Sayyaf Group (ASG).
Menurut saya, terorisme teritorial harus ditangani secara khusus oleh TNI (misalnya, Koopsusgab). Terorisme tamkin (teritorial) ini jika ditangkap maka implikasi yuridisnya adalah akan diadili di sidang pengadilan humaniter atau pengadilan militer.

Kapolri Tito Karnavian saat RS Bhayangkara Surabaya, Minggu (14/5/2018). Tito menyebut bahwa para pelaku bom sepanjang Minggu hingga Selasa ini masing-masing merupakan satu keluarga, yang terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya sekaligus.
Kamil Salamah (1994, 181) telah membahas bahwa terorisme teritorial punya basis ideologi agama yang kuat. Teroris yang menerapkan strategi perang teritorial (Djelantik dan Akbar, 2016: 90) harus dihadapi oleh aparat keamanan yang memiliki kemampuan tempur yang memadai.
Thomas Koruth Samuel (2016: 53) dan Al Chiadar (2015: 245) juga sudah membahas betapa penanganan yang salah terhadap teroris tamkin menunjukkan kurangnya kesadaran teritorial dari para pemimpin politik sebagaimana terlihat di Thailand, Filipina dan Suriah.
Sidney Jones (2015) juga sudah mengingatkan kita akan kemunculan qital tamkin yang dimiliki oleh teroris teritorial yang berbeda dengan qital nikoyah yang hanya melakukan strategi hit and run di berbagai lokasi. Terorisme tanzhim (non- teritorial) cukup ditangani dan dihadapi oleh polisi, dan jika teroris tanzim ditangkap cukup disidangkan di pengadilan negeri atau pengadilan sipil.

Personel TNI diturunkan di salah satu lokasi teror bom Gereja Santa Maria Tak Bercela, Jalan Ngagel Madya, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (13/5/2018).
KOMPAS/AMBROSIUS HARTO (BRO)
Perubahan dari strategi nikoyah ke strategi teritorial inilah yang harusnya diagregasi dan diartikulasikan secara tepat di dalam UU Antiterorisme yang baru ini. Sebab, hal yang saat ini menjadi fokus jihadis adalah nikayah atau melukai, menyerang, dan melumpuhkan orang yang mereka anggap sebagai "kafir" dalam sistem taksonomi hukum mereka yang keliru.
Bagi kelompok teroris yang berideologi Wahabi Takfiri ini, yang paling penting adalah tamkin, yaitu menguasai sebuah wilayah dengan pemimpin yang paham ilmu syar'i (hukum agama) dan fiqhul waqi' (hukum politik). Para ulama mereka yang dianggap sebagai intelektual organik telah mengeluarkan sejumlah fatwa brutal dan sadis yang mengingkari nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. UU

Tidak ada komentar:
Posting Komentar