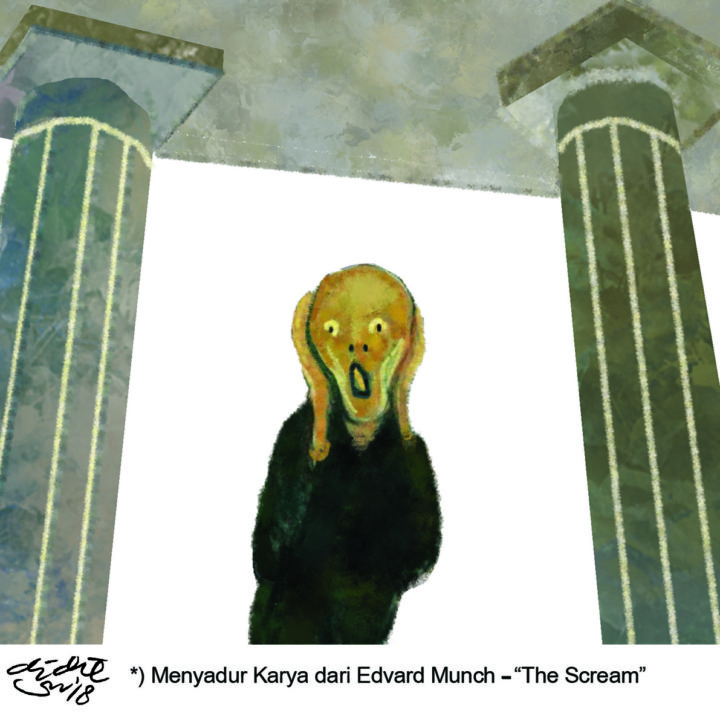
Mengawali semester II-2018, nilai tukar dollar Amerika Serikat cenderung terus menguat atas mata uang global.
Estimasi dari awal tahun menunjukkan terjadinya apresiasi dollar AS 3,6 persen atas euro dan 2,8 persen atas yuan China. Pada tingkat regional ASEAN, dollar AS menguat atas rupiah 6,8 persen, ringgit Malaysia 0,5 persen, dollar Singapura 2,3 persen, dan baht Thailand 2,2 persen.
Penguatan ini sering dipahami sebagai implikasi kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS, (The Fed) dan sengketa perdagangan AS-China. Secara umum sering disebut bahwa perkembangan global ini merupakan akibat dari kebijakan Presiden AS Donald Trump. Namun, argumentasi pengaruh kebijakan eksternal ini tak sepenuhnya kuat.
Pelemahan rupiah tidak saja terhadap dollar AS, tetapi juga pada mata uang lain. Euro mengalami apresiasi atas rupiah 3 persen, yuan dan yen masing-masing menguat 3,9 dan 8 persen. Terhadap negara sekawasan, ringgit menguat 5,96 persen atas rupiah, begitu juga dollar Singapura dan baht Thailand, masing-masing menguat 3,6 persen dan 4,2 persen.
Berada pada nilai di atas Rp 14.000 per dollar AS menjadikan asumsi nilai tukar pada penyusunan APBN 2018 sangat berbeda, yaitu Rp 13.400 per dollar AS. Karena itu, memahami penyebab guncangan rupiah menjadi esensial sehingga solusi yang diambil pun lebih baik.
Estimasi nilai tukar riil
Perhitungan nilai tukar riil menggambarkan nilai tukar keseimbangan dalam referensi ekonomi moneter. Jika nilai rupiah saat ini lebih lemah daripada keseimbangannya, rupiah dinyatakan undervalued. Demikian sebaliknya, jika lebih kuat, rupiah dinyatakan overvalued. Estimasi atas keseimbangan ini dapat menggunakan beberapa cara perhitungan, yang pada dasarnya menggambarkan fundamental ekonomi suatu negara.
Pada gilirannya rupiah akan bergerak menuju keseimbangan. Jika undervalued, rupiah akan mengalami apresiasi. Demikian halnya jika overvalued, rupiah akan mengalami depresiasi. Beberapa studi mengestimasi bahwa rupiah, yang saat ini berada di atas Rp 14.000-an, mengalami undervalued.
Nilai tukar dapat bergerak berbeda dari nilai keseimbangan disebabkan oleh faktor jangka pendek, yaitu perkembangan eksternal (perilaku investor portofolio) dan efek kepanikan. Faktor pertama, perilaku investor pada akhirnya akan dipengaruhi oleh fundamental ekonomi. Salah satu yang prinsip adalah selama inflasi suatu negara masih lebih tinggi daripada negara lain, daya saing ekonomi dan khususnya perdagangan negara itu akan lebih rendah. Konsekuensinya, mata uang negara itu akan mengalami depresiasi.
Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam tiga tahun terakhir dapat meredam inflasi hingga di bawah 4 persen. Performa ini suatu pencapaian karena terjadi untuk tiga tahun berturut-turut. Namun, tetap saja inflasi ini masih lebih tinggi daripada sejumlah negara sekawasan, termasuk Thailand, Malaysia, dan Singapura. Karena itu, tidak bisa dielakkan jika rupiah mengalami depresiasi.
Namun, kalaupun depresiasi, hasil estimasi Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) hanya akan bergerak pada kisaran Rp 13.804-Rp 13.845 per dollar AS untuk 2018. Estimasi ini merujuk pada landasan diferensial riil sehingga nilai rupiah di atas Rp 14.000 per dollar AS cenderung undervalued.
Kenaikan suku bunga
Selama beberapa tahun terakhir, rupiah, yang secara fundamental mengalami depresiasi, terlihat stabil dan pernah apresiasi terhadap dollar AS seperti pada 2011. Investor portofolio memegang rupiah karena tertarik menanamkan investasi pada pasar uang dan pasar modal. Namun, pergerakan investor portofolio dapat dengan mudah berbalik arah. Supaya investor portofolio, baik asing maupun domestik, tertarik memegang rupiah, daya tarik dipertahankan.
Tidak heran jika BI melakukan tren pembalikan suku bunga (7-day Reverse Repo Rate) sejak Mei 2018, yakni dari 4,25 persen menjadi 4,50 persen atau naik 25 basis poin (bps) pada pertengahan Mei 2018, kemudian 4,75 persen (naik 25 bps) pada akhir Mei 2018, dan 5,25 persen (naik 50 bps) pada akhir Juni 2018.
Namun, apakah kenaikan suku bunga ini efektif? Data Juni hingga awal Juli 2018 menunjukkan, depresiasi rupiah masih terjadi. Malah kenaikan suku bunga ini akan mengganggu upaya mendorong ekonomi yang ekspansif sejak September 2017 dengan suku bunga 4,25 persen dari periode sebelumnya yang terus menurun.
Kenaikan suku bunga hanya akan memperparah pertumbuhan kredit. Dalam beberapa tahun terakhir, kredit perbankan hanya bertumbuh rendah, bahkan satu digit pada 2016-2017. Pertumbuhan kredit yang rendah akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Ekspektasi pertumbuhan ekonomi 5,4 persen seperti pada asumsi APBN 2018 tidak logis dan koreksi Bank Dunia menjadi 5,2 persen lebih masuk akal.
Kenaikan suku bunga mengikuti kenaikan suku bunga rujukan The Fed untuk memengaruhi keputusan investor tidak bisa dilanjutkan. Dapat diduga pelemahan nilai tukar mata uang disertai adanya faktor selain perkembangan eksternal.
Kepanikan dan komunikasi
Melihat pola pergerakan, depresiasi rupiah saat ini dapat disebabkan oleh perkembangan eksternal yang diikuti dengan efek kepanikan. Efek kepanikan disebabkan kekhawatiran dunia usaha untuk pembiayaan bahan baku impor dan jatuh tempo pelunasan kewajiban dalam jangka pendek. Depresiasi rupiah pun terjadi dalam fluktuasi yang tidak wajar, bahkan terhadap mata uang lain. Efek kepanikan pernah terjadi pada periode akhir 1997 dan awal 1998.
Kekhawatiran hanya dapat diatasi dengan penjelasan bank sentral yang meyakinkan atas keseimbangan atau fundamental nilai rupiah. Komunikasi untuk menyampaikan informasi termasuk mengenai kekuatan cadangan devisa dan pergerakan investasi portofolio yang berada dalam pengamatan BI.
Dengan langkah komunikasi yang lebih baik, diharapkan dalam jangka pendek tidak perlu terjadi lagi kenaikan suku bunga meski The Fed menaikkan suku bunga rujukan. Dengan inflasi yang masih terkendali, kenaikan suku bunga secara beruntun akan mengganggu pertumbuhan ekonomi yang sudah melambat.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar