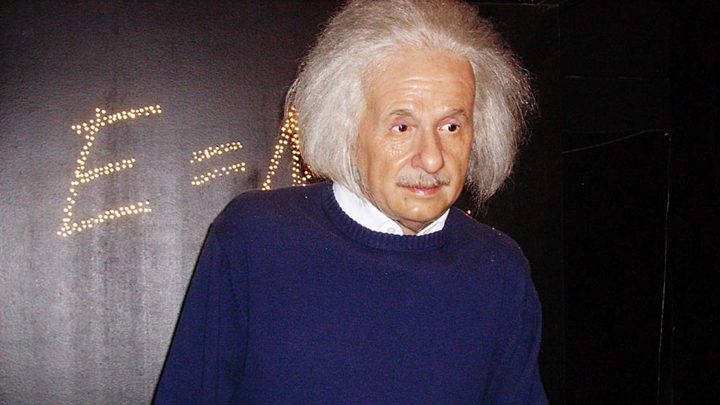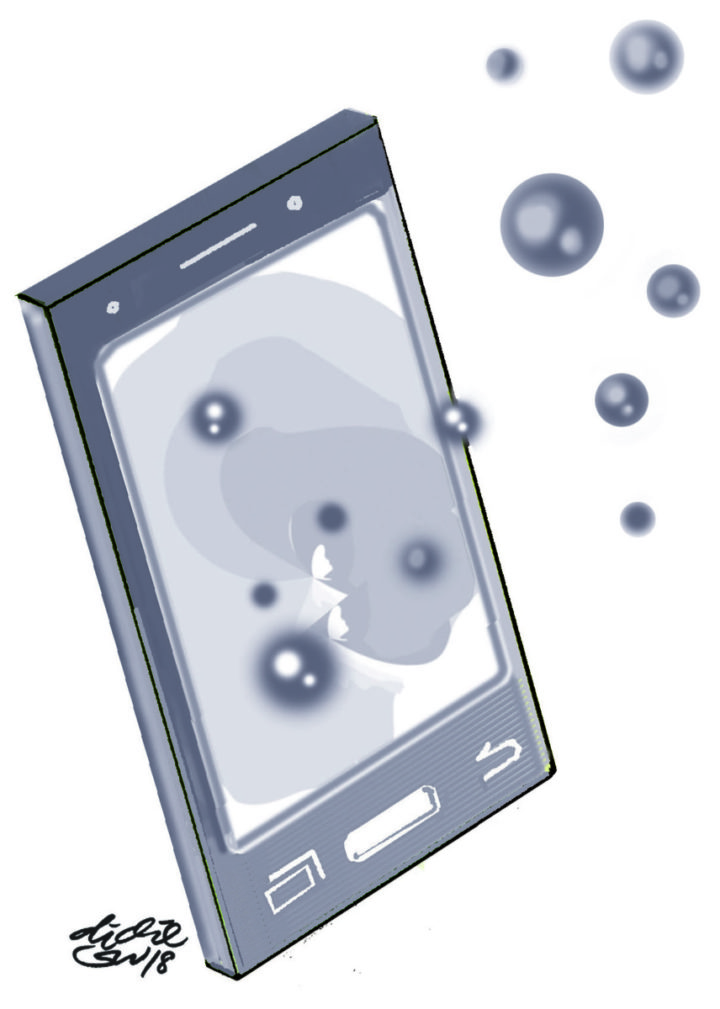Laku pangastuti terutama di tengah gejolak "tahun politik" baru bisa ampuh jika kita memahami genealogi termutakhir dari laku sura dira.
Satu sumber penting dari genealogi demikian diberikan oleh Giovanni Sartori. Pada tulisan "Video-Politics and Video-Democracy" (1994), Sartori melakukan refleksi filosofis yang andal. Dinyatakannya bahwa status kemanusiaan kita telah tergelincir dari sifat homo sapiens ke sifat homo videns. Lewat meluasnya adiksi pada televisi, dia sudah mengantisipasi akselerasi kemerosotan homo sapiens lantaran revolusi media sosial satu dasawarsa kemudian.
Sartori menguraikan bahwa homo sapiens bersaksi atas dunia yang disimaknya dengan modal akal budi, sedangkan homo videns bersaksi atas dunia yang ditontonnya semata dengan naluri. Homo videns adalah makhluk produk televisi yang jiwanya "tak lagi bekerja dengan konsep-konsep, dengan pandangan-pandangan abstrak, tetapi dengan imaji-imaji terberi". Beda dengan homo sapiens, mentalitas homo videns tak kuasa membaca hal-hal hingga di balik atau di seberang imaji-imaji itu.
Homo videns sebagai satu versi manusia modern hanya mampu "menonton", tak mampu "menyimak". Dia tak lagi sanggup memahami aneka relasi eksistensial, apalagi mencapai abstraksi universal dan komprehensif. Lantaran mentalnya mengerdil, dia bereaksi terhadap dunia sekitarnya kembali hanya secara naluriah. Serbuan imaji-imaji tanpa batas dan saringan telah menumpulkan daya pikir manusia terkini dan membuat perilaku mereka kembali sulit dibedakan dari perilaku manusia terkuno.
Pada saat-saat tanjakan kontestasi politik, bacaan orisinal Sartori ini bisa menjadi penjelas keluasan dan kedalaman ranah sura dira yang ditimbulkan oleh manusia homo videns serta perkalian negativitasnya. Terutama degradasi dari homo sapiens ke homo videns—dari manusia yang sanggup "membaca" ke manusia yang hanya bisa "menonton"—inilah yang memarakkan rantai laku sura dira yang kini juga cenderung merubung bangsa kita.
Kini homo videns bisa disebut sebagai sumber utama politisasi agama, fanatisme, populisme, fundamentalisme, radikalisme, politik identitas, fabrikasi hoaks, dan waham "pasca-kebenaran (post truth)". Begitu pula miopia, prasangka, laku grusa-grusu, sifat rawan fobia, ucapan temperamental, dalih-dalih ad hoc yang tak bisa dipertanggungjawabkan, serta segala wacana vulgar dan tindakan hasil pikiran pendek atau pretensi monopoli kebenaran. Dalam kontestasi politik, belasan laku sura dira ini hadir bersisian, saling bersenyawa, sambung menyambung mempertebal kegelapan jiwa homo videns.
Semua laku buruk itu pada hakikatnya tersungkup dalam sifat egosentrisme eskapis, yang lahir dari kontradiksi antara keniscayaan untuk bertahan hidup dan ketakmampuan mencerna atau merundingkan hal ihwal di seberang tumpuan ego. Inilah yang melahirkan praksis di mana segenap yang benar atau bajik tiada hentinya dipelintir. Memakai istilah keren yang menipu seolah hal baru, waham "pasca-kebenaran" hanyalah alias dari pelintiran kebenaran, sama halnya "pasca-modernisme" pelintiran modernisme.
Bermula dari menolak tiap otoritas mapan dan narasi besar, dua-duanya jadinya menolak pengukuhan otoritas dan narasi apa pun. Sulit dibedakan dari sofisme Yunani Purba, ia menyuburkan pelbagai laku dan pandangan liar, anarkisme, primitivisme, bahkan selalu siap berpilin praktis dengan semua laku benci, epidemik korupsi, dan sikap anti keadaban.
Sudah pasti kebencian antarkelompok politik akan mudah marak dan merajalela sebab di tengah keniscayaan berinteraksi dalam banjir informasi, cakrawala mayoritas kelompok selaku homo videns terpenjara pada kekeringan dunia imaji mereka sendiri. Yang berlaku di sini mungkin adalah perpaduan antara apa yang disebut Nietzsche hawa nafsu untuk berkuasa (Wille zur Macht) dan "naluri hewan kelompok" (Herdentrieb). Tak mampu atau tak sudi saling menyimak, di sini tiap kelompok pun sama hausnya akan harta dan kekuasaan dan sama terpanggilnya pada laku pongah dan kekerasan.
Lantaran tiap imaji pada diri tiap homo videns hanya dilihat sebagaimana yang terberi, kebenaran sebagai suatu konsep yang reflektif-refleksif mustahil dicapai. Di sini mentalitas homo videns kembali ke taraf termentah, yaitu dalam status alam hewani (the state of nature). Tangkapan "kebenaran" lintas ataupun intra-kelompok atas suatu masalah mengalami multiplisitas kacau yang, sesuai dengan sifat dunia hewani, semuanya bersifat ad hoc, arbitrer, dan saling tolak. Begitu ia hendak direlasikan atau dijadikan alat penghantam lawan dalam pergulatan yang saling menegasikan, ia pun meniscayakan laku pelintar-pelintiran kebenaran.
Paham dan kerinduan perihal kesebangsaan, kesemanusiaan, apalagi kesemestaan persaudaraan tak lagi dipahami apalagi diperlukan. Telah dicampakkan maxim Immanuel Kant bahwa kebajikan suatu tindakan mestilah diukur dari potensi validitas universalnya. Dalam kondisi demikian, pasti maraklah laku homo homini lupus atau, dalam ungkapan Bugis, ade sianre bale—laku saling memangsa seperti segenap ikan dalam samudra. Sebab bagi hewan kelompok mana pun, yang jadi tujuan hanyalah bagaimana mematikan lawan demi merebut tiap bentuk kekayaan ataupun tiap ruang kekuasaan.
Bangsa kita beruntung memiliki banyak pepatah hikmat dengan kandungan luhur universal. Dari kultur Jawa, kita antara lain bersua dengan sura dira jayaningrat lebur dening pangastuti yang bermakna bahwa segenap laku angkara akan lebur oleh laku kasih, lembut, bajik, dan sabar. Empat kata penunjuk kemuliaan itu terangkum dalam kata pangastuti. Sulit bagi kita untuk tidak menangkap kata pangastuti di luar pancaran cahaya iman.
Saya percaya bahwa laku pangastuti sejati hanya bisa lahir dari keterlatihan dalam amalan pembersih kalbu, dari nurani bening berkat ketertempaan di alam hening—dari jiwa yang selalu rindu pada swara ing asepi yang dulu juga dirujuk Clifford Geertz. Sebab, di situlah manusia melebur segala keangkuhannya di depan Zat Yang Maha Menggetarkan. Nabi Muhammad sendiri, yang dipercayai umatnya sebagai paragon budi pekerti, adalah seorang petapa, di dalam ataupun di luar goa. Umumnya umat Islam percaya bahwa Allah-lah pemilik termaha segala jenis keutamaan yang terdeteksi rasa dan rasio, termasuk sifat Kasih, Lembut, Bajik, dan Sabar. Dan mahkota dari progresi Muslim-mukmin-muhsin dan segenap manusia suci adalah laku pangastuti.
Al Quran sangat menekankan pentingnya menjelajahi dan menyimak aneka peradaban lintas zaman dan benua. Ini berarti pemuliaan laku menuntut ilmu dan orang berilmu. Idealnya tak lain agar homo sapiens tetap homo sapiens—makhluk berakal budi yang menyadari dan menghidupi diri sebagai makhluk cahaya yang terus menyongsong Sang Maha Cahaya.
Wacana politik tak bermutu
Laku pangastuti sarat simak dan sarat kasih itulah yang paling kita butuhkan di Tanah Air, lebih-lebih di musim tanjakan kontestasi politik. Kini belasan laku politik sura dira pun terhela ke dalam aneka wacana politik bermutu rendah. Pada momen kontestasi politik yang sejatinya adalah perhelatan nasion-demokrasi, yang digalakkan justru politik identitas. Wacana buruk juga tecermin pada laku meniru- niru Donald Trump yang kian mempertajam perpecahan bangsa Amerika dan merawankan tatanan dunia, apalagi dengan meneriakkan "Yang penting kau menang, bagaimanapun caranya".
Idem ditto adalah rendahnya mutu kampanye di bidang ekonomi. Yang dituju adalah faset-faset atau soal-soal dalam bentuknya yang paling vulgar dan mentah, suapan untuk populisme vulgar-mentah manusia-manusia homo videns. Tak tampak usaha untuk tajam dan utuh menyimak masalah. Tak disorot ancaman kembar mahabiang termutakhir dari kesenjangan ekonomi, yaitu oligarki dan neoliberalisme. Jika ini tak tegas-cerdas diantisipasi, kembar celaka itu akan menggiring kita jadi kere dalam cengkeraman totalitarianisme yang lambat laun akan membunuh nasion-demokrasi kita sekaligus, termasuk ideal-ideal yang paling kita junjung dalam cita-cita kemerdekaan.
Membuka mata kita dari kepercayaan buta pada pasar, Noam Chomsky menegaskan dalam Profit Over People (1999), bahwa "hampir selalu pasar tidak bersifat kompetitif". Oligarki dan tiap perusahaan raksasa meraup keuntungan serakah semaunya. "Mereka," tulis Robert W McChesney, "adalah organisasi totaliter, yang berkiprah pada jalur-jalur nondemokratis." Itu "sangat menggerogoti kemampuan kita membina masyarakat demokratis". Sepak terjang mereka yang maha memiskinkan lebih-lebih lagi berkontribusi menyebarkan pelbagai laku sura dira ke seluruh lapisan masyarakat.
Kita juga perlu mempertanyakan berlanjut-tidaknya imposisi kebijakan dualisme ekonomi kolonial ke dalam perekonomian nasional kita. Kebijakan dualisme inilah yang dulu disanjung De Kat Angelino (1931) dan JH Boeke (1953) atau yang dibongkar JS Furnivall (1939). Ini pun mahabiang kesenjangan ekonomi. Dari artikel cemerlang Ben Anderson, "Old State, New Society: Indonesia's New Order in Comparative Historical Perspective" (1981), kita juga tahu bahwa sebagaimana Orde Baru mengadopsi model kebijakan politik Hindia Belanda, ia pun mengadopsi model kebijakan ekonominya.
Bermula dari sistem ekonomi kolonial, pelaku ekonomi besar di sektor perkotaan dan/atau modern terus diperkaya sedang pelaku ekonomi kecil di sektor perdesaan dan/atau tradisional—lokus mayoritas kita—terus dimiskinkan. Jika betul, ini kudu mutlak diakhiri. Begitu pun pricing policy asimetris kota vs desa, aneka permainan ekspor-impor yang selalu merugikan petani, dan aneka distorsi, konversi, serta diskrepansi alokasi lahan terutama oleh para penghalal cara di kalangan pengembang dan pemilik perkebunan. Juga rangkaian proyek reklamasi pantai pengundang mahabencana lingkungan hampir di seluruh wilayah Tanah Air. Kebijakan ekonomi kolonial Orde Baru inilah penyebab loncatan eksponensial dari ketimpangan penguasaan aset ekonomi, khususnya lahan bangsa kita.
Di atas semuanya, kita menghendaki kebebasan dari obsesi pada pertumbuhan yang justru lebih banyak memiskinkan rakyat. Joseph Stiglitz (2003), misalnya, menganjurkan rangkaian kebijakan ekonomi cerdas penyusut kemiskinan yang sekaligus menaikkan pertumbuhan. Sebelumnya, preskripsi senada telah disampaikan Amartya Sen (1999): "Penyingkiran aneka bentuk rantai kemiskinan itulah substansi pembangunan".
Sulit untuk tak mengindahkan suara profetis Karl Marx bahwa di depan ofensif akumulasi modal segala sesuatu akan "menguap ke udara". Tiap sarana media sosial adalah juga alat ofensif akumulasi modal—pembiak homo videns. Kian membiak homo videns, kian santer pula akumulasi modal. Di depan hukum besi ini, seluruh laku sura dira di pelbagai bidang ekonomi-politik, termasuk re-boost perbudakan seks dan perdagangan manusia, adalah jalan untuk "menguap di udara".
Dalam bahasa Marx (Capital I, 1967), "Vampir tak pernah melepaskan cengkeramannya atas manusia selama pada dirinya masih ada otot, saraf, dan tetesan darah untuk dieksploitasi". Kian tinggi tensi kontestasi politik, kian perlu kita menjaganya dari aneka distorsi. Kian kencang kampanye picik dengan kacamata kuda, kian perlu pula kita menjernihkan nalar dan memperluas cakrawala. Kian merajalela laku muslihat angkara, kian perlu kita bertolak dari alam hening. Kian kuat fiksasi pemberhalaan pada harta dan kekuasaan, kian perlu kita membebaskan jiwa dari naluri hewani.
Singkatnya, kian sura dira, kian pangastuti. Tentu dengan dua piwanti. Pertama, kendati menjadi pembiak terbesar homo videns, televisi dan/atau medsos bukanlah pembiak tunggal dari laku sura dira di zaman modern. Kapan pun, kebiadaban memang selalu membayangi peradaban. Kedua, laku pangastuti bukan panasea, juga bukan solusi tanpa syarat atas seluruh laku sura dira, terutama menyangkut kejahatan luar biasa. Ia sungguh harus ditopang dengan setegar mungkin menegakkan negara hukum.