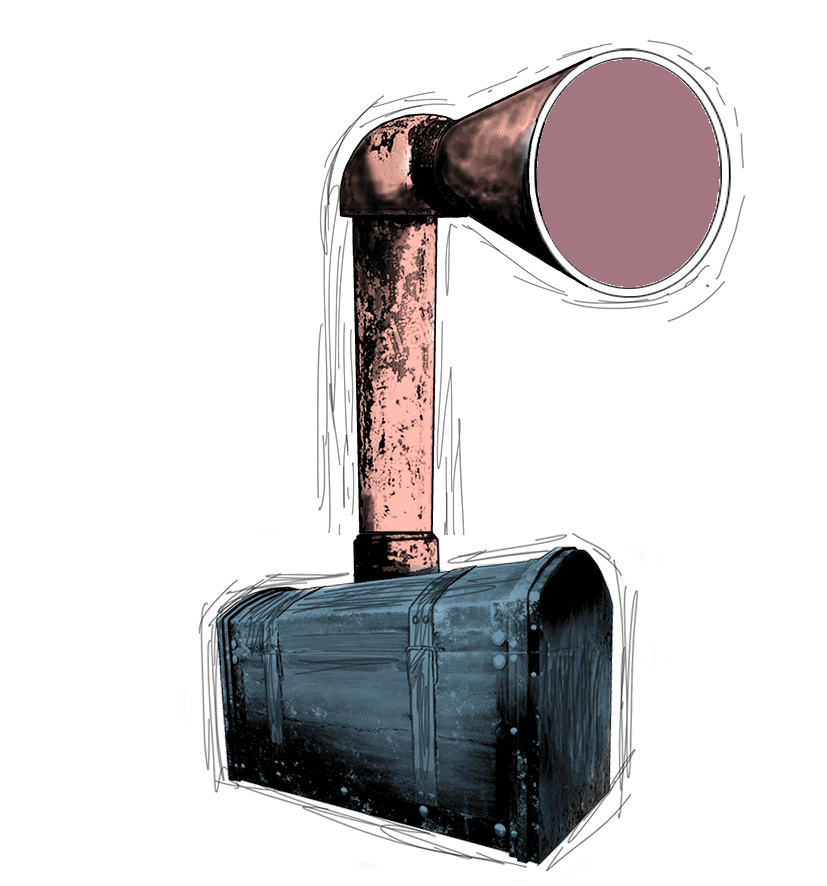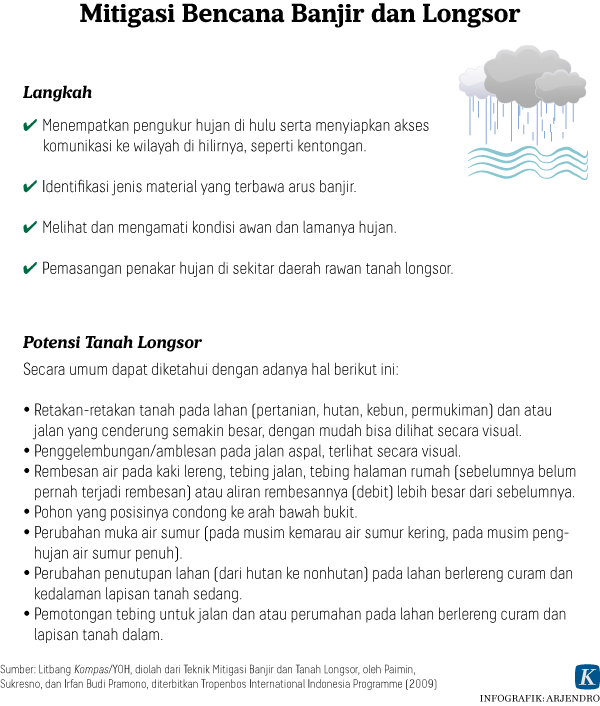Seiring dengan semakin tingginya target pajak dalam APBN 2018, Direktorat Jenderal Pajak diyakini akan mengintensifkan pemungutan dan penegakan hukum di bidang perpajakan.
Apalagi setelah selesainya pelaksanaan amnesti (tax amnesty) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, pemerintah telah menerbitkan PP No 36/2017 tanggal 6 September 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan Tertentu berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan.
Yang menjadi sasaran dari pelaksanaan PP No 36/2017 tersebut adalah para wajib pajak (WP) yang telah mengikuti program pengampunan pajak atau yang belum mengikuti dan belum atau kurang melapor semua harta bersih. Untuk melengkapi regulasi dalam pemungutan pajak pasca- amnesti tersebut juga telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 tanggal 17 November 2017 tentang Pelaksanaan UU No 11/2016 tentang Pengampunan Pajak.
Pokok-pokok dalam regulasi-regulasi terkait pengampunan pajak tersebut di atas mengatur mengenai bagaimana
perlakuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap WP, baik yang sudah mengikuti program pengampunan pajak maupun yang belum, jika DJP menemukan harta bersih (harta dikurangi utang) yang tidak atau kurang dilaporkan. Terhadap WP yang sudah mengikuti pengampunan pajak kemudian DJP menemukan harta bersih yang belum atau kurang diungkap dalam surat pernyataan, maka harta tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan yang akan ditagih dengan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB).
Tambahan penghasilan tersebut selanjutnya akan dikenai Pajak Penghasilan final dengan tarif sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 36 Tahun 2017 ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan 200 persen sesuai dengan ketentuan UU Pengampunan Pajak. Sementara terhadap WP yang tidak mengikuti program pengampunan pajak, jika DJP menemukan harta bersih yang belum dilaporkan di dalam SPT Tahunan PPh maka tambahan harta tersebut akan ditagih dengan SKPKB dengan mengenakan tarif Pajak Penghasilan final sesuai dengan Pasal 4 PP No 36/2017 ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 persen sebulan paling lama 24 bulan sesuai UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Sengketa pajak amnesti pajak
Apabila atas SKPKB tersebut WP menyatakan tidak setuju/keberatan, maka akan timbul sengketa pajak. Seandainya sengketa pajak tersebut berlanjut sampai ke pengadilan, maka upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh WP? Menurut Pasal 19 UU Pengampunan Pajak, "Segala sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan UU Pengampunan Pajak hanya dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan, dan gugatan tersebut hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak."
Lebih lanjut di dalam Pasal 46 Ayat 3 PMK No 165/2017 disebutkan, penyelesaian sengketa atas penerbitan SKPKB terkait UU Pengampunan Pajak tersebut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ini berarti terhadap sengketa pajak atas penerbitan SKPKB dalam rangka pelaksanaan UU Pengampunan Pajak, upaya hukumnya adalah melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Pajak.
Sementara menurut hukum acara di Pengadilan Pajak (Pasal 31 UU No 14/2002 tentang Pengadilan Pajak) dikenal ada dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu melalui banding atau gugatan. Proses pengajuan banding dan gugatan ke Pengadilan Pajak mengikuti ketentuan yang ada dalam UU No 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 16/2009 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan (UU KUP).
Apabila WP tidak setuju atas isi/materi surat ketetapan pajak seperti ketidaksetujuan terhadap besarnya jumlah pajak, maka WP dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak (Pasal 25 dan 26 UU KUP) dan jika surat keberatannya ditolak serta DJP menerbitkan keputusan penolakan, maka keputusan tersebut menjadi dasar pengajuan banding ke Pengadilan Pajak (Pasal 27 UU KUP).
Sementara yang merupakan obyek gugatan diatur dalam Pasal 23 Ayat 2 UU KUP, yaitu: (a) atas pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang; (b) keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak; (c) keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 Ayat 1 dan Pasal 26; atau (d) penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Dengan demikian, baik menurut UU Pengadilan Pajak maupun UU KUP, jika sengketa pajak terkait dengan isi/materi SKPKB, setelah adanya keputusan penolakan keberatan dari DJP, maka upaya hukumnya adalah banding, bukan melalui gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 UU Pengampunan Pajak.
Perbaikan regulasi
Guna mengatasi problematika hukum dalam penyelesaian sengketa pajak terkait pelaksanaan aturan pengampunan pajak tersebut di atas, diperlukan adanya perbaikan terhadap aturan-aturan yang terkait. Langkah yang paling baik adalah melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 19 UU Pengampunan Pajak.
Susunan redaksional Pasal 19 Ayat 1 UU Pengampunan Pajak sebaiknya diubah menjadi, "Segala sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang ini dapat diselesaikan melalui pengajuan Banding atau Gugatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan". Dengan demikian, ketentuan tersebut akan sejalan dengan UU Pengadilan Pajak dan UU KUP.
Sepanjang sengketa pajak terkait dengan isi/materi surat ketetapan pajak, maka upaya hukumnya melalui banding, sedangkan jika yang jadi sengketa adalah prosedur penerbitan atau aspek pemenuhan ketentuan formal penerbitan surat ketetapan pajak, maka upaya hukumnya dilakukan melalui pengajuan gugatan.
Namun, jika UU Pengampunan Pajak tidak dikehendaki untuk direvisi, yang berarti penyelesaian sengketa atas pelaksanaan UU Pengampunan Pajak tetap melalui jalur gugatan sesuai Pasal 19 UU Pengampunan Pajak, maka apakah hal itu dimungkinkan? Satu-satunya peluang untuk dapat mengajukan gugatan atas terbitnya suatu surat ketetapan pajak dan selama ini memang dalam praktiknya banyak ditempuh oleh WP adalah melalui Pasal 36 Ayat 1 Huruf b UU KUP.
Banyak WP lebih memilih menggunakan ketentuan Pasal 36 Ayat 1 b UU KUP daripada proses keberatan sesuai Pasal
25 UU KUP karena batas waktu penyelesaian permohonannya lebih cepat, yaitu ditentukan paling lama enam bulan. Sementara jika menggunakan mekanisme pengajuan keberatan, batas waktu penyelesaiannya lebih lama, yaitu paling lama 12 bulan.
Ketentuan Pasal 36 Ayat 1 Huruf b UU KUP berbunyi, "Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar."
Pasal 36 Ayat 1 Huruf b UU KUP ini dapat menjadi "jalan" menuju Pasal 23 Ayat 2 UU KUP yang merupakan "pintu masuk" pengajuan gugatan ke Pengadilan Pajak. Apabila atas suatu SKPKB, WP tidak mengajukan keberatan sesuai Pasal 25 UU KUP tetapi memilih mengajukan permohonan pembatalan SKPKB melalui Pasal 36 Ayat 1 b UU KUP, maka jika permohonannya ditolak, keputusan penolakan tersebut menjadi dasar pengajuan gugatan ke Pengadilan Pajak.
Dasar ketentuannya adalah Pasal 23 Ayat 2 Huruf C UU KUP yang berbunyi, "Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 Ayat 1 dan Pasal 26, hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak".
Namun, ketentuan Pasal 36 Ayat 1 b UU KUP ini dalam praktiknya sering diperdebatkan karena dianggap "tumpang tindih" dengan mekanisme pembatalan surat ketetapan pajak melalui pengajuan keberatan sesuai Pasal 25 dan Pasal 26 UU KUP. UU KUP tidak memberikan kriteria dan batasan yang jelas dalam hal apa pembatalan suatu surat ketetapan pajak diajukan melalui pasal ini dan apa perbedaannya dengan mekanisme pengajuan keberatan atas surat ketetapan pajak yang diatur dalam Pasal 25 UU KUP.
Di dalam penjelasan Pasal 36 Ayat 1 Huruf b UU KUP antara lain berbunyi, "Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi."
Sebenarnya isi penjelasan pasal sedemikian hanya menyebutkan suatu contoh dalam hal apa ketentuan Pasal 36 Ayat 1 b dapat digunakan, yaitu digunakan jika WP tidak dapat menempuh prosedur keberatan sesuai Pasal 25 UU KUP karena terdapat persoalan formal pengajuan keberatan yang tidak dapat dipenuhi oleh WP, sementara secara material/substansi sebenarnya WP sudah benar sehingga memang surat ketetapan pajak itu tak benar. Untuk itu, dengan alasan keadilan, Dirjen Pajak dengan kewenangannya dapat membatalkan surat ketetapan pajak.
Memori penjelasan pasal tersebut sebenarnya hanya merujuk pada suatu contoh saja dan tidak menyebutkan suatu norma hukum tertentu tentang kriteria dan persyaratan pengajuan permohonan secara jelas. Dalam praktiknya kemudian pasal tersebut ditafsirkan secara meluas menjadi segala sesuatu yang menyangkut aspek formal atau prosedur penetapan/penerbitan surat ketetapan pajak yang dianggap tidak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, maka upaya hukumnya ditempuh melalui Pasal 36 Ayat 1 b UU KUP.
Selain itu, ada juga pandangan yang menyatakan bahwa penggunaan Pasal 36 UU KUP merupakan wewenang penuh Dirjen Pajak, di mana WP dapat memohon pembatalan surat ketetapan pajak dengan mengharapkan "kemurahan dan kebaikan hati" (clemency) Dirjen Pajak. Padahal, dalam kondisi saat ini kecil kemungkinan Dirjen Pajak bersedia membatalkan suatu surat ketetapan pajak tanpa adanya alasan-alasan yuridis yang cukup, sekalipun dengan alasan keadilan.
Mengingat saat ini sedang berlangsung pembahasan revisi UU KUP, sebaiknya ketentuan Pasal 36 Ayat 1 b UU KUP ini perlu direvitalisasi agar jelas kriteria dan ruang lingkupnya sehingga menjadi jelas pula perbedaannya dengan mekanisme keberatan yang diatur dalam Pasal 25 dan 26 UU KUP. Dalam konteks pelaksanaan UU Pengampunan Pajak, perlu pula dipertimbangkan dalam revisi UU KUP apakah khusus atas SKPKB yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak dapat diselesaikan melalui Pasal 36 Ayat 1 b UU KUP.
Penyelesaian sengketa SKPKB yang terkait pengampunan pajak semestinya lebih sederhana prosesnya karena prinsipnya hanya mencocokkan data harta kekayaan yang dilaporkan oleh WP dengan data harta yang dimiliki DJP dan semestinya tidak diperlukan proses pemeriksaan dan pembuktian pembukuan/pencatatan yang rumit seperti halnya penyelesaian keberatan menurut Pasal 26 UU KUP.