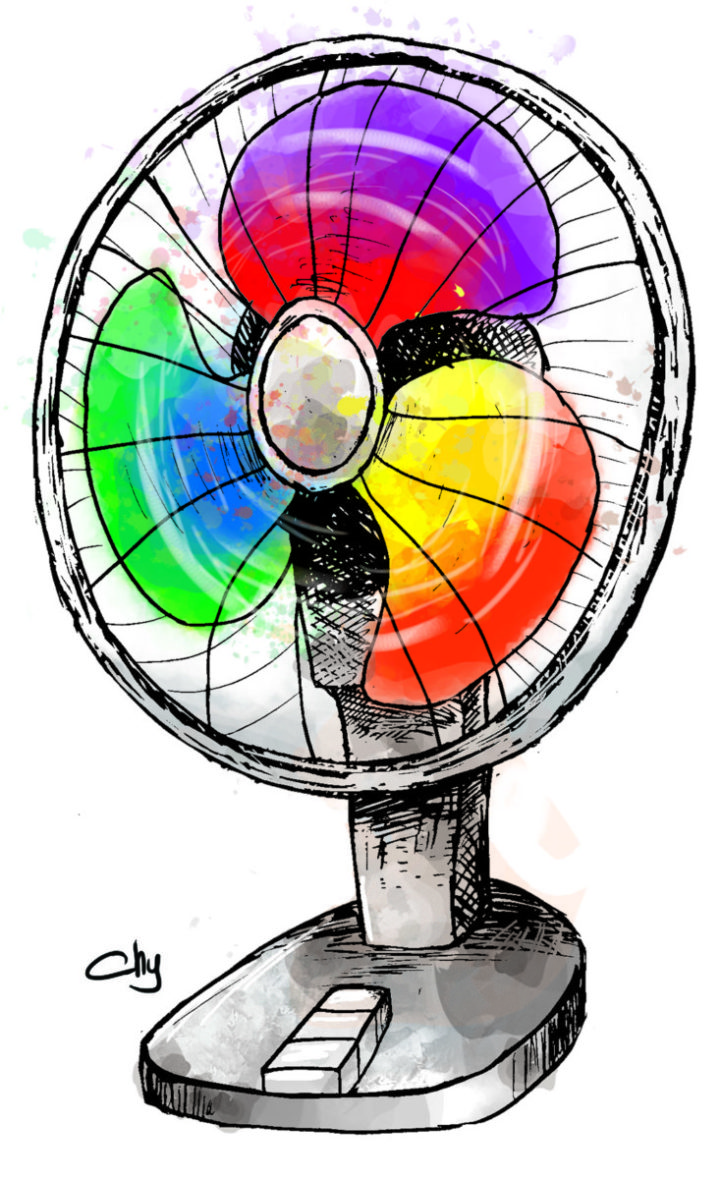
Jelang Pemilu 2019 tensi politik dirasakan semakin memanas. Tidak hanya di kalangan elite, tetapi juga merambat hingga akar rumput (masyarakat).
Jika tidak bijak menyikapi perbedaan dalam kontestasi politik, dikhawatirkan akan menimbulkan disharmonisasi—bahkan disorganisasi dan disintegrasi—dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
Kondisi disharmoni ini sebenarnya sudah berlangsung sejak Pemilu 2014 yang berlanjut dengan perhelatan gelombang pilkada serentak. Ekspresi perbedaan politik (dukungan dan ketidakpuasan) kerap disampaikan secara agresif dan menjatuhkan. Hal ini diperparah dengan penggunaan isu atau sentimen SARA yang menyulut kontroversi dan emosi.
Sebagai contoh yang paling menguras emosi adalah kasus penistaan agama jelang Pilkada DKI. Kasus-kasus lain, seperti persekusi dan penolakan ulama dan tokoh masyarakat, kriminalisasi ulama, penyerangan ulama oleh "orang gila", menambah ketegangan di dalam masyarakat. Disharmoni di media sosial jauh lebih heboh dan panas. Media sosial (medsos) gaduh dan riuh rendah dengan perang pernyataan, meme, tagar, saling serang dan sindir, bahkan tidak sedikit yang bernuansa ujaran kebencian (hate speech) dan berita bohong atau fitnah (hoax). Semuanya jika kita amati bermuara pada polarisasi dukungan politik elektoral pemilu.
Dalam beberapa pekan ini misalnya terjadi gelombang penolakan dan pembubaran deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di sejumlah daerah. Pro kontra mencuat di antara dua pihak. Di satu sisi, kelompok gerakan #2019GantiPresiden merasa apa yang dilakukan merupakan ekspresi kebebasan berkumpul dan berpendapat yang dijamin konstitusi dan UU sehingga segala bentuk penolakan dimaknai sebagai pengekangan kebebasan berekspresi. Di sisi lain, kelompok kontra menilai gerakan ini mengganggu kerukunan dan keharmonisan masyarakat karena dipandang menyerang dan tak menghormati presiden berkuasa, menyebarkan kebencian, memecah belah masyarakat, bentuk kampanye hitam, bahkan ada yang menyebutnya sebagai perbuatan makar yang berpotensi gangguan keamanan dan stabilitas politik/pemerintahan.
Mencari konsensus
Dalam setiap perbedaan tajam yang mengancam harmonisasi, keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa sudah semestinya kita berusaha mencari konsensus atau titik temu—yang berangkat dari kesadaran untuk menjaga kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
Reformasi 1998 membawa angin kebebasan dan peningkatan partisipasi rakyat dalam berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita menerima demokrasi sebagai sistem bernegara dan bersamaan dengan itu memberikan jaminan kebebasan individu dan kelompok dalam melaksanakan hak dan kebebasan sebagai warga negara. UUD 1945 hasil perubahan mengintroduksi banyak pasal dan ayat tambahan tentang hak asasi manusia (HAM). Bahkan, UUD menghadirkan bab tersendiri tentang HAM (Bab XA) mulai dari Pasal 28A hingga Pasal 28J. Hal ini menunjukkan betapa negara memperkuat penghormatan dan perlindungan atas hak asasi warga negara.
Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sendiri dijamin oleh konstitusi Pasal 28, yang ditegaskan kembali pada Pasal 28E Ayat (3): "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Secara operasional, jaminan atas hak itu ditegaskan dan dijabarkan dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Pertanyaannya, apakah dalam melaksanakan hak asasi bisa dilakukan dengan sebebas-bebasnya? UUD 1945 nyatanya memberikan batasan yang jelas pada Pasal 28J. Batasannya adalah penghormatan terhadap HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Ayat 1). Selain itu, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Ayat 2).
Konstruksi pasal-pasal HAM dalam konstitusi tersebut menghendaki adanya konsensus (titik temu) yang semestinya dipedomani bersama oleh seluruh warga negara bahwa dalam melaksanakan hak dan kebebasan menganut prinsip: 1) jaminan perlindungan atas hak asasi manusia setiap orang; 2) penghormatan atas hak asasi orang lain; 3) pelaksanaan hak dan kebebasan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Diperlukan kebesaran jiwa dan kelapangan hati dalam melaksanakan hak dan kebebasan serta dalam memberikan keleluasaan bagi orang lain dalam melaksanakan hak dan kebebasannya—sepanjang hal itu dilakukan secara bertanggung jawab dan dalam koridor hukum dan aturan.
Dalam konteks deklarasi gerakan #2019GantiPresiden atau #2019TetapJokowi, misalnya, sepanjang dilakukan secara taat aturan, semestinya setiap warga negara dapat menghormati dan memberikan ruang sebagai bentuk ekspresi kebebasan yang dijamin oleh konstitusi. Sikap sekelompok orang menghalang-halangi, membubarkan, atau memersekusi gerakan itu tentu tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan semangat kebebasan dan HAM dalam konstitusi.
Seseorang atau sekelompok orang baru dapat memperkarakan jika ditemukan tindakan yang melanggar hukum (tindak pidana). Tindak pidana itu dapat dilaporkan dan diproses hukum melalui prosedur hukum yang tersedia alias tidak main hakim sendiri karena konstitusi tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip dalam negara hukum seseorang tidak boleh dihukum tentang apa yang dikatakan, apalagi yang dipikirkannya. Bahkan, ketika ada organisasi yang menyatakan ingin mendirikan negara merdeka yang terpisah dari NKRI sekalipun, negara belum bisa bertindak sampai ada ancaman nyata (real threat) seperti mengangkat senjata.
Sikap tepat aparat
Dalam kondisi pertentangan yang tajam dan disharmoni yang meluas di masyarakat, aparat keamanan (kepolisian) dihadapkan pada posisi yang dilematis: kerap ditekan sekaligus dipersalahkan saat melakukan tindakan kepolisian. Meski demikian, kita bisa memahami jika polisi akhirnya mengambil langkah untuk menghindari pecahnya konflik fisik komunal. Polisi dihadapkan pada perannya antara kepentingan kewajiban (negara) dan hak (warga negara) di satu sisi dan secara simultan ada pertentangan hak antar warga negara.
Di sinilah letak dilematisnya tindakan kepolisian yang dirasakan bukan hanya di Indonesia, melainkan secara universal. Di satu sisi, jika polisi mengutamakan kewajibannya menjaga ketertiban, tetapi berakibat adanya warga negara yang hak-hak asasinya terlanggar (terhalangi), berarti oknum polisi itu akan berada di bawah ancaman pelanggaran HAM. Bahkan, Pasal 18 UU No 9 Tahun 1998 memberikan ancaman pidana (kejahatan) bagi setiap perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Demikian pula halnya jika polisi bermaksud membela/ menjunjung hak suatu kelompok, tetapi berakibat ada kelompok lain yang terlanggar hak asasinya. Maka, di sini polisi dituntut untuk mampu mempertimbangkan apakah benar ada kelompok yang haknya terlanggar (terinjak) atau sesungguhnya hanya kelompok lain yang berhak.
Dalam konteks pertarungan politik, seperti menghadapi dinamika pesta demokrasi yang sedang berlangsung akhir-akhir ini, jika polisi keliru dalam bertindak, akibatnya bukan hanya dirasakan polisi, melainkan bisa berdampak politik terutama bagi pasangan capres-cawapres. Polisi bisa terbawa arus politisasi yang jelas tidak baik bagi institusi Polri yang saat ini sedang giat menjaga dan mempromosikan netralitas dan independensinya.
Aparat dan pejabat yang sedang berkuasa atau dekat dengan kekuasaan harus menegaskan posisinya agar tidak gegabah dan membabi buta dalam melakukan tindakan yang bisa dipersepsi memihak pada pasangan calon tertentu atau bahkan "menzalimi" pasangan lainnya.
Kita semestinya menghentikan sikap "menzalimi" lawan politik karena yang demikian hanya akan menghasilkan dendam tak berkesudahan sampai anak cucu. Dendam politik sangat kontraproduktif bagi bangsa ini. Secara politik pihak yang kalah akan terus-menerus menggerogoti pihak yang menang. Jika itu terus berulang, kapan bangsa ini akan kembali seperti para pendahulu yang bersatu padu melawan ancaman penjajah dan meneriakkan kata "merdeka"?
Saya yakin tidak sedikit elite bangsa yang bersuara serupa dengan penulis. Kita berharap memiliki pemimpin yang lapang dada dan berjiwa besar. Tidak memanaskan suasana dengan saling hujat dan ujaran kebencian, sebaliknya turut "membela" lawan politiknya ketika disudutkan oleh pendukungnya dengan berita-berita yang tidak benar dan ujaran kebencian.
Berkaca pada negara yang telah matang dalam berdemokrasi, betapa pun panas persaingan politik para kandidat tetap bersikap obyektif—dan siapa pun pemenangnya diterima dengan sewajarnya dan biasa saja. Dalam hal ini, kita bisa belajar dari John McCain—rival Barack Obama pada pemilu Amerika Serikat tahun 2008, yang belum lama ini meninggal dunia. McCain secara terbuka membela Obama ketika saat kampanye pendukungnya menyebut Obama sebagai orang Arab dengan nada kebencian. McCain membela rivalnya itu dengan menegaskan bahwa Obama adalah warga negara AS, orang yang santun dan sayang keluarga, yang kebetulan mempunyai pemikiran yang beda soal isu fundamental. Maka, jangan takut jika nantinya Obama memenangi pemilihan. Inilah teladan yang baik dalam berkontestasi politik.
Kita semua berharap panasnya suhu politik tidak sampai mengganggu stabilitas nasional. Jangan sampai perbedaan preferensi politik menjadikan kita saling bermusuhan dan berkonflik sehingga terjadi perpecahan (disharmoni dan disintegrasi) di antara warga bangsa. Kita mendorong seluruh elite politik, terutama pasangan capres-cawapres, intensif bertemu dalam suasana kebersamaan (silaturahmi) dan merumuskan konsensus politik yang santun, teduh, dan bermartabat.
Konsensus untuk mengharamkan kampanye hitam, penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian. Lebih jauh, di antara pasangan capres dan cawapres serta elite politik turut aktif mengklarifikasi—bukan membiarkan atau malah menikmati—berita hoaks, ujaran kebencian, dan insinuasi atas lawan politiknya.
Pelukan hangat Jokowi-Prabowo yang diprakarsai Hanifan, peraih medali emas pencak silat dalam ajang Asian Games lalu, bisa menjadi momentum konsensus dari panasnya persaingan politik. Lebih lanjut, kita berharap tidak hanya berhenti di situ, tetapi berlanjut dengan pertemuan-pertemuan silaturahmi lainnya untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa persatuan dan kesatuan bangsa di atas segalanya. Jika hal itu dilakukan, penulis yakin disharmonisasi yang merebak akibat panasnya tensi politik tidak akan sampai membakar bangsa ini.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar